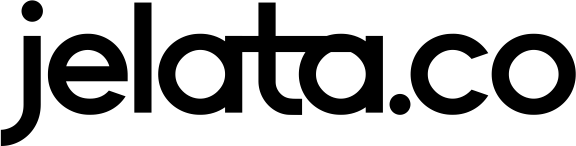1.
Setelah makan, dan menggenapi beberapa urusan, kau berangkat ke tempat pertunjukan; dan kau sadari, cukup sering menonton pertunjukan atau pameran dengan keadaan perut yang sudah terisi—meski tak kenyang. Sesampainya di sana, kau mendapati orang-orang menanti dimulai pertunjukan. Dan, tentu, kau terpukau keramaian semacam itu. Dan, terdengar pemberitahuan, pertunjukan hendak dimulai. Satu per satu penonton masuk; mencari tempat duduk dan posisi menonton yang nyaman. Dan, kau duduk di tepi-tengah, di dekat undakan. Di depan, ada Asita yang disorot terang lampu: spotlight di antara gelap panggung itu. Tangannya bergerak, jari-jarinya membuat semacam ombak. Adegan itu berlangsung cukup lama: menggenapi penonton yang masuk seluruhnya. Lalu, setelah mengangkat pandang sedikit lebih tinggi, kau pun dapati ketiga aktor lain ada di situ: terdiam berdiri dan menanti.
Sebuah tanda! Asita membuat gerakan lebih, gerakan dari sebuah pintu yang dibuka-terbuka; dan gerakan itu bergerak pada eksplorasi, pada suatu pembukaan diri. Sepasang matamu, tentu, amat terpukau pada tubuh dan gerak itu. Akan tetapi, bayang yang rebah itu, bayang dari tubuh Asita yang terkena lampu itu, bagimu, tak kalah mempesona. Suara suling terdengar telinga—membangun dan mempertebal atmosfer dan suasana. Ketiga orang di atas panggung, yaitu Tias, Pupuh, dan Ghani, bergerak pula; berjalan menuju ke sisi lainnya, menuju tangga turun—untuk bergabung dengan Asita. Mereka bertiga bergerak dengan lucu, berjalan dengan suatu gerak langkah menyeret. Dan Asita, di bawah, masihlah disorot lampu, masihlah menelusuri dan juga melaku sesuatu.
Lampu yang menyorot ketiga lainnya terasa memberi bobot lebih; dan mencipta pula bayang. Di beberapa titik, ketiganya berhenti; mengeksplorasi tangan sendiri. Mereka berjalan dengan perlahan; dan bayang pada dinding itu jadi lukisan-relief tubuh yang memberi bobot dramatik tersendiri. Lalu, mereka semua, pun Asita, jadi satu gerombolan, satu kesatuan. Keempatnya, dengan kostum yang serupa-senada, bergerak di dalam suatu komposisi yang laras; berjalan menyeret mencipta bunyi, bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Kemudian, di sisi panggung seberang, setelah sampai, mereka membentuk baris dua-dua. Musik, tentu, kau dengar dan rasa; dan kian tebal menggarisbawahi lakuan, juga tempo permainan.

Di sana, mereka tak hanya berjalan, berjalan di tempat; tetapi juga melaku gerak renang begitu serempak. Kemudian, keempatnya seperti berada dalam adegan bekerja: mengetik, mengergaji, menata batu, dan laku sejenis lainnya. Intensitas naik, dan naik; lalu, pada suatu titik, Ghani diinggal di sudut sendiri—Asita, Tias, dan Pupuh berjalan dengan teatrikal ke sisi panggung lainnya, ke sisi panggung sebelahnya. Tiga aktor itu diterangi lampu temaram; sedang Ghani mendapat spotlight-nya. Ia beradegan, ya, bila boleh menyebut demikian, tentang makan dan minum, besua dan bercengkrama, memakai-memilih pakaian dan berolah raga. Ia melakukan itu setelah memakai VR: memakai VR imajiner yang muncul dari gerak pentomimnya dan perpaduan dengan musik-suara. Ia mengeser layar—seperti di dunia masa depan. Ia beradegan demikian secara berulang dan berulang, berulang dan berulang. Rasa sakit dari pengulangan rutinitas itu tampak dari raut dan gerak tubuh Ghani: gerak pantomim yang lumrah itu terasa jadi berbobot lebih. Intensias semakin naik, dan diakhiri seperti robot yang dol. Lalu, Ghani bergabung dengan ketiga lainnya—yang ada di sisi sebelah . . .
Kemudian, sebuah komposisi dilaku kembali keempat aktor itu; dan kembali mengeskplorasi panggung; keserempakan. Adegan bergulang, jatuh, dan gerak-gerak ganjil dimunculkan. Lalu, ketiga aktor, Tias, Asita, dan Ghani, dengan gerak teaterikalnya, menaiki tangga ke panggung atas: meninggalkan Pupuh di panggung bawah. Dan, seperti sebelumnya, tiga yang lain disorot lampu temaram; sedang yang seorang, Pupuh, dalam hal ini, mendapat spotlight terang. Dan di saat seperti itu, kepalamu, yang rambutnya telah gondrong, dihinggapi tanya: kenapa fokusnya dibuat dua, kenapa dibagi begini rupa? Tentu, kau belum menemu jawab kala itu; dan lebih tenggelam menyaksi.
Musik berganti: mencipta ngeri. Dan Pupuh pun memunculkan gerak-gerak yang tak lumrah. “Ah, adakah gerak yang lumrah—ketika ketakutan?” Ia terbangun, berlari, menembus sesuatu, seperti seorang yang kabur dari penjaga; seperti seorang, atau malah sesuatu, yang berusaha bebas dari perburuan. Dadamu, melalui gerak dan bunyi itu, berhasil mendapat suatu perasaan tertentu; tapi kepalamu belum genap menemu: Pupuh ada di mana dan sebenarnya tengah apa? Namun, adegan dan aksi, di bagian itu, tentu, begitu memukaumu; dan kau jadi bertanya-tanya: Di kilau mata itu, apa yang dipandang sebenarnya, apa yang dilihatnya sampai ketaktutan, apa yang ada di mata aktor? Dan kau tak dapat lupa: bagaimana Pupuh menampar pipinya dengan kaki—dalam posisi semacam sila-yoga. Ah, pantomim, ternyata, bisa begini rupa! Suara sirine bergema, bergema…
Kemudian, Asita dan Ghani bergerak: turun. Dan, entah bagaimana, Asita, Ghani, dan Pupuh seperti menjelma satwa-satwa: tikus-tikus yang bercericit dan menyusup di celah dan loteng. Dan kau, itu kali, telah mendapati suatu pola: satu per satu aktor beraksi dengan di sela transisi yang menjadi jembatan dan pemecah kebosanan. Adegan tikus-tikus berebut sesuatu, makanan barangkali, begitu memukau, membuat matamu enggan berpaling; meski rasa penasaranmu, sebab telah menemu pola, jadi tergoda menyaksi sisi lain apa yang dilaku Tias di atas sana. Ah, musik kembali mengubah atmosfer; pun lampu menguatkan suatu dunia pula. Lalu, ketiganya, Asita, Ghani, dan Pupuh, berdiam di bawah; membiarkan Tias beradegan di atas.
Tias bersimpuh dan membuat adegan yang berkisar pada kain—dan pakaian. Di mula, tampak ia seperti tengah membuat kain dari benang: menenun. Dan saat menarik benang, tentu benang imajiner, kau terpukau: sepasang matamu seperti menyaksi, ada kemilau dari benang itu, ada sekilas seperti pada senar. Lalu, kain itu jadi; dan adegan berkisar pada kerja melilit: pada kerja menggulung dan mengendit. Posisi Tias yang berkisar antara duduk, simpuh, dan semacam rebah, memberimu ngeri dan horor tersendiri. Suara yang lirih kian mempertebal bobot adegan itu. Ia tampak terus melilit dan melilit, menggulung dan menggulung kain ke tubuhnya dengan berulang dan berulang. Tentu, kain itu imajiner; tak tampak di matamu yang penonton; tetapi, rasa sesak dan sakit itu amat terasa, terasa di tubuh dan dadamu. Lalu, adegan pun memuncak, memuncak: rasa sakit yang telak!

Dan seperti yang kau duga, sebab terbaca pola, transisi kembali dikerja, Ghani dan Puhpuh membuat lagi gerak dan berpindah dari bawah ke atas; demikian pula dengan Tias yang bangkit menuju suatu sisi. Di atas, lalu ada Ghani, Pupuh, dan Tias; dan di bawah, ada Asita. Asita menggerakkan jari-jemarinya seperti mendefinisi terbang; lalu membuat burung-burungan dari sepasang tangan; juga mengepak; dan perlahan menuju ke tengah. Kembali, tiga dalam terang-temaram; dan seorang dalam spotlight terang . . . Asita bergerak, di sepasang matamu, seperti dalam kerja menelusuri tentang membuka, terbang, berkelana, dan penelusuran itu sendiri. Dan kembali, selain pada gerak itu sendiri, kau terpukau pada bayang-bayang, pada bayang yang tampak dan muncul bersamaan dengan semua laku. Intensi kian naik, kian naik, tapi naik yang terasa liris, dan memberi suatu lembut yang ganjil. Lalu, tanpa genap benar kau sadar, aktor yang lain mulai memosisi, mulai menuju bagian sendiri-sendiri—
Keempat aktor itu, kini, beradegan bersama; posisi di tiap sesi terasa terjalin ganjil. Pembagian Tias di atas, Ghani di sisi kiri, dan Pupuh di kanan, pun Asita di tengah-tengah seperti mendapat pemertegas. Keserentakan itu memukau; memberi semacam jawab atas tanya kenapa tadi ada keterpecahan. Di sana, mereka melaku gerakan yang tadi dilaku sendiri-sendiri; dan kini tetap dilaku sendiri, tetapi dalam suatu keserentalan, dalam suatu komposisi. Rasa lelah, keganjilan yang sakit, dan kesesakan menelusuri bergema: kian bergema. Dan perlahan, lampu meredup—menyisakan Asita di tengah. Ia perlahan, setelah serangkaian soal dan adegan di bawah terang lampu, adegan yang menyuguhkan suatu pernyataan, bahwa tubuh adalah juga narasu, adalah dramaturgi itu sendiri, bangkit dan menghadap depan; bangkit dan memberi suatu senyuman! Kemudian, lampu padam; selesai pertunjukan. Dan, setelahnya, seperti yang lain, kau mantap memberi tepuk tangan.
2.
Amatlah kau yakini, pertunjukan bukan hanya tentang apa yang ditampilkan dan bagaimana sesuatu itu ditampilkan—juga bukan hanya soal siapa yang menampilkan. Namun, bagimu, siapa yang menonton, dan bagaimana seseorang itu menonton, adalah juga penting, adalah juga berharga. Adapun, sebagai penonton, kau adalah seorang yang lebih dibesarkan bahasa, lebih dibesarkan kata-kata dibesarkan cerita. Bahkan, agak sering, kau merasa, tubuh pertamamu, bukanlah tubuh fisik, melainkan bahasa yang puitik, bahasa yang lirik. Dan bagimu, hal itu jadi suatu yang menarik, juga pelik, ketika menyaksi pertunjukan di mana bahasa tak benar-benar hadir, di mana bahasa hadir dengan cara dan bentuk yang lain. Namun, bagimu, sudut pandang yang demikian adalah suatu hal yang mengasyikkan ketika menonton, pantomim dalam hal ini.
Menyaksi Laboratorium Obah #3, di IFI, dengan tajuk “Berhenti Sejenak”, bagimu, adalah pengalaman yang menyenangkan; rasa senang yang bermacam tentu, sebab ada suatu horor, getir, ngeri, sedih, juga perasaan lain yang hadir, saat dan setelah menonton. Dan, sepasang matamu yang besar oleh bahasa itu, mencari teks, mencari bacaan; dan “Berhenti Sejenak”, dengan segala di dalamnya, bagimu, lebih seperti suatu saran: nanti dulu, nikmati saja ini, dan nanti baru ditimbang lagi. Dan kau pun menerima itu. Sepanjang pertunjukan, meski kau dapati pola, yang berarti bisa dibaca, kau lebih melihat dan merasa emosilah yang hadir. Di satu sisi, pantomim yang tak berkata, bagimu, termasuk itu kali, malah memberikan dirimu sekian kata: memberikan keberlimpahan atasnya.
Saat menyaksi, mulanya, seperti biasa, kau dihantui tanya ini pertunjukan apa, bercerita tentang apa, dan tanya yang menghentui penikmatan lainnya. Dan tentulah saja, dalam berjalannya pertunjukan, tanya itu, pelan maupun lekas, bagimu terjawab. Namun, saat menyaksi “Berhenti Sejenak” dengan 4 aktor pun 4 tubuh itu, kau jadi lebih tertarik bertanya, lalu membayang dan menerka, apa yang mereka lihat, dengar, dan rasa dengan melalui tubuh mereka. Bagimu, pertunjukkan itu, dengan seluruh tim, sutradara, aktor, musik-artistik, berhasil mempertebal itu—dan memberi tawaran: berhenti sejenak: untuk menimbang.

Sebab begitu lekas, pikirmu kemudian, manusia luput untuk bahkan sejenak membayangkan apa yang dilihat orang lain, apa yang didengar orang lain, dan apa yang dirasa-alami orang lain. Orang-orang pun melihat-dengar, tapi tak benar-benar melihat-dengar. Bahkan, sebab dituntut, entah oleh apa, ketergesaan membuat orang luput pada diri sendiri. Adapun, bagimu, “Berhenti Sejenak” berhasil memantik tanya dan emosi: apa yang dilihat sampai seperti itu, apa yang didengar sampai melaku itu, apa yang dirasa dan alami sampai jadi begitu. Bagimu, di beberapa hal, mungkin, sebab keterbatasan kosagerak sendiri, kau masih hanya meraba; tetapi, keinginan untuk mengerti tadi dan empati menjadi begitu berharga dan berarti, jadi bernilai sekali.
Sepulang dari pertunjukan, kau memutuskan sejenak menepi: memesan kopi sasetan di warung kecil dan bertemu seorang yang betah menyediakan sepasang telinga; dan sesampai rumah, kau memilih untuk tak langsung membuat catatan kecil-kecilan; tetapi bercengkrama dengan orang rumah. Kemudian, setelahnya, sambil rebah, sambil berbaring di antara tumpukan kertas dan garapan yang betah melimpah, kau merenungi tanya dari dan atas pertunjukkan itu, juga sebuah pertunjukan yang kau saksi pagi tadi: Agaknya, berhenti sejenak memanglah perlu dan baik, tapi sampai kapan, tapi seberapa bentar itu mesti dilaku? “Di dunia semacam ini, seberapakah lama seorang mesti berhenti sejenak?” Amatlah kau pahami, bahwa terus melaju tidaklah baik; tetapi betapa sulit pual menakar sebentar ini. Namun, kau akhirnya memilih: sejanak dapatlah diarti tidur dan mengupaya bangun pagi—lalu mengerja kembali! []
(Agustus, 2025)
Biodata Penulis:
Polanco S. Achri adalah seorang penyair dan penulis prosa, juga pengulas teater dan seni rupa, yang lahir dan tinggal di Yogyakarta. Selain menulis, dan mengulas, ia kadang menyutradarai pertunjukan dan memproduseri film dokumenter kecil-kecilan; juga menguratori pameran. Ia dapat dihubungi di FB: Polanco Surya Achri dan/atau Instagram: polanco_achri.