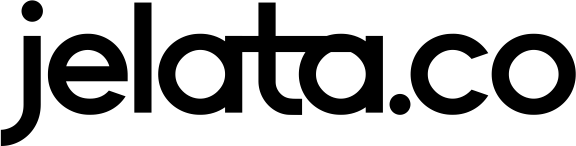1.
Setelah berziarah ke makam Soerjopranoto, dan mampir ke Aula Budi Utomo, serta makan siang di sana, kalian lalu dibawa ke TBY. Di bis, kalian diberi ikat kepala bertuliskan: Sarekat Islam—dengan lambang bulan-bintang di antara dua kata yang menjelma frasa. Di depan TBY, kalian menanti; dan menyorakkan hidup rakyat, hidup buruh. Para lakon itu masuk; dan rebana ditabuh. Rombongan berjalan menuju ampiteater TBY yang telah diubah jadi ruang kongres. Selawat berkumandang bersama iringan. Kalian duduk: menanti kongres mulai. Sadili masuk, memberi pengantar tentang anggota pasif dan aktif, lantas mengenalkan masing-masing tokoh. Setelah genap, tokoh-tokoh itu duduk di kursi yang telah diberi nama. Sadili pun ke belakang: berkata: hanya hendak jadi juru ketik—membersamai jalan kongres dengan bunyi tik-tik-tik.

Cokroaminoto menjadi moderator; dan memberi arahan. Soerjopranoto diberi kesempatan naik podium-mimbar; menjelaskan ide dan gagasan. Di atas podium-mimbar, ia terhenti: menatap papan namanya sendiri: lalu turun lagi dan menghilangkan “R.M.” pada namanya. Dan, setelah genap, ia sampaikan masalah, soalan, dan upaya menyelesaikan. Ditegaskannya, feodalisme, kolonialisme, dan kapitalisme mesti diatasi dengan sistem yang tepat-sesuai. Setelah rampung, ruang diskusi bergulir. Semaoen memberi tanggapan pula; menggarisbawahi apa yang jadi soal dan memberi cara pandangnya. Dan dialog, bantah-bantahan antartokoh begitu riuh, pelik. Dan kau tak genap bisa mengingat, selain hanya bahwa Soerjopranoto menawarkan cara dan metode “rapi”-berjenjang, sedang Semaoen, Darsono, serta Hadji Misbach meminta cepat: revolusi!

Penonton riuh. Kongres ditunda, sebab masuk waktu sembahayang. Tokoh-tokoh pergi; dan Sadili kembali: memanggil tokoh dari masa depan: dari masa kini. Dan Muhidin pun datang: menyampaikan lektur yang menambal lubang, memperjelas yang samar, serta menghubungkan konteks dengan masa kini: dalam nada ironik-tragik.
2.
Sebagai pertunjukan, kau bisa berkata lekas, itu adalah pertunjukan yang asik: dan semacam menunjukkan sejarah yang hidup. Pertunjukan itu menggarisbawahi bahwa seminar, kongres, debat adalah juga pertunjukan—ada dramaturgi, alur narasi, dan spaktakel. Akan tetapi, ketika kau mencermati lagi, kau dapati semacam soal. Soalan pertama, yang kau rasa, adalah perkara waktu, linimasa. Pertunjukan menawarkan kecairan, bahkan sci-fi. Namun, dengan begitu lugu, meski berpijak pada fiksi spekulasi, dan presentasi realis, kau tetap tergoda untuk bertanya: kejadian itu di kurun apa? Memang, di akhir, kau dapati sebuah garis dari lektur Muhidin; tapi kekacauan waktu tetap tak genap terjawab. Andaikan saja garis waktu kongres itu berpijak pada sejarah, soalannya di garus waktu mana penonton tengah berada: Di pra-Indonesia atau 2024? Amat kau pahami, menyatakan soalan yang demikian terasa menggelikan, tapi begimu setidaknya itu penting. Dudukan mula menjadi penting; sebab di ruang itu soal selanjutnya bisa dipilih: menolak atau mengamini.

Soalan yang mengganjal adalah persona tokoh dan keaktoran. Tentu, kostum dan riasan yang dimunculkan amat bisa dikata apik: cocok dan sesuai. Ampiteater di kala petang, tanpa lampu sorot yang amat, tapi citra wajah aktor bisa tampak, bahkan dari belakang. Kostum-kostum yang melekat! Soalannya adalah relasi daripada itu. Di kepalamu, kala menonton atau sesudah, masihlah tergoda tanya yang hampir sama: Seperti apakah tubuh dan gerak daripada seorang Cokroaminoto, Sosrokarsono, Semaoen, Darsono, Hadji Misbach, dan juga Agus Salim, serta Soerjopranoto? Sudah adakah gesture itu di tahun itu? Gerak macam apakah yang muncul oleh Cokroaminoto kala menanggapi tegangan antara Agus Salim dan Hadji Misbach? Apakah aktor hanya memakai kostum dan riasan lantas menjadi?
Dan soalan yang selanjutnya, yang masih terikat, adalah bahasa. Kau paham, ada penyesuaian bahasa. Namun, itu kembali pada garis waktu di muka, pada linimasa di depan: Penonton ada di garis waktu mana? Apakah susunan gramatika di kurun itu memang seperti itu? Tentu kau pahami, ada kebebasan pilihan artistik; tapi bila sejenis capainnya adalah membawa penonton pada sejarah spekulasi, bukankah gestur dan bahasa pada sejarah spekulasi itu jadi terlampau penting?

Dan pertanyaan lugu yang hinggap saat dan setelah menyaksikan adalah bukankah pertunjukan ini adalah pertunjukan dalam serangkaian 6 pertunjukan tubuh Soerjopranoto, lantas kenapa di kongres itu ia, Soerjoprenoto, seperti sesuatu yang minor? Kau sempat tergoda untuk bertanya langsung kepada para pemain atau siapa pun yang terlibat, tetapi jelas kau urungkan—dan lebih suka untuk menerka-nerka. Apa komposisi ruang dan benda-benda memang mengejar hal yang demikian? Apa posisi duduk Soerjopranoto di tepi adalah sejenis upaya menunjukkan bahwa ia ada di tepi—meski gagasan dan praktiknya adalah besar, agung, dan mendalam? Kau tak tahu, tapi kau enggan bertanya pada aktor, sutradara, atau yang terlibat di dalamnya.
3.
Meski begitu, sebagai sebuah pertunjukan, pertunjukan itu mesti diakui memberi gema—bukan hanya soal dramaturgi atau limpahan spaktakel: tapi sebab memberi godaan untuk menelusuri, membayangkan serangkaian peristiwa-peristiwa, bahkan lintasan jaman yang lain []
(Yogyakarta, Desember 2024—Februari 2025)
PENULIS

Polanco S. Achri lahir dan tinggal di Yogyakarta. Ia menulis puisi, prosa-fiksi, dan esai tentang seni. Selain menulis, terkadang, ia menyutradarai pertunjukan dan mengurasi pameran. Ia dapat dihubungi di FB: Polanco Surya Achri dan/atau Instagram: polanco_achri.