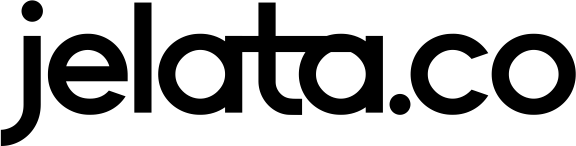Di hari-hari yang hujan, orang-orang ingin manja dan merasakan kenikmatan. Oh, hujan dan tidur yang lelap. Keinginan yang remeh. Ada yang menyambut hujan dengan kopi dan rokok. Nah, cara yang wajar tapi membosankan. Di kamar, menonton film yang romantis sambil selimutan. Duh, orang yang takut merana dan terlilit bahagia.
Hujan itu makin indah dan basah jika menuruti keinginan mulia: mencuci pakaian keluarga yang kotor. Satu atau dua ember rendaman cucian itu pemandangan yang elok. Duduk, mengucek dan menyikat itu tindakan yang perkasa. Walah, peristiwa picisan!
Padahal, hujan turun tidak memberi jadwal. Pagi kadang hujan deras dan lama. Yang dinantikan kaum manja adalah hujan saat sore atau malam. Pokoknya, hujan datang dan pergi tanpa memberi kabar dulu. Kita yang mendapatkan hujan tidak perlu sewot dan misuh-misuh. Ingat, hujan tidak bisa diajak omong.

Konon, hujan di desa dan kota itu berbeda rupa dan rasa. Apakah kita mau percaya? Sebaiknya, percaya saja. Bawalah tubuhmu mondar-mandir bila hujan: dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Buktikan rupa dan rasa yang berbeda. Orang yang mudah sendu akan mengatakan hujan yang anggun terjadi di desa. Ia malah bersumpah bahwa hujan di desa yang paling puitis. Sumpah untuk menyaingi hujan-hujan yang “berjatuhan” dalam puisi-puisi gubahan Sapardi Djoko Damono.
Ada orang yang tidak terima. Hujan yang gagah itu di kota, katanya sambil mecucu. Oh, hujan itu gagah dan membuat kota makin pongah! Yang paling membedakan hujan di kota dan desa: penerima. Aku wajib memberi keterangan sedikit: hujan menimpa aspal berbeda dengan hujan yang mencium tanah. Nah, pemandangan air hujan pastinya mesra di desa ketimbang di kota.
Sudahlah, kita hentikan (masalah) hujan. Pada 18 Desember 2024, aku membeli Kompas yang harganya setara semangkok soto atau mi ayam. Jika harga gorengan seribu rupiah, koran itu setara sembilan gorengan. Maka, orang yang waras dan lapar memilih makan soto, mi ayam, atau gorengan. Aku malah berbuat dosa dengan membeli Kompas. Aku sengaja membelinya, sebelum semuanya tamat di Indonesia. Banyak koran sudah pamitan.
Eh, aku membacanya saat sore yang hujan deras, setelah mencuci pakaian dua ember. Di luar basah dan aku malah bermanja dengan air saat mencuci. Yang teringat adalah air panas. Yakinlah, aku tidak mau minum air bening yang panas. Air di panci yang disembur api di kompor aku gunakan membuat segelas teh. Sore itu tanpa roti dan santapan. Padahal, aku membayangkan ada pisang goreng, kacang rebus, jagung, atau tela. Semuanya tidak ada. Di tatapan mata, yang ada hanya segelas teh. Sabar untuk absennya makanan-makanan yang semestinya datang bersama hujan.
Pasangan teh adalah koran. Aku membaca di Kompas mengenai desa. Berita yang menghindarkan pembaca dari masuk angin atau pegal-linu. Yang terbaca: “Lima desa mendapatkan Apresiasi Desa Budaya 2024 dari Kementerian Kebudayaan atas dedikasi pada agenda pemajuan kebudayaan.” Berita di akhir tahun atau Desember memang isinya anugerah, penghargaan, dan apresiasi. Bulan yang paling konyol!
Nah, ada penjelasan dari menteri yang bernama Fadli Zon: “Desa-desa ini adalah contoh nyata ketangguhan budaya. Mereka membuktikan bahwa kebudayaan dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman dan mempertahankan akar sejarah serta nilai-nilai luhur dengan kreativitas dan kerja keras.” Yang aku baca adalah kata-kata dalam keterangan resmi cap birokrasi. Kalimat-kalimat yang cukup bagus tapi tidak bisa dinyanyikan. Ingat, Fadli Zon itu menteri, kolektor keris, pemilik ribuan buku, pemelihara peta-peta kuno, dan lain-lain. Namanya mirip dengan sosok yang biasa bernyanyi dalam Padi.

Sejak dulu, aku suka mendengarkan lagu-lagu Padi tapi yang sedih-sedih. Hujan kadang cocok dengan mendengarkan suara Fadly ketimbang membaca lembaran-lembaran koran yang tidak mengenyangkan. Suara itu terdengar lagi: “Aku tak mengerti, apa yang mungkin terjadi. Sepenuh hatiku, aku tak mengerti.” Ada lagi: “Kaulah rahasia terbesar hidupku, yang takkan mungkin aku ungkapkan. Kusimpan erat perasaanku meski ajal menanti.”
Namun, berita yang terbaca adalah desa. Aku mesti membaca dan memikirkannya sampai tetes hujan terakhir, yang mengecup daun salam atau tanah di samping rumahku. Desa dan budaya sebenarnya tema yang biasa. Dugaanku: pemerintah sedang kurang pekerjaan sehingga memerlukan membuat apresiasi atau anugerah untuk desa-desa. Keyakinan yang belum terbantah: desa sangat penting untuk Indonesia tapi yang beranak-pinak adalah kota. Desa telanjur sering diremehkan dan dikasihani melalui bahasa-bahasa yang bikin merinding, mewek, dan sinis.
Hidup di desa dan memikirkan desa? Ah, hujan jadinya tidak romantis. Teh yang diminum mengurangi imajinasi desa yang manis setelah “guyuran” miliaran rupiah yang membuat salah tingkah. Desa dimengerti dengan uang. Oh, desa yang bakal kehabisan cerita. Bagiku, desa itu cerita-cerita yang membatalkan orang bunuh diri atau piknik ke tepian neraka.
Hari-hari berlalu tapi hujan tetap saja mau turun di rumah, memberi air masuk rumah alias bocor yang menimpa buku-buku. Pada saat ada sinar matahari, aku kadang menjemur buku-buku basah, tidak hanya pakaian yang sudah dicuci.
Pada hari yang bukan terindah, aku menyimak berita dan keterangan orang-orang yang ikut merayakan 75 tahun UGM. Oh, universitas yang bersejarah dan mentereng di Jogjakarta. Dulu, aku tidak berani bermimpi kuliah di situ. Faktanya, ingin kuliah di UNS saja tidak bisa. Aku mengerti penyebabnya: bodoh. Aku paling benci jika mengerjakan ujian untuk kuliah berupa soal-soal matematika dan bahasa Inggris. Terkutuklah ujian-ujian yang menghina kebodohanku.
Aku sempat menjemur buku biru. Duh, sebutan yang mengingatkan film biru. Buku berwarna biru ikut mendapat kecupan air hujan dalam rumah. Akhirnya, aku menjemurnya di dekat pohon pisang dan pepaya. Berharap buku itu kering meski penampilannya tak seelok dulu. Buku yang berjudul Desaku dan Kampus Biru (1993). Buku yang berkaitan dengan KKN. Judulnya itu biasa. Namun, KKN selalu mengingatkan Orde Baru. Yang aku maksudkan, KKN itu kuliah kerja nyata. Padahal, KKN pada masa Orde Baru sangat seru. Maksudku, yang berarti korupsi, kolusi, nepotisme.

Buku biru adalah buku panduan untuk ribuan mahasiswa yang datang ke desa-desa. Konon, mereka datang membawa pengetahuan. Mereka yang akan mengubah nasib desa. Yang teringat: para mahasiswa terbiasa mengenakan jas almamater. Duh, omongannya cerdas dan bermutu sehingga membingungkan kuping-kuping orang desa. Sialnya, aku tidak pernah ikut KKN, yang berakibat mendapat makanan-makanan khas desa, kekasih atau istri, dan hujan dengan rupa dan rasa desa.
Buku dari masa Orde Baru itu pasti disusul buku-buku yang lainnya. Setahuku, UGM terus membuat KKN, yang membuktikan perhatian kepada desa-desa. Pada suatu hari nanti, aku ingin menyambut kedatangan para mahasiswa KKN di desaku. Mereka pasti bisa mengubah desaku dan mengindahkan nasibku agar dapat menikmati teh, pisang goreng, dan kacang rebus saat hujan turun sebelum maghrib.
Penulis