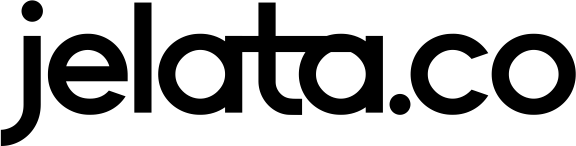Kisah yang akan kubagikan ini dimulai tepat sebelum aku menemukan tempat peristirahatan terakhirku. Pada sebuah kotak kayu mahoni yang sudah lapuk bersama saudara-saudaraku lainnya. Tidak pernah aku duga bahwa pada akhirnya aku akan berlabuh di tempat ini. Tapi tentu berlabuh lebih baik dari pada harus terapung di atas samudera kebimbangan selamanya, ‘kan? Sebab sejauh yang telah aku arungi, aku memang seperti perahu yang berlayar tanpa tujuan. Baiklah kalau begitu, mari dengarkan kisahku dari awal. Kisah ini dimulai ketika aku bertemu dengan seorang anak muda religius bernama Anwar.
Anwar tinggal bersama enam orang anggota keluarganya, di sebuah rumah yang hanya berisi dua ruangan sempit berukuran masing-masing lima kali empat dan tiga setengah kali dua setengah meter. Satu ruangan kecil digunakan untuk tempat tidur bapak dan ibu Anwar, sekaligus tempat mereka beribadah. Sedangkan ruangan yang lebih besar digunakan sebagai tempat tidur semua anak-anak, juga tempat belajar, tempat makan, ruang tamu, bahkan aku melihat kompor kecil dengan tabung gas tiga kilo di pojok ruangan untuk memasak. Jika malam tiba mereka berhimpitan bagai ikan sarden dalam kaleng. Hawa dingin kerap tak terasa karena efek dari kulit bertemu kulit lebih menghangatkan dari pada mantel beruang.
Anwar adalah bujang paling tua, baru saja lulus SMA dan kini sedang sibuk cari kerja. Empat adiknya masih di jenjang SD dan SMP. Kondisi ini otomatis membuat Anwar menjadi calon tulang punggung baru keluarga. Sayang sudah sekian bulan panggilan kerja belum juga menghampirinya. Dari timur ke barat belum ada titik temu. Dari utara ke selatan masih buntu. Padahal Anwar rajin beribadah. Pernah kudengar jawaban Anwar saat ditanya kenapa ia tetap rajin ibadah walau masih tetap melarat. “Saya sudah sering kalah di kehidupan dunia, setidaknya saya mau berhasil di akhirat.” Jawabannya sungguh memikat.
Hanya saja aku teringat kata-kata seorang bijak, ia bilang bahwa iman seorang hamba itu naik turun. Kadang menguat dan bertengger di puncak hati paling dalam. Kadang juga terjerembab saat tidak mampu menerima ujian. Anwar makin gusar, ia tidak ingin jadi pengangguran terlalu lama. Setinggi apapun tingkatan sekolahmu tapi jika tetap menganggur maka kau hanyalah beban keluarga bahkan beban negara. Dalam kegelisahan itulah Anwar mendengar di kampungnya ada orang pintar yang mampu memecahkan semua kesulitan duniawi. Tanpa pikir panjang ia segera ke sana, menemui si orang pintar dan melemparkan semua tumpukan beban di punggungnya. Si orang pintar terdiam memejamkan mata. Terduduk tenang layaknya memang pintar.
Ia meminta sebuah benda apapun yang sedang Anwar bawa. Anwar memeriksa tubuhnya yang nyaris melompong, ia menemukan diriku di saku kemejanya. Segera saja aku dimantrai dengan jampi-jampi, “Bawa ini saat wawancara kerja; jimat.” Si orang pintar menatap Anwar bulat-bulat, ia tahu si miskin tidak akan mampu membayar mahar, “Seikhlasnya saja,” kata-kata itu menuntun Anwar memberikan seluruh sisa uang di dompetnya. Ajaib, hanya kurun dua hari saja mantra itu bekerja. Anwar diundang wawancara dan langsung disuruh kerja hari itu juga. Sepulangnya dari kantor ia menuju ke rumah si orang pintar untuk sekedar berterima kasih. Di jalan Anwar berhenti sejenak di pedagang es degan dekat pangkalan becak.
“Terima kasih, ya, tapi aku sudah tak membutuhkanmu.” Dia mencampakkanku begitu saja demi segelas es degan. Belum juga degan segar itu membasahi kerongkongannya tiba-tiba seorang bapak-bapak tegap berpakaian preman menyergapnya, “Ikut kami ke kantor, jangan melawan!” Mata Anwar melebar, lubang hidungnya kembang-kempis. Pembelaannya sia-sia belaka. Konon ini berkaitan dengan si orang pintar, ia ternyata mengelabui orang-orang sebagai dukun pengganda uang. Anwar adalah orang terakhir yang terdeteksi menemui si orang pintar dan diduga ikut meminta jasanya. Mampuslah dia. Penjual es degan tertegun melihat pelanggannya diseret tak berdaya, ia sedang melayani pembeli lain.
Seorang ibu-ibu yang membeli dua bungkus es degan untuk dibawa pulang. Harga es degan lima ribu rupiah, ibu tersebut menyerahkan selembar pecahan dua puluh ribuan. Aku kembali berpindah tangan. Tapi hanya sebentar. Ia segera menukarku pada seorang tukang becak bermuka masam berkulit legam. Aku tak menyukai wajahnya yang sangar. Namun ia memperlakukanku dengan lembut.
Menerimaku dengan kedua tangannya, memandangi dengan penuh syukur. Ia menoleh pada seorang wanita berpakaian kantoran yang sedang menunggu becak lain. “Mbak, boleh pinjam pulpennya nggih?” ia melihat di saku wanita itu ada pulpen hitam. Lantas mencoret-coret diriku yang tentu membuatku kotor dan tersinggung. Ia melipatku dan menyisipkan ke dompetnya terpisah dengan uang lain secara hati-hati. Wajahnya penuh kelegaan. Setelah mengembalikan pulpen, tukang becak itu langsung giat menggenjot becaknya.
Di tanjakan menuju gang rumah si pelanggan, mendadak keringatnya jatuh sebiji-biji jagung. Nafasnya berat, tangannya menggapai pundak kemudian leher. Pandangannya memburam. Sekuat tenaga diarahkan becaknya menepi, ia berhenti setelah menabrak tiang listrik. Pelanggannya terjungkal. Ibu itu bangun berniat memaki, tetapi diurungkan saat melihat si tukang becak sudah tergeletak mendelik mencengkram dada sebelah kiri. Kerumunan orang datang, tukang becak malang tersebut segera dibawa ke rumah sakit.
Sungguh kusesalkan ia tidak selamat. Semua benda yang melekat di tubuhnya dikembalikan ke keluarganya, termasuk dompet berisi aku. “Bapak, kan, sudah janji membelikan Billa sepeda listrik, kok sekarang malah pergi?” sang anak merintih memeluk ibunya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku singgah di rumah si tukang becak, melewati tujuh harian tahlil. Istri si tukang becak menghibur buah hatinya yang terhanyut duka, menyarankan untuk membeli sepeda listrik yang selama ini diimpikan. Dengan keengganan sang anak terpaksa datang ke toko elektronik sambil membawa dompet almarhum bapaknya.
Ia tidak memilih lama karena tahu harga paling murah adalah satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah. “Harganya sudah naik Kak, jadi satu juta dua ratus dua puluh ribu!” Cukup ketus ulah si pramuniaga membuat anak tukang becak tersentak. “Tapi uangku pas cuma ini,” katanya, tidak mampu menyembunyikan kepanikan. Ia mengais semua bagian dompet, alisnya berkerut saat menemukanku yang tersisa paling akhir di selipan bagian lain. Pramuniaga menunggu sambil menyilangkan tangan di dada. Saat akan menyerahkanku, tangannya bergetar. Ia melihat tulisan mendiang bapaknya di tubuhku, “Selamat ulang tahun Billa, anak bapak paling cantik.”
Sekuat tenaga anak itu menahanku untuk tak berpindah tangan, tapi si pramuniaga dengan cekatan merampasku. Anak itu berpaling lemas laiknya ban sepeda bocor, ia mengacuhkan instruksi si pramuniaga. Bahkan menyeret sepeda itu pulang tanpa mencoba menaikinya terlebih dahulu. “Anak aneh! sudah uangnya lama, ada coretannya lagi,” si pramuniaga bersungut-sungut memelototiku. “Tempel saja di etalase, contoh uang yang sudah nggak laku!” perintah kasir toko. Namun si pramuniaga meremasku dan bergegas lari keluar toko, ia segera masuk pasar dan berhenti di sebuah lapak uang kuno. “Berapa kira-kira Pak?” bapak penjual uang kuno memeriksaku sebentar, “Kalau ada coretannya begini nilainya turun, paling sembilan ribu.”
Mereka berdebat saling tawar, dapatlah di angka sebelas ribu. Pramuniaga cukup senang tidak merugi. Bapak penjual uang kuno juga senang. Ia letakkan diriku di dalam sebuah kotak kayu mahoni lapuk, “Huh bocah apes! uang ini berharga lebih dari itu kalau dibeli kolektor atau jadi mas kawin unik.” Betul apa kata bapak penjual uang kuno. Sebentar lagi keberadaan diriku memang akan terlupakan. Hanya akan menjelma menjadi lembaran uang kertas lawas. Diriku merenung, tahu sudah digantikan uang baru bergambar saudaraku Frans Kaisiepo. Saatnya aku beristirahat. Sudah cukup waktuku berkelana dari satu cerita ke cerita yang lain. Dari satu kehidupan manusia ke manusia yang lain. Tapi mungkin saja cerita ini berlanjut jika benar nantinya aku kembali dibeli orang, entah untuk tujuan apa. Uang beli uang? Sungguh aneh. Hingga sebuah sapaan menggugahku, “Jangan bermuram saudaraku, ceritakan kisahmu pada kami.” Aku melihat asal suara itu, tampak R.A Kartini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Cut Nyak Dien tersenyum menyambutku.
Komentar
Cerpen ini menarik untuk dibaca terutama karena sudut pandang orang pertama yang menjadi salah satu tokohnya. Perjalanan “aku” bisa dengan sangat lincah memandang serta menelusur kondisi sosial ekonomi.
(Tiaswening Maharsi, Redaktur Cerpen)
Penulis

Faisal Fadhli Lulusan Fakultas Hukum yang menyukai seni, film, olahraga serta sejarah. Dikenal dengan nama pena GoresTerka, sekarang sedang menekuni dunia kepenulisan. Terutama cerpen, sudah menulis sejak remaja dan mulai mengirimkan karya di tahun 2022.
Instagram @goresterka