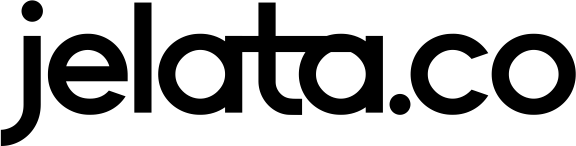Sesampai di kosan, aku tidak bisa fokus pada buku bacaanku. Tafsir Al-azhar karangan Prof. Dr. Hamka kututup pelan-pelan, kemudian kuletak di atas meja. Aku hanya mengulang-ngulang bacaan yang telah lalu. Sebelumnya sudah aku baca tuntas sampai 30 juz. Tafsir Al-azhar sebagai pelengkap bacaanku dari beberapa tafsir yang aku punya menggunakan bahasa arab. Aku juga membaca Tafsir Al-misbah ditulis oleh Prof. Dr. Quraish Shihab. Aku belum selesai membaca semuanya. Baru beberapa jilid. Aku bandingkan kedua tafsir tersebut, menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk menghindari rasa jenuh, biasanya aku membaca tiga buku yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
Kini, aku berlari ke dapur memanaskan air, membuatkan segelas susu coklat. Aku harus bisa mengajak pikiranku yang galau berdamai. Aku membuka buku tulis yang berisi karanganku. Malam ini aku melanjutkannya dengan cara manual, menulis dengan tangan. Aku juga tidak tahu kenapa, ada saat-saat tertentu biar aku lebih berkonsentrasi melepas imajinasiku harus menulis lewat tangan menggunakan pena. Kalau menulis langsung lewat komputer, kadang-kadang pikiranku bukan saja pecah, tapi ide-ide yang menumpuk tak bisa kualirkan lewat mesin komputer, itu terjadi tidak setiap waktu, walaupun waktunya tak menentu.
Buku tulis sudah kutelanjangi. Aku duduk sebentar seakan melakukan imitasi. Begitu aku dapat ide yang ingin dituliskan, aku mengambil air wudhu, mengikuti sabda nabi, wudhu adalah senjata bagi orang mukmin. Aku menyimpulkan jika ingin melakukan sesuatu alangkah baiknya dilakukan dengan berwudhu terlebih dulu, termasuk menulis. Bahkan sebelum melakukan persetubuhan dengan istri di sunatkan berwudlu. Jika ingin melakukan yang kedua kali, setelah membasuh kotoran yang lengket di farji masing-masing tetap juga disunatkan berwudlu lagi terlebih dulu, walaupun belum melakukan mandi junub, begitulah penjelasan dari kitab yang pernah aku baca.
Dalam kesendirian yang sepi ini aku tidak butuh ditemani beberapa batang rokok seperti penulis atau sastrawan lain. Sampai saat ini aku percaya rokok itu racun yang membunuh. Aku tidak ingin mengait-ngaitkannya dengan hukum, haram atau tidak rokok itu. Nuranimu sendiri pun mempercayai mudrat sebatang rokok lebih banyak ketimbang manfaatnya. Ujung penaku yang tajam menari-nari di atas kertas melaksanakan titahnya. Dalam kesendirianku, dan dalam kesunyian seperti ini aku bisa mendapatkan ide yang gemilang. Sesekali kita butuh sepi, ucap Ikhsanuddin dalam bukunya dengan judul sama. Aku mengikuti perintah yang tidak memaksa itu. Aku mendapatkan ketenangan ketika mengarang sebuah cerpen Perempuan Bekas, sampai selesai, belum termasuk revisi.
Sinopsisnya seperti ini, gadis nakal itu lebih mencintai om-om yang berduit, daripada lelaki perjaka yang gagah perkasa tapi kere. Sebenarnya perempuan itu merasa tak pantas menyebut perasaan yang tumbuh terpaksa itu dengan sebutan cinta. Ia sendiri yang mengklaim diri, seorang gadis yang layu sebelum berkembang. Suatu hari ia ditemui seorang Ibu tua renta yang mengaku Ibu kandungnya. Nama perempuan tua renta itu Midah. Awalnya perempuan bekas itu tidak percaya. Waktu terus bergulir. Suatu hari ia bercerita tentang kedatangan Midah perempuan renta itu yang datang menemuinya. Bu Sarifah yang mengasuhnya sejak kecil bersikeras mengatakan, Midah adalah benar Ibu kandung Aswati, perempuan bekas itu.
“Tolong, jujurlah untuk hal ini Ibu, untuk apa berbohong kepada perempuan bekas sepertiku,” ia bersujud di bawah kaki Sarifah yang ia anggap sebagai Ibu kandungnya.
“Ya, perempuan itu memang ibumu Nak, aku berani bersumpah atas nama Tuhan,” menimpali Sarifah yang sudah tahu kisah tersembunyi yang disimpan dan diikat erat-erat agar perempuan bekas tidak tahu. Perempuan bekas tetap merasa terkejut, walaupun akhir-akhir ini rasa kecurigaan sudah mulai tumbuh dalam benaknya. Ia tidak tahu apakah perasaannya senang atau terluka. Mungkin setelah mendapat berita ini ia menemukan sejuta kemurkaan. Kalau ada Ibu kandung, kenapa aku harus diasuh orang lain? Berarti aku dibuang atau terbuang? Pertanyaan itu mengaduk-ngaduk pikirannya yang semakin kacau. Saat itu ia ingin memilih mati.
“Ibumu sangat menyayangimu Aswati, kelakuan ayahmu yang bejat yang membuat ibumu gegabah seperti ini. Ia terpaksa menyuruhku untuk mengasuhmu. Kalau tidak ia akan menceraikan ibumu.” Perempuan itu belum bisa menerima sepenuh hati.
“Kenapa?” Ia belum menemukan jawaban.
“Setelah ia tahu kau bukan anak kandungnya, kau hasil hubungan gelap seseorang dengan ibumu. “Aswati belum bisa diam.
“Berarti ibuku lebih memilih lelaki itu daripada aku, dasar Ibu tidak berguna,”
“Bukan begitu,” Sarifah mencoba menenangkan suasana yang hampir gaduh. Saat ini ia tak tahu kepada siapa harus mengaduh.
“Maafkanlah Ibu tirimu ini, jika terlalu lancang menurutmu Nak. Suami Ibu kandungmu pernah bilang padaku, ia tidak suka mengasuh anak perempuan haram. Menurut pemikirannya, haram pula hukum memeliharanya. Kalau ibumu bersikeras untuk memiliharamu, suaminya akan meninggalkan ibumu. Alasannya, ya, katanya karena kau anak haram.” Wajah Sarifah seperti ketakutan. Ia tidak ingin perempuan yang ia pelihara-bertahun-tahun berontak.
“Pemikiran bodoh, mana ada anak haram, yang haram itu perbuatan orang tua mereka. Setiap anak yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci, termasuk aku.”
“Maaf Nak, jangan merasa sok tahu, kamukan cuma perempuan bekas,”
“Aku tidak merasa sok tahu, aku hanya diberi tahu.”
Akhir cerita ini, perempuan itu menemukan seorang lelaki yang tahu agama, dan benar-benar menjalankannya. Barulah ia merasa menemukan cinta yang utuh. Tidak seperti bayang-bayang, tidak seperti perasaan yang tumbuh kemudian sewaktu-waktu lenyap. Ia mencintai dan dicintai dengan sepenuh jiwa dan raga. Ia yang berwajah cerah memeluk kekasihnya yang bersandar menatap bintang yang berkelip lewat jendela yang tersenyum. Sampai di situ aku menutup cerita. Paling lambat dua hari lagi, setelah direvisi habis-habisan, sampai menggunakan jurus terakhir, aku mengirim sepotong naskah ini ke media . Kalau layak muat dan diterbitkan, pembaca sendiri yang mengambil nilai moral yang kuselipkan dalam isi cerita ini yang kususun dengan jiwa yang damai. Semakin banyak penafsiran yang berbeda-beda, semakin kaya karya sastra yang kucipta, dan semakin mengigit rasanya. Itulah salah satu keindahan karya sastra.
PENULIS
Depri Ajopan, lahir di Desa Lubuk Gobing, Sumatera Barat, 7 Desember 1989. Lulus program S1 Universitas Negeri Padang Prodi Sastra Indonesia. Ia bergiat sebagai anggota Komunitas Suku Seni Riau dan mengajar di Pesantren Basma Darul Ilmi Wassa’dah, Kepenuhan Barat Mulya, Rokan Hulu, Riau.