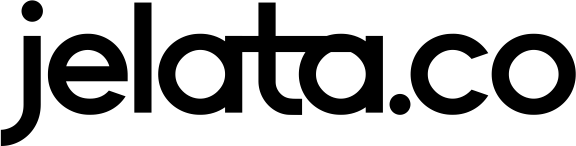Jakarta sebagai Gambar
Mengapa melukis? Untuk apa menciptakan gambar baru di dunia yang sudah sesak akan imaji dan representasi? Jawaban yang paling dasar adalah kesenian merupakan sesuatu yang membuat manusia bersentuhan dengan kemanusiaannya.
Untuk para seniman, jawaban dari pertanyaan tadi tentu menjadi kompleks. Semua jawaban valid. Bagi saya pribadi, alasan untuk menciptakan gambar baru ditengah kesesakan adalah untuk memperlihatkan apa yang tidak terlihat, virtualitas dari gambar yang kita lihat sehari-hari sebagai penduduk Jakarta.
Sebagai pendatang, harus saya akui Jakarta merupakan pengalaman yang sangat ekspansif bagi persepsi, horizon pengetahuan dan data sensorik tubuh – segala hal yang esensial bagi seorang seniman. Jakarta sendiri merupakan satu gambar besar dengan detil yang tidak terbatas: heterogenitas pada titik ekstrim, hampir tanpa pusat.
Pusat atau gambar utama hanyalah satu dari lautan gambar yang dibingkai oleh media massa. Gambar-gambar utama itu terus dipertontonkan agar menjadi identitas kota – yang pada akhirnya menjadi sebuah stereotip.
Patung selamat datang di Bundaran HI, ondel-ondel, dan lain sebagainya merupakan gambar-gambar utama yang dibingkai media dan pemegang otoritas untuk merepresentasikan Jakarta. Namun pada kenyataannya, Jakarta memiliki terlalu banyak gambar lain yang sama pentingnya, sama bernilainya.
Kemiskinan sama bernilainya dengan kemegahan gedung-gedung di Sudirman, banjir yang menenggelamkan warga sama bernilainya dengan pesta malam di Senopati. Nilai dalam konteks ini bukan dilandaskan pada moral, namun pada intensitas: daya dan energi. Oleh karena itu, pameran Jakarta Emang Gitu ini menjadi menarik karena kita dapat melihat arus energi yang diakses oleh setiap seniman.
Melihat Jakarta dengan Kaca Pembesar
Salah satu hal yang menyenangkan dari menghadiri pameran ini adalah menyaksikan bagaimana setiap seniman melihat Jakarta. Kompleksitas ibu kota dengan beragam isunya tidak saya lihat sebagai sejumlah masalah yang harus diselesaikan, namun sebagai planet-planet kecil yang eksis secara bersamaan: sebuah multiplisitas.
Jika gambar-gambar besar tentang Jakarta adalah apa yang dijejalkan pada orang oleh media, yang diproduksi secara massal sehingga peristiwa tersebut – yang seharusnya menjadi objek seni – menjadi sama saja dengan objek lainnya, maka pada pameran ini saya menikmati karya seniman yang melihat Jakarta dengan kaca pembesar: gambar-gambar minor, yang berada di luar frame televisi.

Kabel listrik yang semrawut dan memakan korban dihadirkan oleh HS dengan judul “Nirestetika”. Fenomena yang tidak akan diunggah di laman sosial media pemerintah kota ini sering kita jumpai di jalanan.
Objek ini pada bentuk faktualnya sangat mengganggu pemandangan, menurunkan semangat dan memberi efek kotor seperti sampah yang bergelantungan. Namun objek yang sama menyergap saya dengan keindahannya pada karya Nirestetika.
Saya ingin memandangnya berulang kali – kontras dengan gulungan kabel di Antasari yang membayangkannya saja saya enggan. Karya lain yang menghadirkan gambar-gambar kecil Jakarta diantaranya “Work Hard Play Hard” (Fransiska Fitrinia) yang menyoroti fenomena odong-odong sebagai hiburan anak kelas sosial bawah, “Demi Persingkat Waktu” (Indra Arief Hidayat), dan masih banyak lagi.
Kerja seni tentu bukan hanya memindahkan realita ke atas kanvas. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, membayangkan gulungan kabel listrik saja saya enggan – namun lukisan ini sebaliknya.
Diluar persoalan teknis seperti skill dan material yang dipakai oleh seniman, ia menghadirkan virtualitas – dunia kemungkinan, dan sisi afektif dari fenomena tersebut. Dengan “Nirestetika”, pelukis melangkah lebih jauh dari melihat Jakarta dari kaca pembesar.
Melalui kaca pembesar itu ia masuk ke celah kemungkinan dari peristiwa tersebut, merampok – mengantungi apapun yang muat di tangannya, lalu menghadirkannya pada kita.
Karya lain yang langsung merebut perhatian saya yaitu “Menyambung hidup badut Jakarta” (Nikma Harahap). Karya ini sinematik – dengan beberapa scene yang dimontase dalam satu frame.
Garis pemisah antar scene dikaburkan sehingga hampir terlihat seperti superimposed – bertumpuknya adegan demi adegan namun kita tetap bisa melihat jelas setiap adegannya. Hal ini perlu diapresiasi sebagai kerja konsep yang berhasil, sebuah usaha untuk melampaui batasan seni lukis sebagai gambar diam.

Pemilihan subjek badut juga saya pikir sebagai keputusan yang cerdas. Fenomena manusia-manusia berkostum di jalan-jalan raya di Jakarta baru terjadi beberapa tahun terakhir ini; dimulai dengan Badut Mampang yang muncul pada 2017 dan kemudian aktivitas mencari uang dengan berkostum ini menjadi semakin marak dan beragam seiring bergulirnya waktu.
Selain pada makna denotatifnya – yaitu sebagai aktivitas untuk mendapatkan uang, badut juga metafor yang tepat untuk prototype manusia Jakarta yang harus menekan autentisitasnya demi berbagai hal, seringnya demi diterima di lingkaran sosial yang diinginkan.
Karya ini bertemakan kemanusiaan, mudah untuk dipahami namun tetap mengganggu pikiran. Tanpa perlu membaca deskripsi, saya yakin banyak yang bisa merasa terkait dengan karya ini. Keterkaitan ini justru bisa terjadi jika karya tersebut bersifat impersonal.
Non-human: Menjadi Kota Itu Sendiri
Ketika melihat karya Dick Syahrir, saya membayangkan seseorang dalam sebuah lingkungan sosial dimana ia terlalu mengenal lingkungan tersebut dengan segala kompleksitasnya.
Ia mungkin sudah membuat banyak penilaian tentangnya di masa lalu – namun penilaian atau judgement tersebut tidak bisa merangkum objek yang dinilai, dalam konteks ini lingkungan sosial tersebut.
Akhirnya, ia tidak lagi berusaha memaknai lingkungan tersebut layaknya seorang manusia. Untuk menjelaskan sebuah kompleksitas, ia harus mencari analogi. Analogi itu tidak mendikte – ia multitafsir namun tetap memiliki petunjuk dan batasan-batasan interpretatif. Karya yang berjudul “Jali-Jali” ini menganalogikan Jakarta dilihat dari tata kotanya.
Selaras dengan deskripsi lukisan yang tertulis “Kesan lingkungan bangunan-bangunan di Jakarta masa kini”, karya ini memanggil memori saya akan pengalaman melewati gang-gang kecil di Kalipasir, perkampungan yang mengelilingi separuh dari Taman Ismail Marzuki.
Kalipasir bagaikan labirin yang dijejali oleh bangunan-bangunan tak tentu arah. Jika sebagai pengendara motor akselerasi anda tidak begitu baik, maka pasti akan sering menabrak – entah pot bunga, tembok rumah orang, atau terjerembab di selokan.

Momen tersebut menandai terbukanya kotak Pandora kesekian – dimana sebagai pendatang, kesan-kesan umum saya tentang Jakarta semakin diporak-porandakan. Dick Syahrir menghidupkan memori tersebut dengan sangat kuat melalui Jali-Jali.
Selain karya Dick Syahrir, “Ampuuun Kaka…” (Anton) dan “Preplexed (2024)” (Philips Sambalao) juga berada dalam arus yang sama: mereka menarik jarak dari metafora-metafora humanis dan mengekspresikan gagasannya dengan elemen-elemen grafis seperti bentuk, tekstur visual dan garis.
Jakarta Emang Gitu: Membidik Rasa
Seperti kerja seni yang saya kagumi, kata “Emang Gitu” pada judul pameran ini menggunakan gaya penyampaian yang ingin langsung membidik sasaran; emang sebagai penekanan, gitu secara spesifik menunjuk sesuatu – sebuah abstraksi.
Kita tidak datang ke pameran seni untuk melihat hal-hal normatif seperti yang biasa kita temui pada artikel berita. Kita tidak tertarik untuk membaca apapun yang sekadar menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial.
Dengan metode dan melalui aliran apapun, seniman berkomunikasi dengan melakukan abstraksi. Seni adalah antinomi dari klise. Autentisitas seorang seniman hanya bisa muncul jika ia dapat menghindari klise.
Laku itu sendiri membutuhkan jam terbang dan kematangan. Bukan berarti seniman muda tidak bisa melakukannya. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kemampuan untuk menunda.
Dalam novel “The Hunger Artist” (1961), Franz Kafka mengeksplorasi tubuh yang memutuskan untuk menunda pemuasan dari rasa lapar. Dalam novel tersebut, sang seniman mencapai level yang baru dalam kesenimanannya melalui kelaparan.
Dengan melambatkan respon tubuh, ia mendapatkan rasa dan imaji yang baru akan tubuhnya. Bagi saya, begitu pula seorang pelukis harus menunda dalam membidik imaji yang akan dipindahkan ke kanvas.
Lukisan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan fotografi, maka keuntungan tersebut sebaiknya tidak disia-siakan. Walau berupa gambar diam, karya-karya yang saya kagumi dalam pameran ini sebenarnya bergerak – ia bukan monument yang mengabadikan sebuah momen, namun sebuah peristiwa seni, arus energi yang dihadirkan melalui kerja artistik yang tidak mudah.
Penulis
Keisha Aozora

Penari dan Penulis
bermukim di Tangerang Selatan.
Tanggapan Pembaca atas tulisan di atas
Tulisan diatas telah ditanggapi oleh dua pembaca langsung sebelum diterbitkan. Nama penanggapnya adalah mas Ibob (Gp Widiatmono) dan pak Bambang Nursito. Mas Ibob seorang pengrajin kayu dan pendesain undangan nikahan, kalender dll. Sedang pak Bambang seorang Prodiakon dan pekerja buruh seni di Padepokan Bagong Kussudiardja.
Berikut tanggapan mas Ibob:

Beberapa kali mencoba baca kok kepala malah mendidih 😆
Sepertinya sudah tidak sanggup menerima bacaan yang seperti itu
🥴 (Emoticon Capek dech…)
Apresiasi Gambar:
Lukisan ‘nirestetika’ cukup mewakili begitu semrawutnya wajah kota. Sebuah gambaran dimana pemangku kebijakan yang tidak siap menata wajah kotanya. Tidak sedap juga berbahaya.
“Menyambung Hidup”, menunjukkan hidup mesti luwes mencari peluang. Ketika sektor formal, kerja di kantor tak bisa di dapat, tak perlu malu mencipta kerja sendiri, termasuk melucu di jalanan. Tuk menyambung hidup mesti luwes.
Lukisan ketiga berhasil menggambarkan begitu kompleksnya pemukiman kota. Sempit, berdesakan. Hidup terasa sesak.
Berikut tanggapan mas Bambang:

Bagi saya yang jarang membaca, tulisan ini sangat berat untuk dipahami, tetapi tulisan ini sangat jelas dalam menjelaskan deskripsi tentang kehidupan Jakarta yang semrawut, sing hawane kemrungsung, hawane panas yang disebabkan karena polusi, setelah membaca tulisan ini membawa pikiran kembali ke Jakarta seperti lagune Koes Plus. Apik tulisane..
Gambar :
1. Sangat menterjemahkan keadaan Jakarta dimana instalasi kabel yg ruwet dengan hiruk pikuk keseharian di Jakarta, udara yg tingkat polusinya tinggi, banjir kalua terjadi hujan dan sampah dimana-mana
2. Dengan banyaknya karakter gambar merupakan lukisan yang menterjemahkan bahwa di Jakarta kita harus bisa menjadi badut (bermuka dua) agar bisa diterima dikalangan tertentu.
Gambar ini juga menterjemahkan adanya manusia yang sedang sedih, manusia yang sedang tertawa dan seorang badut menggambarkan anggota DPR yang lucu dengan tingkah lakunya, lucunya mengalahkan seorang pelawak ,,, cen uasuuoooq
3. Di Jakarta memang banyak gedung-gedung bertingkat, bentuknya kotak-kotak dan banyak sekali gang-gang sempit dimana lahan bermain untuk anak-anak sangat minim sekali tanah lapang untuk bermain.