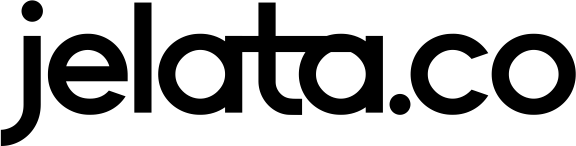Nyanyian dari Teluk Cenderawasih
Laut di sini tidak biru, ia bening seperti mata nenek yang menatap masa lalu tanpa dendam. Di atas perahu, para nelayan mendengar desir ombak seperti bisikan dari arwah yang pernah tenggelam bersama mimpi tentang kebebasan. Sagu dibakar di tangan perempuan yang rambutnya berbau asin, ia tahu: setiap butir garam adalah kesetiaan. Seorang anak menggambar burung di pasir, lalu angin menghapusnya—begitu juga sejarah, kadang disapu sebelum sempat dihafal. Namun, ketika sore tiba, dan bayangan perahu menjadi doa panjang, laut kembali bernyanyi dalam bahasa yang tak bisa diterjemahkan manusia: bahasa yang hanya dimengerti oleh ikan, bulan, dan mereka yang masih percaya pada rumah di bawah cahaya timur.
2025
Tanah yang Menyala di Lembah Baliem
Kabut turun seperti doa yang lupa alamat, di sela lembah, tubuh-tubuh tanah membuka diri pada pagi yang belum punya nama. Di sana, api bukan sekadar panas, ia bahasa para leluhur yang disulut dari batu dan kenangan. Ubi tumbuh dari kesabaran ibu-ibu yang menanam cinta dengan kuku, keladi direbus bersama kabar angin dari masa silam. Seorang anak lelaki meniup abu, memanggil roh yang pernah menulis sejarah di kulit babi dan duri pandan. Di langit, seekor burung melintas, mungkin burung terakhir yang tahu arti rumah. Lalu dunia terasa diam—seakan menunggu manusia kembali mengucap terima kasih pada bumi yang tak pernah menolak luka.
2025
Tifa, Batu, dan Langit yang Tak Tidur
Di Wamena, tifa berdetak seperti jantung bumi yang menolak diam. Api unggun menari di antara wajah-wajah tua, setiap kerutnya adalah peta waktu. Lelaki memukul tanah dengan nada yang membuat roh turun, perempuan menatap langit dengan sabar yang diwariskan dari sagu dan hujan. Daging babi dibagi, bukan untuk kenyang—melainkan untuk mengingat bahwa lapar adalah cara alam menegur manusia. Di antara asap, seseorang berbisik: “Kita ini cuma abu yang belajar jadi cahaya.” Dan malam pun mendengarkan, tanpa bertanya apa itu merdeka. Papua, di sini doa tak pernah selesai, hanya berpindah dari tifa ke batu, dari batu ke langit, dari langit ke dada manusia yang masih berani hidup.
2025
Penulis

Rifqi Septian Dewantara pegiat sastra asal Balikpapan, Kalimantan Timur Mei 1998. Karya-karyanya tersebar di berbagai media online dan majalah digital seperti Media Indonesia, BeritaSatu, Suara Merdeka, Borobudur Writers & Cultural Festival, Bali Politika, Majalah Elipsis, dll. Buku antologi puisinya berjudul “LIKE” (2024) dan “SHARE” (2025) diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi. Kini sedang menyusun buku puisi tunggal “Aku Tidak Datang dari Masa Depan” (Langgam Pustaka, 2025). Bisa disapa melalui Instagram: @rifqiseptiandewantara
Komentar
Semangat dan lebih banyak membaca agar menulis lebih kreatif lagi.
Salam puisi