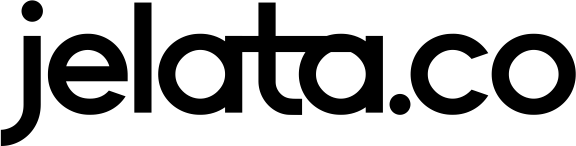Komunitas Mikroba, kelompok yang bergiat di bidang pendidikan, kesenian, pertanian, dan ekonomi mandiri menekankan dirinya bukan NGO, organ pemerintah, dan bukan nabi baru penolong masyarakat. Mereka hanya teman. Argumentasi itu membuat saya melihat bahwa komunitas ini (sadar atau tidak) ingin menarik diri dari wacana representasi atas narasi praktik-praktik kerja partisipatoris ala NGO, dan menitikberatkan pada medan kreatif-kultural. Menarik diri dari konstruksi wacana itu bukan berarti ingin menjadi eksklusif dan elitis lalu mencibir kerja-kerja yang lain. Penawaran kerangka, konsep, dan praktik kerja secara lebih adil dalam menempatkan diri di tengah masyarakat adalah salah satu tujuannya.
Dalam pengamatan singkat, selama kurang lebih dua hari satu malam, ditambah obrolan singkat di Kafe Boenga milik Cak Kepik, saya menyaksikan keriuhan ruang kerja Mikroba dan kisah-kisah tentang Rapah Ombo. Saya membayangkan keduanya seperti dua kutub yang saling bertolak belakang namun bertemu pada titik tertentu hingga luruh menjadi satu bagian. Praktik kerja Mikroba yang berada dalam konstruksi berpikir organisasi ‘pemberdayaan’ dan praktik hidup sehari-hari masyarakat (perfomance of everyday life) lewat kerja tubuh, bahasa, dan kondisi yang melingkupinya cukup menarik untuk dilihat lebih jauh. Tapi, setidaknya kita dapat mengajukan pertanyaan, performance atau perfomance behaviour seperti apa yang diperankan dan dijalankan masyarakat Rapah Ombo? Sejauh mana Mikroba lewat praktik-praktik kreatif-kulturalnya berkontribusi memperbarui peran atau pembentukan yang lain? Setidaknya, dari sana kita dapat melihat peleburan kerja keduanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, atau meminjam istilah Raymond William, mendramatisasi kehidupan (dramatize) dengan lebih baik.
Memungut Remah Kisah Rapah Ombo
Mulanya saya pikir, akan berjumpa dengan ornamen kayu jati menjulang dihias kain warna-warni, senyum-senyum manis nan ramah laki-laki dan perempuan sambil menawarkan brosur wisata tepat sebelah tiket masuk, serta terpampang merchandise terbuat dari kayu jati seperti kebanyakan daerah dampingan pihak lain dalam wacana manajerialisme ekonomi kreatif masyarakat mandiri; visit locality. Sebaliknya, saya malah berjumpa dengan kesederhanaan masyarakat di tepian batas kota Jombang. Dalam keterbatasannya akan akses informasi dan geografis ke tempat lain, masyarakat menjalani drama kehidupan. Di samping itu, masyarakat mengaku tidak memiliki bentuk kesenian lokal (jatilan, ludruk, wayang, atau ritual-ritual tradisi panen, dll). Apa yang akan dikatakan seorang teoritikus atau pemikir melihat masyarakat macam ini?
Performa keseharian (daily perfomance) memang dapat menjadi modus kita untuk memahami kembali diri atau merefleksikan kembali peran dalam kehidupan. Seperti dikatakan Elin Diamond, bahwa performance is always a doing and thing done. Artinya perfomance tidak lagi terpancang pada konvensi-konvensi seni melainkan juga pada konvensi (tatanan) sosial, perilaku, pekerjaan, atau peran apa saja yang dimainkan seseorang dalam keseharian secara performatif. Drama sosial, ruang dan waktu (space and time), baik dimaknai secara sadar atau tidak dalam kompleksitasnya juga bagian dari performance seseorang. Misalnya, saat seorang petani Rapah Ombo, berperan menjadi petani padi dalam kompleksitas ruang dan waktu; lingkungan minim air, tanah berlumpur abu, tidak semua lahan produktif, absennya peran negara, sementara di satu sisi mereka harus tetap menjalankan hidup, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di satu sisi kita melihat betapa tubuh mereka seolah ingin melampaui keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami sebagai bagian dari menghidupi perannya sebagai petani.
Namun performance selalu punya rujukan, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung, sifatnya material maupun imajiner, besar atau kecil pengaruhnya. Akan tetapi ujaran (perilaku) sehari-hari (speech act of everyday life) biasanya sangat mendasar dalam setiap subjek-kelompok, karena dari sana kita bisa melihat interkoneksitas antara subjek dan sesuatu di luar dirinya. Saya melihat, adanya peran pengalaman di masa lalu yang andil dalam pembentukan subjek masyarakat Rapah Ombo. Pengalaman masa lalu itu bersumber dari babad kampung, kolonialisme, dan masa revolusi kemerdekaan.
Konon, babad ini dimulai dari kisah pencurian sapi oleh empat orang, terdiri dari tiga bersaudara dan satunya adalah teman biasa dari Lamongan. Menurut cerita yang berkembang, pencurian itu dilakukan dalam kondisi terpepet (entah terpepet oleh kondisi ekonomi, politik, atau soal kenakalan anak muda), tapi yang jelas mereka mencuri sapi milik warga. Mereka dikejar-kejar warga, hingga pada akhirnya tertangkap kemudian disandera di sebuah kandang sapi sebagai hukumannya. Entah berapa lama masa hukuman itu. Babak selanjutnya, mereka dapat bebas namun mereka tidak bisa pulang ke rumah asalnya dikarenakan adanya sanksi moral dari masyarakat. Masa pembebasan kemudian berlanjut pada pengembaraan menyusuri hutan untuk bermukim, hingga akhirnya mereka mendapat rumah baru berupa dataran luas dihimpit berbagai bukit rimbun, yang mereka namai Rapah Ombo. Rapah Ombo diambil dari sifat atau identifikasi alam, Rapah (dataran) Ombo (luas). Masyarakat mempercayai hal tersebut sebagai asal-usul kampungnya. Sebagai folklor memang tidak diketahui benar dan tidaknya, tapi mereka mempercayai hal tersebut sebagai fakta di masa lalu. Namun, baik sebagai fakta di masa lalu atau mitos, kisah kampung masih dianggap penting oleh masyarakat, bahkan hingga sekarang masih terus dituturkan. Secara tidak langsung, babad ini dipersepsi sebagai bagian dari identitas diri.
Di samping itu, memori masyarakat akan kolonialisme masih cukup kuat meski nilainya tidak lagi sama atau sudah bergeser. Ketika saya menanyakan salah satu brug atau jembatan yang terbuat dari material kereta api (rel kereta dan bantalan kayunya) mereka menjawab, “oh, itu treteg rel”. Beberapa orang memang mengatakan, termasuk Sinyo, salah satu kolega Mikroba, bahwa kolonialisme memang menginjakkan kaki di dataran luas ini guna mengambil gelondongan kayu jati dan menggunakan kereta api sebagai alat transportasi pelangsir hasil bumi. Ingatan terhadap situs berupa peti baja tempat pengambilan upah para penebang jati yang diisi oleh masinis setiap hari Sabtu, masih diarsipkan masyarakat sebagai ingatan kolektif. Cara memaknai situs ini agaknya tidak penuh amarah dan rasa dendam, mungkin lebih sebagai rujukan bersama bahwa kolonialisme pernah menancapkan kaki di sana.
Ingatan lain yang masih mereka rawat adalah soal surat balas budi Brigjen Kretarto, orang yang cukup berjasa di kawasan itu. Tanpa ada instruksi dari kaum nasionalis, masyarakat turut andil dalam pengusiran penjajah Jepang, membantu kerja Brigjen Kretarto di batalyon Siliwangi. Sekitar tahun 1950 akhir, Kretarto melayangkan surat balas budinya pada masyarakat Rapah Ombo. Sayang, karena singkatnya waktu dan padatnya acara, saya tidak berhasil melihat isi surat itu. Tapi, saya jutru bertanya apa signifikansi ketiga memori itu, apakah ia membentuk mentalitas penghamba, mandiri, romantik, heroik, atau justru tidak semuanya?
Ketika saya berkeliling di sekitar kampung, nampak bangunan Sekolah Dasar tak terawat; baik bangunannya maupun fungsinya sebagai aparatus pendidikan negara. Beberapa tahun belakangan ini Sekolah Dasar tersebut tidak beroperasi, bukan karena minimnya minat anak-anak bersekolah dan dorongan dari orangtua, melainkan ketidaktersediaan tenaga pengajar. Meski beberapa kali, tenaga pengajar pemerintah maupun pihak lain, seperti Universitas Negeri Surabaya (UNESA), atau organisasi independen lain melakukan kegiatan belajar mengajar di sana. Namun persoalan jarak dan medan menjadi kendala utama; jalan berbatu, terjal, dan curam terlebih saat hujan menjadi salah satu faktor besar macetnya aktivitas itu. Tidak jauh dari situ, saya mendapati instalasi listrik pemerintah masih bersih dan baru menjulang tinggi. Menurut penuturan warga, Pembangkit Listrik Negara (PLN) baru berdiri satu tahun lalu (2017), sebelumnya masyarakat hanya memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun sekitar tahun 2003 guna memenuhi kebutuhan.
Bagi kita yang berpikir logis, dalam kondisi seperti itu mestinya timbul sikap resisten, tapi berbeda cara masyarakat menghadapi situasi di sini. Jika tidak bisa dikatakan resisten, mereka bekerja segiat dan seloyal mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka bisa hidup dalam segala keterbatasannya. Bukankah ini lebih produktif? Di samping itu aktivitas kerja sehari-hari memberikan gambaran lain, di saat masyarakat urban merasa pekerjaan mengalienasi dirinya, saya melihat performa mereka menjalani kehidupan di tengah keterbatasan justru menjadi plesure dari adanya penyatuan diri dan pekerjaan; tidak menjadi beban dan lahir keluh kesah. Hal itulah salah satu yang saya tangkap dari gesture sosial atau gesture individu mereka dalam melakoni hidup sehari-hari yang tampak menarik sebab seperti berupaya melawan keterbatasannya.
Anehnya, menurut Sinyo, mental inferior, minder, merasa ‘kurang maju’ justru terlihat cukup dominan, khususnya saat mereka berhadapan dengan orang lain. Itu terlihat dialami baik anak kecil, para petani, maupun masyarakat lain. Acapkali personil Mikroba mencoba mengakrabi masyarakat sekitar; tetapi obrolan mandheg. Titik inilah yang menjadi kunci Komunitas Mikroba mengerjakan agendanya.
Mikroba dan Teman Setia
Mikroba bukan satu-satunya komunitas yang pernah bekerja di Rapah Ombo. Sebelumnya, beberapa LSM, atau mahasiswa-mahasiswa dari universitas di Jawa Timur sempat menjalin hubungan kerja, tapi pada akhirnya, karena suatu alasan dan lain-lain mereka tidak melanjutkan aktivitas di sana.
Secara organisasi Mikroba cenderung mandiri dan solid. Artinya tidak memiliki ketergantungan dan terpaku pada pihak tertentu, misalnya sumber donor atau kekuasaan lain di luar dirinya. Meski sesekali mereka mengambil bibit pemerintah atau dana sumbangan perorangan, tapi tidak mengubah tujuan organisasi. Bantuan dimanfaatkan untuk melapangkan jalan menemani masyarakat.
Sebagaimana hubungan pertemanan, kedekatan dan kerenggangan sebuah relasi adalah keniscayaan. Beberapa kali konflik-konflik kecil antara masyarakat dan Mikroba terjadi, namun pada akhirnya dapat terselesaikan. “Kami menjalin pertemanan di bidang pendidikan, pertanian, ekonomi mandiri, dan lain lain, tapi yang lebih utama adalah sebagai manusia,” ucap Sinyo. Perkataan itu secara tersirat menjelaskan kepentingan politis mereka, yaitu sebagai teman sesama, berbeda dari organisasi lain yang seringkali sekadar memenuhi agenda organisasi atau mengusung motif ekonomi. Di saat bersamaan, Mikroba terhindar dari label heroisme sosial.
Pendekatan partisipatoris memang sedang marak akhir-akhir ini, tidak hanya di kalangan gerakan sosial tapi juga di kalangan kebudayaan. Lalu apa yang menarik dari Mikroba? Mereka mula-mula mengerjakan persoalan di bidang pendidikan sebagai gejala yang perlu direspon. Di tengah absennya pemerintah mengulurkan tangannya terkait pendidikan di Rapah Ombo, Mikroba mencoba masuk, mengisi, dan memanfaatkan ruang aparatus pendidikan. Dengan keterbatasan akan wacana pendidikan, mereka mengadopsi sistem pemetaan (mapping) yang mereka dapat dari bahan bacaan maupun tradisi universitas; membuat outline; sumber daya alam, pembagian kelompok yang berpotensi konflik sosial, aktivitas manusianya, sejarah masyarakat, dan bahkan sampai pendapatan per kapita. Hasil pembacaan tidak lantas mereka terapkan untuk membaca masyarakat sepenuhnya, cukup sebagai bekal menghubungkan, mengkomparasi, dan menemukan titik temu dari konstruksi berpikir sebagai ‘orang luar’ (outsider). Titik beratnya tidak lain untuk menginvestigasi perilaku masyarakat atau dalam istilah perfomance studies disebut behaviour performance yang berangkat dari disiplin antropologi sosial. Menariknya, konsep itu justru muncul dari praktik lapangan:
“Aku dudu wong buku, aku ngerti mergo aku medhun. Ono wong ngomong Romo Mangun aku yo gak ngerti! Aku sinau seko masyarakat, ngerti kahanane wong. Seko kono aku sinau akeh, mereka ki pinter, mulo aku meh sinau seko masyarakat”.
Posisi pengajar lebih banyak sebagai saksi dan pendengar, posisi yang diupayakan sebagai suatu penghargaan. Pemilihan posisi sebagai seorang pengajar macam itu memungkinkan seorang siswa merasa dihargai perannya sebagai manusia Rapah Ombo beserta seluruh pengalaman dan pengetahuannya. Dari sanalah penghormatan antara si pengajar dan peserta didik lahir. Sehingga, saat Sinyo menginstruksikan sesuatu, siswa segera merespon tanpa paksaan. Aktivitas berjalan secara inklusif tanpa otoritas serupa polisi yang mengawasi gerak gerik siswa, dengan kata lain siswa dibebaskan untuk memilih. Tidak jarang pula, para peserta didik diajak bermain di sekitar permukiman seperti hutan jati, sawah, dan area setempat. Entah bermain drama atau mengenali alam. Sinyo ingin membawa konsep, di manapun tempat dapat dipakai sebagai sekolah dan tempat bermain. Sistem ini memang memunculkan kembali keakraban dan proses pertukaran peran antara peserta didik dan pengajar. Sesekali ia mengajak anak-anak untuk membaca dan menulis puisi sebagai proses belajar menulis, merasakan, dan berani tampil agar hilang rasa malu. Memang saat pertunjukan malam itu (31/4), saya menyaksikan ada yang menarik, ketika seorang anak membacakan puisi tentang seorang ayah yang meninggal digigit ular dengan nada cukup haru. Keberanian perform anak-anak Rapah Ombo tampil di publiknya, ditonton orangtuanya, kakeknya, neneknya, masyarakatnya, tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan sebelumnya jika Mikroba datang, anak-anak lari dan bersembunyi di rumahnya masing-masing. Keberanian itu memang hal yang paling nampak dari individu-individu Rapah Ombo. Kita tidak tahu bagaimana performa mereka yang tidak teramati setiap detik-menitnya, seperti cara mereka berpikir, memandang dirinya dan masyarakat, atau saat mereka berlaku sehari-hari. Akan tetapi, hal ini menunjukkan ada proses penarikan kembali sesuatu yang terlepas dan penubuhan kembali mereka sebagai manusia yang setara.
Metode pendekatan pertemanan dan sistem kultural kembali dipraktikkan dalam bidang pertanian, yaitu ketika workshop pembuatan Pupuk Organik Cair (POC). Monopoli pupuk dan ketergantungan pupuk di kalangan petani menjadi kasus mendesak yang segera direspon oleh Mikroba. Monopoli pupuk dilihat cukup bermasalah, selain monopoli ekonomi atas sentralisasi distribusi pupuk urea yang dikuasai oleh pemodal lokal sehingga membuat para petani menjadi sangat bergantung pada satu produk, selain sistem pembayaran yang tidak adil; petani dibebaskan membeli pupuk tanpa uang muka dan tak perlu kontan, namun sebagai gantinya hasil panen dimonopoli kembali dengan dipotong pembelian pupuk urea. Lewat pembongkaran secara halus, Mikroba yang dibantu oleh Hakim, salah satu lulusan mahasiswa pertanian, membuat tandingan produk. Kemudian secara massal membagikan proses pembuatan POC. Bahan-bahan material pupuk juga diambil dari apa yang ada di masyarakat, seperti air kencing sapi, bayam, kelor, dan lain-lain. Hasil pupuk didistribusikan kembali ke masyarakat. Keuntungan penjualan pupuk, rencananya akan dibuat badan usaha berbasis koperasi. Beberapa usahanya sudah berjalan, seperti ternak lele dan madu hutan.
Penutup
Proses perjumpaan performance everyday of life Rapah Ombo dan proses interaksi Mikroba, sedikit besar berpengaruh pada dramatisasi kehidupan masyarakat. Mikroba tidak mengubah gesture sosial masyarakat Rapah Ombo sepenuhnya. Kerja-kerja Mikroba seperti memberikan gambaran lain atas peran-peran yang telah ada sebelumnya. Saya sempat tersentak, ketika salah satu petani laki-laki di workshop pupuk POC nyeletuk, “Ra ono kami tup gak patheken, aku iso isih iso urip!”. Kepercayaan diri untuk tampil ‘menyutradarai hidupnya’ bagi saya adalah tindak performatif seseorang ketika dia mampu melihat kembali dunia baru dengan lebih optimis. Ujaran atau speech act oleh petani itu tentu tidak hanya berlaku secara monolitik; ia hidup untuk membuktikan pada kekuasaan bahwa dia mampu bekerja, tapi juga bahwa hidup pada dasarnya adalah kerja itu sendiri. Tanpa bekerja manusia tidak akan pernah bisa melakukan perfomance karena perfomance pada mulanya adalah doing and things done. Memerankan dan berperan.***
PENULIS
FEBRIAN ADINATA HASIBUAN lahir di Temanggung, 16 Februari 1991. Menyelesaikan pendidikan tinggi (S2) di Fakultas Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dengan konsentrasi studi teater dan performatifitas. Mengawali kegiatan seni bersama Teater Teksas, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Pada 2014 turut membentuk Kolektif Kaleng Merah. Saat ini bermukim di Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat ini aktif berkegiatan dalam penelitian dan pengamatan khususnya seni rupa.