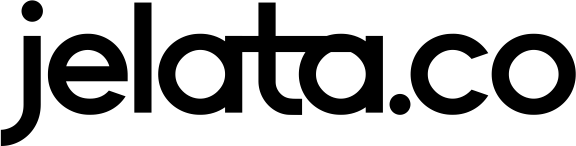Apakah salah jika menonton teater tidak diniatkan sebagai hiburan? Sama sekali tidak. Justru, menonton teater sebagai sarana belajar dan refleksi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mencari tawa. Dalam teater, setiap detik adalah peristiwa yang tidak akan terulang. Seperti kata Antonin Artaud dalam The Theatre and Its Double (1938), “Teater adalah kehidupan yang ditekankan, bukan sekadar tiruan kehidupan.” Maka rasanya sayang bila pengalaman menonton teater hanya dilewatkan sebagai hiburan belaka.
Teater adalah proses hidup yang kompleks. Ia bukan hanya pertunjukan, tapi juga terapi, eksperimen batin, dan pengalaman eksistensial yang jarang terjadi. Menontonnya dengan kesungguhan berarti membuka diri terhadap kemungkinan belajar — dari tubuh, emosi, dan bahkan absurditas manusia itu sendiri. Hiburan sejati mungkin ada pada film yang bisa diputar ulang tanpa perlu “mengerinyitkan dahi”. Tapi teater? Ia hadir hanya sekali, meski dipentaskan ulang, ia tak akan pernah sama, dan selebihnya tinggal menjadi ingatan.
Lalu, ada apa dengan penonton teater kita? Mengapa ketika adegan slapstick muncul, ruang justru nyaris terbahak-bahak? Mungkin benar seperti kata Atsuko Okatsuka, pelawak Jepang yang kini menetap di Amerika, bahwa “selera humor bertumpu pada literatur, dan tawa terbahak-bahak adalah milik mereka yang tak punya.” Apakah kita menertawakan panggung, atau sebenarnya sedang menertawakan hidup kita yang terlalu berat hingga tawa menjadi satu-satunya pelarian?
Dalam Jokes and Their Relation of the Unconscious karya Sigmund Freud (1905) dijelaskan bahwa tertawa adalah bentuk pelepasan energi psikis dan represi yang memiliki fungsi katarsis. Pandangan psikoanalisis menerangkan manusia seringkali menahan berbagai dorongan -terutama hasrat seks dan agresivitas- yang berbenturan dengan norma. Sehingga tertawa menjadi katup pelepasan tekanan tersebut.
Freud membagi tiga bentuk ekspresi yang menghasilkan tawa: (a) Lelucon atau lawakan (joke) adalah cara tidak langsung untuk mengungkapkan sesuatu yang dilarang atau ditekan. Seperti berbicara soal politik atau seksual yang dianggap tabu, yang mungkin dirasa tidak pantas untuk dibicarakan secara sosial. Sehingga melalui lelucon, dorongan untuk membicarakan hal tersebut bisa dilepaskan dan manghasilkan tawa. (b) Komedi yang menunjukan ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan atau kelebihan dan kekurangan seseorang. Dalam bentuk ini seseorang -penonton- tertawa karena merasa superior atas objek yang ditertawakan. Misalnya dalam komedi slapstick, di Indonesia seringkali disebut ‘srimulatan’ -mengacau pada kelompok komedi Srimulat yang berdiri sejak tahun 1950 dan identik dengan gaya komedi slapstik. Seperti orang jatuh, terpeleset, kaki terinjak, mata kecolok, laki-laki yang berdandan seperti perempuan dengan berlebihan dan sebagainya yang behubungan dengan fisik dan visual.
Pada tahun 2000an tayangan komedi Opera van Java di salah satu stasiun Televisi swasta Nasional sangat digemari masyarakat dengan menghadirkan komedian Azis Gagap sebagai objek ‘penderitaan’, ia kerap kali mendapat bulian dan dipukul oleh stik properti yang terbuat dari stereofoam. Aksi tersebut mengundang gelak tawa penonton dan selalu diulang pada tiap episode. Freud melihat bentuk komedi ini sebagai pembebasan energi represi sosial, dimana penonton bisa menertawakan kelemahan orang lain tanpa rasa bersalah. Perilaku tersebut merupakan bentuk pemuasan dorongan agresif dan narsistik yang ditekan oleh norma sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketegangan emosional, mungkin merasa rendah diri, frustasi sosial atau perasaan marah yang tak bisa diunkapkan secara langsung. Sehingga tawa merupakan katup pelepasan energi represi. Dengan menertawakan kelemahan orang lain, sementara waktu penonton merasa lebih kuat, lebih pintar, atau berharga dibandingkan dengan yang ditertawakannya. Freud menyebutnya sebagai kompensasi psikologis terhadap perasaan tak berdaya.
Orang-orang atau penonton yang mudah tertawa dengan bentuk humor ini melampiaskan agresinya (karena menekan banyak emosi negative seperti marah, benci, iri, dsb) dengan jalan yang aman tanpa melanggar norma sehingga dapat mengembalikan kondisi psikis. Dengan menertawakan orang lain Freud mengatakan dalam hierarki simbolik, penonton dalam kondisi sementara bisa merasa ‘naik tingkat’ dan menutupi luka harga diri sendiri.
(c) Humor satir, merupakan bentuk kemenangan ego untuk menolak tunduk pada realitas pahit, bahkan menjadi tanda kedewasaan psikis menurut Freud. Seperti situasi “Aku tidak berangkat ke Jakarta besok, semoga mantan di sana tak salah paham – ini bukan karena aku sudah ikhlas, cuma belum cukup ongkos.”
Namun, siapa bilang tertawa itu dosa? Kadang tawa adalah cara paling jujur tubuh memahami kebenaran yang terlalu pedih untuk ditangisi. Belajar dan refleksi tak selalu harus bersujud dalam diam. Mereka bisa lahir dari ledakan tawa — dari absurditas hidup yang disadari sepenuhnya. Mungkin bukan soal sering tertawa atau sedih, tapi kapan tawa dan sedih itu benar-benar punya makna.
Mengutip Schopenhauer dalam buku “Ketawa itu Obat, Ketawa itu Racun?” oleh Dr. Beni Kurniawan, tertawa adalah respon yang datang dari sesuatu yang dibilang sebagai “the ludicrous”, yaitu suatu ketidaksinambungan persepsi. Pelepasan ketegangan seperti yang dikatakan oleh Freud, dapat merangsang perasaan senang dan positif. Sebuah penelitian yang dirangkum dalam buku Anatomy of An Illness dari Norman Cousins – seorang jurnalis- berdasarkan pengalaman pribadinya melawan penyakit ankylosing spondylitis — penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan parah pada tulang belakang dan sendi dan hampir lumpuh, ia menyarankan seseorang tertawa 5-10 menit dalam sehari. Karena tertawa dapat menurunkan kadar hormone stress, memproduksi endorphin -zat Kimia otak yang memberi rasa bahagia dan menekan rasa nyeri- sehingga memberikan efek terapeutik nyata, menghubungkan tubuh, pikiran, dan emosi.
Menonton teater berarti menonton kejujuran tubuh, bukan kepalsuan emosi. Tawa yang muncul dari tubuh yang benar-benar hadir di panggung bukanlah sekadar hiburan administratif, melainkan refleksi spontan dari kehidupan.
Ada banyak naskah teater yang menggambarkan penderitaan sosial dengan komedi satir. Seperti Opera Kecoa karya Nano Riantiarno, Orang Kasar karya Anton Chekov terjemahan WS. Rendra, Setan Bla Bla Bla karya Arthur S. Nalan, dan banyak lainnya. Bentuk komedi yang ditawarkan dalam naskah-naskah tersebut beraneka ragam dan sangat bergantung pada penggarapan sutradara. Mulai dari slapstick, satir, parodi, situasi komedi (sitcom) bisa menjadi konten yang menarik. Memberi pengalaman berkesan kepada penonton yang tak hanya mengajak untuk berfikir tapi juga menghibur.
Adorno dalam Chaplin Times Two, The Yale Journal of Criticism 9.1 (1996) terjemahan oleh John MacKay berbicara tentang seni modern dan estetika sebagai bentuk otonom yang mengandung “negative dialectics” dan sebagai “social antithesis of society”. Karya seni yang benar-benar memiliki daya kritis adalah yang tak hanya melayani pasar atau hiburan, tapi tetap menjaga jarak dan ketegangan terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada. Seni -salah satunya teater- memiliki truth content (Wahrheitsgehalt) yang bukan hanya pesan politis langsung tapi kritik yang masih terkandung dalam bentuk dan struktur estetik.
Tak seperti kultur industri dimana karya seni atau hiburan massal cenderung kehilangan kemampuan kritisnya karena diarahkan oleh pasar dan logika produksi massal. Sementara teater cenderung mempertahankan otonomi dan menawarkan sudut pandang yang kritis, terutama bagi kelompok kecil independent yang kuat mempertahankan ideologinya. Pada disertasi Julia Jarcho: Negative Theatrics: Writing the Postdramatic Stage (2013), terdapat uraian bahwa “art becomes social by its opposition to society, and it occupies this position only as autonomous art.”
Pada akhirnya, tawa dalam teater bukanlah kesimpulan moral. Ia adalah gejala keberadaan, tanda bahwa tubuh penonton ikut bereaksi terhadap kehidupan yang dipentaskan di hadapannya. Kadang, tawa tak perlu ditafsir. Biarkan ia liar, biarkan ia menertawakan tafsir itu sendiri. Sebab mungkin, seperti kata Sang Burung Merak, Rendra, “Teater adalah cermin. Dan yang kita lihat di sana bukan aktor, tapi diri kita sendiri.”
Dengan demikian, menonton teater bukan soal mencari hiburan, tetapi soal menemukan kembali diri — di antara tawa, refleksi, dan kejujuran tubuh yang sedang berbicara. Seperti yang pernah disinggung oleh sutradara teater Jerzy Grotowski, “Tubuh aktor adalah instrumen spiritual.” Di situlah logika dan insting saling bertarung. Tubuh aktor menjadi arena di mana kejujuran diuji — bukan melalui kesempurnaan gerak, tapi dari spontanitas yang memunculkan tawa, air mata, dan kesadaran.***
Penulis

Rika Rostika Johara pernah belajar di Fakultas Psikologi UIN Jakarta, pegiat teater dan jurnalis, tinggal di Kota Tasikmalaya