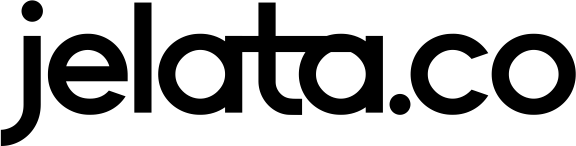Yang kangen desa bisa mendengarkan lagu-lagu Ebiet G Ade, Iwan Fals, atau Franky Sahilatua. Mereka sebenarnya bukan musisi desa. Buktinya lakon bermusik mereka berpusat di kota. Oh, mereka tidak melupakan desa! Yang diungkapkan dalam lagu tidak hanya keindahan, ketenteraman, dan keindahan.
Lagu-lagu yang tidak romantis melainkan menguak tragis. Desa yang terdengar dari lagu adalah desa yang sangat dipengaruhi kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru. Duh, cara pikir yang keterlaluan bahwa kekuasaan menentukan nasib desa. Yang berpikir seperti itu adalah aku yang sedang bodoh dan gagal logis.

Aku dilahirkan di desa. Kini, aku masih berada di desa, cuma bergeser sedikit dari rumah-kelahiran. Harga tanah yang mahal tidak memungkinkan aku tinggal di dekat rumah yang menjadi pusat keluarga besar. Jadi, gagasan harus di tanah-asal dapat sedikit dibantah gara-gara uang. Wah, desa yang terlalu cepat berubah. Apakah itu membuktikan kemajuan?
Beberapa hotel mengubah desa. Perkantoran pemerintah dan perusahaan ikut meramaikan desa. Sekolah atau kampus makin bikin desa menjadi padat. Rumah makan dan kafe ikut mendefinisikan desa. Waduh, desa bakal hanya sebutan setelah ruang dan tata cara hidup “terpaksa” berubah! Konon, desa itu memiliki ketentuan-ketentuan, tidak hanya nama “administratif” dan kesan yang diwariskan para leluhur.
Franky Sahilatua membayangkan: Sekarang semua telah kutinggalkan/ Gedung-gedung dan bising jalanan/ Di hatiku kugenggam kerinduan/ Pada bukit perdesaan// Kini musim demi musim lewat lebih indah/ Matahari bersinar menembus ke dalam hati/ Membawa pesan kedamain// Sekarang semua telah kutingglkan/ Tembok-tembok tinggi dan kepalsuan/ Kuayunkan langkah kurentangkan tangan/ Di bukit-bukit perdesaan. Lagu yang terdengar sejak 1987 itu mengingatkan kebingungan manusia-manusia Indonesia yang berada di kota dan desa. Orde Baru sedang “berteriak” pembangunan nasional, yang menginginkan modernisasi desa. Namun, ada yang ingin desa tetap seperti dulu saja.
Nah, desaku terlalu berubah! Desa yang tidak pernah dibuatkan lagu atau puisi. Desa yang terbiarkan tanpa sejarah tertulis. Anehnya, desa itu perlahan terkenal disebabkan rumah. Ya, rumah yang bakal dihuni tokoh besar beralamat di desa. Rumah yang disebut persembahan negara untuk sosok yang menjadi presiden selama sepuluh tahuh. Ia kelak menghuni rumah di desa yang berubah, bukan di Solo. Desa yang memang berdekatan dengan Solo. Percayalah bahwa desaku bukan desa seperti dalam lagu Franky Sahilatua, Ebiet G Ade, atau Iwan Fals. Desa yang membuatku sulit memiliki nostalgia melalui pohon, batu, sungai, rumah, dan lain-lain.

Aku tetap mengaku sebagai “anak desa”. Walah, pengakuan yang salah jika aku mengingat sebutan itu sah milik Soeharto. Bacalah buku yang ditulis Roeder dalam terjemahan bahasa Indonesia! Soeharto adalah “anak desa” yang berhasil menjadi presiden. Dulu, ia disebut “Bapak Pembangunan Indonesia”, bukan “Bapak Desa Indonesia”. Aku yang lahir di desa mustahil mengikuti jejak Soeharto menjadi presiden. Yang bisa aku wujudkan adalah menjadi pecundang, keparat, dan durjana.
Mengapa pengakuan “anak desa” membuat Soeharto tenar dan berkuasa dalam waktu yang lama? Dugaan: desa menjadi “tema” yang membesarkan Soeharto dalam mencipta kepatuhan dan ketertiban untuk berkuasa. Dugaan yang tidak berdasarkan argumentasi yang jelas. Anggaplah itu kengawuran. Yang teringat: pengaruh Soeharto di desa-desa memang kuat banget. Aku masih merasakannya sampai sekarang.
Yang mengolah tema desa cuma Soeharto? Jawabannya: tidak. Soekarno mendahului dalam mengartikan desa. Ia tidak mengharuskan masalah desa sering muncul dalam pidato atau tulisan. Namun, bukti-bukti bahwa ia memikirkan desa masih dapat ditemukan meski orang-orang mengingat Soekarno dengan pertumbuhan kota-kota yang menyatakan revolusi dan kemodernan di mata dunia.
Pada 1953, terbit buku merah berjudul Desa. Buku lawas yang berkhasiat bagi pembaca yang ingin mengetahui lakon desa di Indonesia, dari masa ke masa. Di halaman awal, penulis yang bernama Soetardjo Kartohadikoesoemo memberi ucapan “politis” menggenapi foto dirinya. Kita membaca: “Dipersembahkan kepada dwitunggal (Bung Karno-Bung Hatta). Tuwuh sakin katresnan dumateng tiang sepuh mangesti luhur rahajuning nuso lan bongso.” Di bawahnya, ada tanda tangan. Pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Agustus 1953. Artinya, desa ada kaitannya dengan sejarah dan kemerdakaan Indonesia. Desa jangan dilupakan! Desa jangan ditelantarkan!

Apakah buku itu dibaca orang-orang yang pernah menjadi menteri mengurusi desa? Ah, kita meragu mereka membaca buku lama. Padahal, Indonesia memiliki menteri baru yang bertanggung jawab memuliakan dan memakmurkan desa. Duh, aku tidak mengetahui namanya. Pokoknya, rezim Prabowo-Gibran masih memikirkan desa. Buktinya, ada menteri desa dalam kabinet. Menteri yang pasti tinggal dan sibuk di kota, bukan berada di desa-desa di seantero Indonesia. Pendapatku itu keliru?
Aku yang betah di desa mulai mengimpikan ada kebijakan-kebijakan pengisahan desa oleh pemerintah. Maksudku, pengisahan itu menjadi siasat pendokumentasian desa yang dapat menjadi pijakan pemajuan desa. Nah, masalah itu berkaitan tulisan, foto, gambar, film, lagu, dan lain-lain.
Bagaimana caranya mendokumentasikan desa dengan sederhana tapi bermakna? Yang menjawab bukan presiden atau menteri. Aku ingin membuatnya tapi malah dirundung bingung. Inginku dokumentasi terwujud sebelum Joko Widodo menghuni rumah di Blulukan. Ingat, desa itu terlalu berubah dan cepat kehilangan jejak-jejaknya.
Penulis