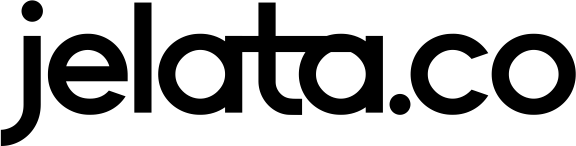Prima Sulistya, teman sekaligus editor saya untuk buku Aku dan Film India Melawan Dunia (dua jilid, terbit 2017), sempat membuat saya marah. Saya selalu menyukai cara kerja dan hasil kerja Prima, salah satunya karena ia tidak sekadar jadi tukang periksa aksara, tidak semata jadi juru bicara EYD dan kepanjangan tangan KBBI, dan—yang idealkan dari seorang editor—ia teguh dan tanpa ragu dan karena itu siap berhadap-hadapan dengan penulis. Tapi kali ini saya tidak bisa membiarkannya.
Jika saja ia memotong satu kalimat atau bahkan satu paragraf, lalu memberi penjelasan bahwa kalimat itu tidak perlu atau menimbulkan regresi yang membuat pembaca kehilangan fokus, saya mungkin bisa terima. (Ya, di kalangan penerbit saya memang punya reputasi sebagai penulis keras kepala bahkan egois yang mempertahankan setiap kata dan titik-koma di naskah saya, tapi sebagai orang yang pernah lama bekerja di penerbitan dan lama bekerja sebagai editor dan tahu logika penerbitan, saya sangat bisa dinego—tinggal apakah Anda bisa meyakinkan saya atau tidak). Tapi apa yang dilakukan Prima kali ini tidak berterima lagi.
Satu nama yang saya tulis di naskah itu tidak ia kenali. Karena ia editor yang teliti, ia cek nama tersebut di internet, sebagaimana nama-nama atau hal-hal lain yang ia merasa asing dan perlu konfirmasi. Rupanya ia tidak menemukannya di mesin pencari. Dan setelah beberapa kali mencari, ia memutuskan mengganti nama yang saya tulis dengan nama yang selalu muncul dalam pencariannya. Mungkin dalam asumsinya saya salah ketik atau salah mengeja. Masalahnya, nama baru yang ditemukannya itu sama sekali tidak saya kenali.
Nama yang saya tulis adalah Peng Tan. Prima yang tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar siapa Peng Tan menggantinya dengan satu nama yang selalu muncul ketika ia mengetikkan nama Peng Tan: Diana Pang. Tapi siapakah Diana Pang? Dan mengapa ia ada di buku yang saya tulis?
Ini bukan lagi kecerobohan—kesalahan yang lumrah dilakukan seorang editor; ini adalah sebuah serangan. Prima tidak sedang mengoreksi naskah saya; ia mengoreksi ingatan saya. Itu artinya ia mengoreksi saya. Dan untuk orang yang sangat percaya diri dengan kemampuan daya ingat sendiri macam saya, dan sangat bangga dengan itu, saya terluka.
Kami pun bertengkar.
***
Peng Tan untuk saya adalah sebuah ingatan yang terang, sangat meyakinkan, bahkan fotografis. Saya tak ragu sama sekali tentang itu.
Sekitar Juni 1998, tak lama setelah huru-hara Mei terjadi, kami bersepuluh, saya dan teman-teman se-SMA dari Lamongan, datang ke Jogja untuk menyiapkan diri menyongsong ujian masuk perguruan tinggi (UMPTN) tahun itu. Kami menyewa kos secara bulanan di sekitaran Sapen, di belakang kampus IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, dua orang untuk tiap satu kamar. Delapan di antara kami tiap hari berangkat ke tempat Bimbingan Belajar, sementara dua sisanya, salah satunya saya, “belajar mandiri”—karena tak sanggup membayar biaya bimbingan. Sepulangnya kedelapan orang dari bimbingan, sekitar jam setengah lima sore, kami sering berkumpul beramai-ramai di kamar seorang mahasiswa Fakultas Dakwah yang jadi senior dadakan kami, biasanya untuk berbagi pertanyaan di antara kami apakah ada contoh soal baru yang dibawa dari bimbel, atau adakah trik khusus untuk menyelesaikan satu soal Matematika atau Fisika yang sudah berbulan-bulan diutak-atik dan gagal, atau sekadar kongko-kongko biasa, gitaran dan nyanyi-nyanyi, atau semata beriung mendengar lagu-lagu dari radio. Senior ini, konon pernah lulus masuk Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sebelum memutuskan pindah ke IAIN Jogja, tempat kami bertanya bagaimana rasanya menempuh UMPTN—apakah sebaiknya kita harus bawa pensil 2B lebih dari satu atau cukup bawa rautan saja, apakah kita bisa bawa penghapus biasa saja atau perlu penghapus merk tertentu, apakah boleh menyingkat nama di borang soal, atau hal-hal lain macam itu. Ia juga banyak memberi petunjuk soal Jogja, semisal kalau mau ke mana naik bus kota jalur berapa dan berapa biayanya—saat itu bus kota di Jogja sedang jaya-jayanya. Di kamar ini pula, seingat saya, saya ditegur olehnya karena memutuskan memilih Sastra Indonesia sebagai pilihan terakhir sekaligus pilihan jurusan ilmu sosial satu-satunya dari tiga pilihan. “Sayang IPC-nya kalau cuma pilih Sasindo,” katanya.
Saya tidak mengingat apakah di kamar itu banyak buku atau tidak (satu hal yang nantinya menjadi standar saya dalam memilah mana mahasiswa baik dan mana mahasiswa buruk), tapi biasanya di situlah kami akan membaca koran secara keroyokan. Hampir pasti bukan koran yang selalu baru, tapi juga bukan koran bekas; saat itu Piala Dunia 1998 sedang berlangsung, dan penggila bola macam saya tak mungkin melewatkan berita termutakhir dari Prancis. Dan, saya rasa, di koran itu pula (bisa dipastikan koran lokal Jogja, meski saya lupa apakah itu KR, Bernas, atau Jogja Pos), di halaman iklan bioskop, sebuah pemandangan khas koran era ‘90an, saya temukan nama Peng Tan.
Tentu saja industri film dan perbioskopan kita sudah ancur-ancuran saat itu. Bioskop Garuda di Babat, kota kecamatan tempat saya menempuh SMA, sudah tutup sejak 1995, tahun pertama saya masuk SMA. Demikian juga bioskop di kota-kota kecil lain, semisal di Tuban dan Lamongan atau Gresik. Masa kehancuran itu mungkin tak berbarengan, tapi jelas simultan. Saya kira di Jogja juga demikian. Sebagian besar bioskopnya telah tumbang. Meski, dengan status kota besar sekaligus kota dengan ratusan perguruan tinggi, membuat kota ini relatif masih menyisakan beberapa gedung bioskopnya. Dan, karena itu, halaman iklan bioskop masih kita temukan di koran lokal. Di sanalah nama dan wajah Peng Tan, juga sebagian besar auratnya, atau sesuatu yang digambarkan demikian, bisa ditemukan. Dan judul yang terkenal itu: Erotic Black Magic.
Saya tak yakin apakah itu perjumpaan terakhir saya dengan Peng Tan, sehingga saya merasa perlu untuk menyimpan ingatan itu. (Barangkali karena ia berbarengan dengan hal-hal penting lain yang mengubah hidup saya, semisal kedatangan saya ke Jogja, juga tes masuk universitas negeri dan kemudian lulus.) Tapi itu jelas bukan perjumpaan pertama.
Peng Tan adalah fenomena ‘90an. Anak-anak kota kecil, antara 1995-1998, pasti akrab dengan wajah dan poster filmnya di bioskop kota mereka. Kami, anak-anak desa yang jauh dari bioskop, biasa menemukannya di Jawa Pos atau koran-koran lain yang terbit di Surabaya (Surabaya Post, Surya, dan Memorandum) lewat iklan-iklan bioskopnya yang sangat menonjol, semenonjol halaman berita duka warga Tionghoa.
Peng Tan, dalam kepala saya saat itu, mewakili sesuatu yang tak boleh disentuh, tapi terasa terjangkau. Ia terlihat tabu, namun ada di situ—seperti kolom ikonik Opo Maneh yang mesum itu, yang mestinya dibaca hanya oleh orang dewasa, tapi kisah Bondet dan Susan itu tiap hari nongol di Jawa Pos dan bisa dibaca siapa saja. Peng Tan mungkin tak ditemukan di Layar Emas RCTI, tidak seperti Rosamund Kwan atau Anita Mui atau Maggie Cheung yang lebih familiar bagi penonton TV, tapi toh nama dan wajahnya dan film-film yang dibintanginya mendominasi iklan-iklan bioskop nyaris tiap hari. Film-filmnya mungkin tak akan dibawa oleh juru putar layar tancap atau tukang putar kaset video yang disewa di saat hajatan, tapi film-film Indonesia yang dianggap sejenis, dari bintang seperti Lela Anggraini atau Kiki Fatmala atau Sally Marcelina, selalu tersedia, dan itu cukup mengobati mata-mata lapar pemirsa.
Bukan kebetulan kemunculan Peng Tan di bioskop-bioskop Indonesia berbarengan dengan wabah esek-esek yang juga melanda film lokal kita, khususnya memasuki sepertiga kedua dekade ‘90an. Saya tak banyak membaca soal sinema Hong Kong, tapi mudah dimengerti bahwa kemunculan film-film Peng Tan tahun-tahun itu tampaknya menjadi penanda sebuah krisis yang terjadi di industri tersebut. Secara internal, konon akibat overload produksi dan jebakan tema dan cerita yang repetitif, setelah sinema Hong Kong mengalami booming di akhir ‘80an berkat film-film aksi gangster dan kung fu kolosal mereka. Secara eksternal, ketidakpastian politik menjelang Penyerahan Kembali negara kota itu oleh Inggris kepada Cina pada 1997 juga berpengaruh. Dan jangan lupakan juga ancaman krisis moneter yang telah mengendap-endap di sebagian besar Asia, yang nantinya meledak pada 1997. Beberapa faktor itu coba kita pindahkan ke Indonesia, lalu kita tambahkan beberapa kerumitan tentang bisnis jaringan bioskop, persoalan distribusi, dan booming (film) televisi pada awal ‘90an (yang jadi cikal-bakal industri sinetron), maka kita akan bisa menemukan persamaannya. Dan bersamaan dengan menghilangnya Festival Film Indonesia setelah 1992 (sebelum kembali lagi pada 1999), industri didominasi nama-nama seperti Sally Marcelina, Kiki Fatmala, dan Inneke Koesherawaty, dengan film-film semacam Gairah Malam, Gairah yang Nakal, Ranjang yang Ternoda, atau seri Gadis Metropolis, sebagai penampil utama film Indonesia saat itu.
Saya ingat, pada satu hari saat SMP, kemungkinan sekitar 1993, di warung pangkalan ojek di salah satu pertigaan jalur Pantura Deandels, tempat anak-anak dari berbagai sekolah di sekitar situ biasa berkumpul menunggu tumpangan untuk pulang, obrolan sedang dikuasai oleh iklan film Yang Muda Yang Bercinta, yang akhirnya bisa tayang setelah berpuluh-puluh tahun dilarang oleh Orde Baru, dan konon sedang diputar di bioskop-bioskop di Tuban, kota terdekat dari tempat itu. Iklan itu begitu menonjol di antara iklan film lain, dan lebih menonjol lagi adalah klaim-klaimnya (disebut “klaim-klaim” karena tidak cuma satu, melainkan berderet-deret). Saya lupa persisnya, tapi kurang-lebih semacam “Yang Dulu Dilarang, Kini Telah Beredar!”, dan “Film Paling Panas di Zamannya”. Bahwa film ini disutradarai oleh maestro Sjumandjaya, naskahnya ditulis oleh maestro Umar Kayam, dan dibintangi oleh maestro Rendra, dan ia dilarang beredar semata karena pertimbangan politik, tentu saja tidak disebut-sebut. Dan tebak posternya: sepasang muda-mudi yang sedang bercumbu dengan panasnya.
Ingatan saya ini dibenarkan oleh catatan dalam Katalog Film Indonesia-nya JB Kristanto. Film yang diproduksi pada 1977 ini dilarang karena “dinilai ada unsur propaganda, agitasi dan menghasut masyarakat, khususnya generasi muda”. Namun, ingatan ini menjadi ironis, ketika—merujuk kepada buku yang sama—pada waktu bersamaan film-film yang bisa dianggap paling bermutu di masa itu, seperti Surat untuk Bidadari (Garin Nugroho, 1992] dan Badut-Badut Kota (Ucik Supra, 1993), justru tidak berhasil tayang di bioskop. Alasannya hampir pasti karena dianggap tak akan bisa mendatangkan penonton.
Mengingat Peng Tan, untuk saya pribadi, tampaknya adalah juga mengingat tentang satu-masa-satu-ketika film Indonesia sedang begitu “bergairah” untuk membunuh dirinya sendiri. Ini juga mengingatkan kepada masa-masa ketika, dengan mata awal akil balig yang lapar, saya menonton film penuh adegan seksual dan kekerasan, lewat film-film video yang diputar massal di tempat-tempat hajatan, yang di satu sisi menjadi pemuas dahaga seorang bocah desa penyuka sinema namun di sisi lain juga traumatis, terutama karena, tumbuh-besar di desa santri, saya merasa melakukan hal yang lazimnya dilarang.
***
Peng Tan, bagaimana pun, adalah bacaan. Ia, untuk saya, adalah baliho bioskop yang diperkecil dalam warna hitam-putih, dan hanya dicetak di halaman koran. Ya, Anda tak salah baca, saya memang tak pernah menontonnya—atau, lebih tepatnya, merasa tak pernah menontonnya. Di bioskop jelas tidak, karena, seperti pernah saya tulis (lihat “Ketika ke Bioskop adalah Suatu Dosa”, dalam Kepikiran Dangdut, 2023), saya tidak pernah masuk bioskop sampai menjadi mahasiswa di Jogja, dan setelah saya bisa nonton bioskop film-film Peng Tan sudah tak ada. Di televisi bisa saja saya menontonnya dengan tanpa sengaja (mengingat Peng Tan juga bermain di film-film arus utama Hong Kong, yang tak mustahil pernah diputar di televisi kita), tapi saya tak mengingat pernah menemukan namanya di kredit film di layar televisi sebagaimana saya menemukan nama Rosamund Kwan, Anita Mui, atau Francoise Yip, atau yang sedikit lebih belakangan semacam Shu Qi.
Menonton film, sebagaimana membaca buku dan menikmati sepakbola, untuk saya adalah hasrat yang seringkali harus dimampatkan. Lebih-lebih untuk menonton Peng Tan. Semua serba terasa jauh (secara geografis), terasa mahal (secara ekonomi), dan terutama terasa terlarang (secara sosial-keagamaan); pokoknya, secara keseluruhan, terasa sulit.
Saya sudah banyak mengoceh soal betapa melelahkannya segala upaya untuk bisa menonton film (lihat Aku dan Film India Melawan Dunia, 2017), dan mungkin akan sedikit mengulangnya di sini. Sebenarnya, bioskop terdekat tidaklah sangat jauh. Tuban, kota kabupaten yang berjarak kurang-lebih 30 menit dari desa kami, memiliki setidaknya tiga gedung bioskop, hingga tiba kehancurannya pada pentengahan ‘90an. Namun, 30 menit itu adalah jarak dengan sepeda motor atau mobil hari ini; 30 tahun lalu, jarak itu—rasa-rasanya—bisa 10 kali lipat jauhnya. Baiklah, angkutan antarkota saat itu sangat ramai, dan menurut pendapat saya tak pernah terlalu mahal bahkan hingga hari ini, dan saat itu aktif selama nyaris 24 jam, tapi dari mana saya dapat uang jajan untuk bayar ongkos angkutan sekaligus bayar untuk tiket bioskop, sementara untuk balik dari sekolah saja kami biasa menunggu truk es batu lewat agar uang seratus perak bisa kami hemat untuk bisa dipakai berangkat besoknya lagi. Ibu saya perempuan malang dengan uang belanja yang selalu kurang, tapi bahkan jika ia bermurah hati memberikan sedikit uang jajan lebih untuk membuat anak lelakinya senang, saya tak yakin dia rela uang itu dipakai untuk menonton, misalnya, Penyimpangan Sex atau Gairah Seksual. Saya bisa bayangkan ratapan semacam “Jelek-jelek, bapakmu mantan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Fud!” dari ibu saya.
Juga, terasa tak tepat waktu. Seorang kawan bisa mereguk masa remajanya sepuasnya bersama dengan film-film yang disukainya ketika bioskop di Tuban masih segar-bugar, masih ramai-ramainya, hanya karena ia lebih tua dua tahun dibanding saya. Ketika saya membaca iklan film Yang Muda Yang Bercinta seperti disebut di atas, ia yang sedang menempuh SMA-nya di Tuban telah malang melintang dari bioskop ke bioskop. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang membuat saya mengenal film India, namun teman itulah yang membawa Sanjay Dutt kepada kami dalam dimensi dan level yang berbeda. Ia bercerita menggebu tentang Zamane Se Kya Darna dan Andolan, film-film Dutt yang ditontonnya di bioskop, jauh sebelum film-film itu nongol di televisi. Kegilaan saya di kemudian hari pada film India sangat berhutang kepada kawan tersebut, namun saya merasa cakupan selera saya lebih luas darinya, dan karena itu saya iri dengannya. Sayang, ketika dua tahun kemudian saya masuk SMA, bioskop sudah pada tutup. Sanjay Dutt hanya ada di layar TPI, sementara Peng Tan tinggal bisa ditemukan di iklan koran.
Di atas semuanya, barangkali saya memang remaja baik-baik. Saya sangat menyukai film, tapi saya tidak senang menimbulkan kekacauan. Masalah yang ditimbulkan karena keranjingan sepakbola sudah sangat merepotkan, saya pikir saya tak mau menjadikannya lebih runyam dengan keranjingan film juga.
***
Jadi, ya, saya baru memulainya dengan sangat telat, ketika saya kuliah di Jogja. Dan, sebenarnya, saya hanya menemukan sisa-sisa puingnya saja. Nyaris dalam arti sebenarnya.
Lima tahun pada pertengahan ‘90an itu adalah masa yang sangat krusial untuk banyak sekali hal. Ia mencakup Pemilu ‘97, pemilu terakhir era Orde Baru, disusul Krisis Moneter, dipuncaki oleh Reformasi Mei ’98, kemudian ditutup dengan pengangkatan Gus Dur sebagai Presiden RI pada ‘99. Tahun-tahun genting itu tak pernah semata tentang politik-ekonomi saja. Selepas Reformasi, TV-TV swasta dan media cetak secara umum seperti bocah-bocah bandel yang menguasai kelas setelah mendengar guru yang mereka benci tidak masuk: mereka nyaris semau-maunya. MTV menjadi raja, dan musik Indonesia mengalami masa-masa hebatnya (dengan kemunculan Padi, Sheila On 7, Dewa formasi baru, dan Peterpan). Sementara film Indonesia mati total, industri film India justru sedang mengalami era keemasannya dan kemudian mengirim impor terbaiknya (atau terburuknya?) bernama Shah Rukh Khan dan Kuch Kuch Hota Hai-nya ke Indonesia. TV-TV keranjingan olehnya, tapi yang paling menggila adalah lapak-lapak CD bajakannya.
Pada tahun kedua saya kuliah, dua bioskop paling besar di Jogja terbakar, dengan memakan korban sebagian penontonnya. Baik untuk bioskop maupun penontonnya, itu adalah cara yang sangat buruk untuk mati. Maka, dari tersisa sebagian, bioskop di Jogja hanya tinggal satu-dua, dan itu termasuk yang paling busuk film-filmnya. Dan seperti semua konsentrasi kerumunan di mana pun di Indonesia saat itu, Kampus Bulaksumur pun dikepung oleh lapak-lapak penjualan dan persewaan VCD. Tak terhindarkan, film-film pertama yang saya tonton di Jogja adalah film-film dari kepingan. Dari mulut TV dan pemutar video, saya rupanya masuk ke mulut CD player komputer.
Meski ketertarikan saya terhadap film tak pernah kendur, bahkan ketika saya mulai memiliki ketertarikan baru, yaitu menulis, bioskop bukan lagi yang terlalu saya pikirkan. Apalagi, saat itu, saya tinggal di masjid. Saya tahu, saya tak terlalu becus mengurus masjid, lebih-lebih mengurus umat, tapi setidaknya tidak ingin bertindak bodoh. Tapi, toh, tindakan bodoh itu terjadi juga.
Konon, perbuatan buruk terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Niat untuk ke bioskop tak pernah hilang sejak masa akil balig saya, tapi saya orang yang selalu jago menegosiasikan niat dan tindakan, karena bawaan overthinking saya. Tapi kesempatan itu terlalu di depan mata, dan saya tak bisa terus menerus mengabaikannya. Itu karena empat bioskop yang masih tersisa di Jogja hanya lima menit jalan kaki dari tempat saya tinggal.
Saya mencoba mengelabui hasrat menonton saya dengan membaca. Di Shopping Center, pasar buku yang juga tak jauh dari tempat saya tinggal, bertumpuk Majalah Film bekas. Saya mensubtitusi dorongan untuk ke bioskop dengan nongkrong berlama-lama di lapak majalah bekas itu. Yang jadi problem, semakin kerap saya membelokkan hasrat menonton dengan membaca, semakin keras dorongan untuk menonton, karena memang untuk itulah Majalah Film dibuat. Problem yang lebih besar, persis di belakang Shopping, berdiri dua bioskop.
Ketika akhirnya dorongan itu tak bisa saya atasi, saya masih menegosiasikannya dengan menonton film yang kurang berisiko. Saat itu baliho film Peng Tan masih terpampang di bioskop Permata, bioskop kelas bawah paling legendaris di Jogja, yang juga tak jauh letaknya. Namun saya memilih menonton film India yang sedang tayang, Ghair (1998). Ghair dibintangi Ajay Devgan, Raveena Tandon, dan Amrish Puri, nama-nama yang sangat saya kenal, tapi ia jelas bukan film yang saya idamkan.
Ketika tekad saya sudah bulat untuk menonton film Peng Tan, balihonya ternyata sudah turun. Yang kemudian naik adalah Raped by an Angel. Saya kenal yang main, Simon Yam. Simon Yam sering nongol di TV, jadi mungkin saja film ini masih aman—meski di sisi lain, demi melihat posternya, saya juga berharap mendapatkan pengganti film Peng Tan yang sepadan. Barangkali karena film ini sudah sangat lama, dan mungkin sudah diputar di bioskop itu ratusan kali, saya hanya bisa mengingat warnanya yang buram dan suaranya yang mendengung-dengung. Dan terutama dengusan kecewa kebanyakan penonton ketika adegan-adegan yang potensial menimbulkan ketegangan dipotong gunting sensor begitu saja.
Setelah Raped by an Angel, saya tak bisa membendung diri lagi. Saya kemudian nonton film Hong Kong lain, Sexual Arousal, kali ini di Jogja Theater, bioskop yang relatif lebih mahal dibanding Permata dan Senopati yang berada persis di sampingnya. (Saya rasa Sexual Arousal hanya dikenal di Indonesia, sebagaimana beberapa film Peng Tan yang juga memakai judul yang berbeda untuk peredarannya di Indonesia; ketika saya mengetiknya, judul yang paling banyak keluar adalah Hidden Desire [1991], salah satu film Hong Kong Cat III paling dikenal, yang dibintangi Veronica Yip.) Dan setelah di bioskop yang sama saya lanjut dengan nonton Tales of Kama Sutra: Perfumed Garden (2000), film produksi Amerika yang disutradarai orang India, yang tampaknya ingin membonceng kesuksesan Kama Sutra-nya Mira Nair, saya merasa sudah terlalu kotor untuk kembali ke masjid. Saya pun pamit.
Sejak itu saya nyaris sepenuhnya tinggal di Kampus, sampai lulus. Di sanalah, dengan akses yang mudah, dan dengan kebebasan yang nyaris tak terbatas, dan rasa bersalah yang menjauh, saya dengan tekun menyisir seri Red Soe Diaries-nya David Duchovny, seri Emmanuelle-nya Silvia Kristel, dan meski kikuk ketika nonton Caligula saya menyukai film-film voyeur Tinto Brass yang lain.
Sementara film-film Peng Tan belum juga saya temukan.
***
Baiklah, Peng Tan atau Pheng Tan ternyata memang Diana Pang. Dalam beberapa kesempatan, ia kadang juga disebut sebagai Pang Dan. Jadi, koreksi Prima benar. Yang salah, Prima mengganti nama yang dengan terang-jelas saya ingat, yaitu Peng Tan, menjadi Diana Pang yang sama sekali asing. Jadi, meskipun Peng Tan adalah Diana Pang, dan nama yang terakhir inilah yang kemudian muncul lemanya di Wikipedia, ia tak bisa mengkoreksi Peng Tan dalam tulisan itu. Peng Tan harusnya tetap ditulis Peng Tan. (Karena itu, di sepanjang tulisan ini, Peng Tan tetap saya sebut sebagai Peng Tan, karena memang demikianlah saya mengingatnya.)
Peng Tan identik dengan film-film esek-esek Hong Kong, biasanya disebut sebagai film Category III, atau yang secara lebih santai ditulis sebagai Cat III (yang setara dengan rating “R” di Hollywood atau 17+ di Indonesia), sebuah kategori film yang didominasi tema-tema eksploitasi seks dan kekerasan (khususnya terhadap perempuan)—meski, di kategori ini juga, masuk beberapa film arus utama dari sutradara-sutradara besar Hong Kong seperti John Woo, Ringo Lam, Tsui Hark, bahkan Wong Kar-Wai. Jadi, ingatan saya memang benar. Yang meleset, Peng Tan jauh dari sosok penting untuk film kategori tersebut. Veronica Yip, aktris yang kadang ditemukan di film-film mandarin yang tayang di TV, justru jauh lebih siginifikan namanya, selain tentu Simon Yam, salah satu nama paling populer dari khazanah film gangster Hong Kong masa itu di Indonesia.
Peng Tan baru muncul ke permukaan pada 1995, ketika perfilman Hong Kong sudah lewat masa emasnya. Ada beberapa film yang dibintanginya, dan tidak semuanya esek-esek. Meski demikian, namanya melejit lewat Evil Instinct (1996), yang beredar di Indonesia sebagai Animal Instinct. Film inilah saya kira yang paling dikenal di Indonesia berasosiasi dengan Peng Tan, yang membuat generasi saya mengingat namanya dan mengasosiasikannya dengan masa-masa sekaratnya bioskop. Selain Evil Instinct, Peng Tan juga membintangi Hong Kong Show Girls (1996), The Six Devil Woman (1996), dan Erotic Ghost Story: Perfect Match (1997).
Ingatan saya yang benar-benar meleset adalah mengasosiasikan Peng Tan dengan film Erotic Black Magic. Pertama-tama, Erotic Black Magic ternyata hanya dikenal di Indonesia, karena film ini secara global sebenarnya berjudul The Eternal Evil of Asia (1995). Dan ia dibintangi bukan oleh Peng Tan, melainkan olen Ellen Chan, nama penting lain dalam film-film Cat III, dan Elvis Tsui, bapak-bapak botak berkumis yang biasa jadi penjahat atau spesialis dukun di nyaris semua film esek-esek Hong Kong. Lalu kenapa saya (dan tampaknya banyak orang yang melewati masa remajanya di pertengahan ‘90an) membaurkan Peng Tan dan film tersebut, barangkali karena film ini dan nama Peng Tan sering bersanding berdekatan dalam satu kolom iklan bioskop di koran.
Yang saya sama sekali tidak tahu, saya menemukan nama Peng Tan di sebuah film Indonesia berjudul Kekuasaan Seksual (1997). Meski diproduksi oleh PH Indonesia, disutradarai orang Indonesia, dan dibintangi beberapa bintang Indonesia, film ini lebih tampak sebagai film Hongkong yang dibuat untuk pasar Indonesia. Dibintangi oleh Reynaldi, Francoise Yip, dan Peng Tan (yang dieja sebagai Pheng Tan). Jadi, ya, Peng Tan memang benar-benar punya keterkaitan dengan film Indonesia.
Karir Peng Tan tampaknya tidak panjang. Wikipedia maupun IMDb mencatat, masa-masa produktifnya hanya sampai tahun 1999, dengan puncaknya terjadi pada 1996. Hanya ada sangat sedikit filmnya yang berangka di atas tahun 2000, itu pun sebagiannya terhitung sebagai film televisi. Ini tampaknya secara umum dialami oleh para aktor Hong Kong, khususnya yang perempuan, mengingat perfilman ini mengalami kelesuan secara drastis setelah pergantian milenium. Konon, ia kini masuk dunia politik dan telah menjadi seorang senator.
Dan sampai di sini, yang bisa saya tulis adalah hasil dari membaca atau mengingat dari apa yang pernah saya baca. Saya tidak pernah menonton film-film Peng Tan, setidaknya demikian yang bisa saya ingat, hingga tulisan ini dikerjakan. Saya mencoba melacak apakah saya bisa menemukan Evil Instinct di internet—seperti dulu saya sempat menyimpan unduhan salah satu dari seri Sex and Zen, satu bagian seri A Chinese Torture Chamber Story, dan Fruit is Swelling, dan mungkin beberapa film Hong Kong lain dalam kategori yang mirip. Saya ternyata hanya menemukan beberapa potongan pendeknya saja.
The Imp (1996) adalah satu-satunya film yang nongol ketika saya melakukan pencarian nama Peng Tan atau Diana Pang di Youtube. Cerita tentang kerasukan yang jauh dari unik, yang mengingatkan saya pada film-film hantu Indonesia berbajet rendah, membuat saya hanya merasa perlu menontonnya tak lebih dari 10 menit. Hal paling positif dari The Imp, saya rasa akhirnya saya bisa melihat wajah Peng Tan lebih jelas, bergerak dan hidup, tidak hanya di iklan bioskop di koran atau baliho di depan Bioskop Permata.
Kekuasaan Seksual bersama nama Peng Tan di kreditnya justru saya temukan dengan sangat kebetulan, setelah saya menyisir nama-nama “bintang-bintang panas” film Indonesia pada film-film yang rilis antara 1993 hingga 1997 di Katalog Film Indonesia-nya JB Kristanto. Rupanya, saya dengan mudah menemukan filmnya. Kekuasaan Seksual, sebuah triller konspirasi, dengan sekuen aksi yang lumayan dominan, tak ada seksual-seksualnya sama sekali ini, tak seperti judulnya. Juga tak ditemukan apa yang disebut sebagai “kekuasaan”—kecuali jika yang dimaksud adalah gambar foto Presiden Suharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno pada sebuah adegan jumpa pers di ujung film. Tapi, bagaimanapun, ini film Yip. Peng Tan hanya nyelip saja, sekadar membuka baju, mencopot rok dan kaus kaki, dan menunjukkan kemampuan menari baletnya dengan hanya berkutang tanpa alasan yang jelas—dan kemudian mati, juga dengan tanpa alasan yang jelas. Yang lebih menarik dari film yang keseluruhannya disulihsuarakan dalam bahasa Indonesia ini, saya menemukan dua suara yang sangat akrab di telinga, yaitu suara Ivone Rose dan Ferry Fadly.
(Jauh lebih mudah ditemukan adalah Erotic Black Magic, tentu dalam judul yang lebih resmi, The Eternal Evil of Asia. Bercerita tentang sepasang suami istri yang diburu teluh, ia menggabungkan triller horor dan erotisisme ala film B, dan karena itu betul-betul mengingatkan saya dengan film-film kita sendiri di era yang sama. Saya lebih banyak tertawa-tawa dibanding takut, apalagi bergairah, terutama karena “Asia” yang dimaksud di judul film ternyata adalah Asia Tenggara. Meskipun spesifik disebut teluh itu berasal dari Thailand, saya agak yakin bahwa pembuat film melirik juga ke Indonesia—mencuri rambut, terus memakai boneka santet yang ditusuki jarum, tampaknya lebih dekat dengan khazanah magis Indonesia dibandingkan dengan tempat lain mana pun di Asia Tenggara.)
Kalau saya agak berusaha lebih keras, mungkin saya bisa temukan film Peng Tan yang lain lagi. Tapi, dengan satu-dua pertimbangan, saya akhirnya memutuskan untuk tak melanjutkan pencarian. Saya rasa, saya menyayangi bayangan saya tentang Peng Tan yang sepenuhnya konseptual, dibentuk di masa yang masih murni sekaligus masih mentah, semata berdasar ingatan, plus informasi yang serba terbatas, yang belum diuji kenyataan; konsep yang saya asosiasikan dengan masa remaja saya yang jauh dari hiburan, yang menggebu oleh begitu banyak keinginan namun pada saat yang sama diganduli oleh berbagai jenis halangan. Peng Tan juga adalah sebuah representasi satu masa yang, ketika mengingatnya, saya juga mengingat nama-nama lain, nama-nama aktor lokal kita, sebagian besar perempuan, dan kesemuanya biasanya diasosiasikan dengan film esek-esek, satu kondisi yang menunjukkan betapa merananya film Indonesia saat itu. Peng Tan, dan poster film-filmnya, adalah juga poster bioskop kelas bawah yang paling terakhir diturunkan: di satu sisi menunjukkan keputusasaan (karena hanya itu yang mereka punya) namun di sisi lain juga menunjukkan resiliensi (karena ia begitu lama ada di sana).
Karena ia tak pernah benar-benar ditonton, Peng Tan, tak seperti Barry Prima dan/atau Rhoma Irama, tak memiliki jejak mendalam dalam masa tumbuh saya dan membentuk saya hari ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai pengarang. Meskipun menjadi semacam gejala ganjil bagi industri filmnya masing-masing, Peng Tan tidak seperti Nana Patekar dari film India, yang kelak mengilhami saya untuk menjadi semacam “bajingan menjengkelkan yang selalu memiliki alasan untuk menjadi bajingan”. Evil Instinct, lagi-lagi karena tidak pernah menontonnya, tak pernah bisa seperti Jaka Sembung atau Pertarungan Iblis Merah yang ditonton berulang-ulang, yang beberapa adegannya, baik yang spektakular atau maupun yang mengerikan, tak pernah bisa keluar dari ingatan saya.
Tapi saya rasa Peng Tan punya tempatnya sendiri, punya fungsinya sendiri, dan karena itu ia mesti diingat dan perlu dicatat.
***
Di masa kuliah dulu, pada awal 2000an, ketika akses utama atas film adalah persewaan VCD, saya dan teman-teman memakai istilah payung “film festival” untuk mewadahi semua jenis film yang mengandung erotisisme, entah yang memang benar-benar film festival (biasanya dengan tanda pohon palem di sampulnya) atau yang semata erotis saja, atau bahkan yang vulgar. Pertama-tama, tentu saja untuk menjadi semacam kode penyamaran, terutama di depan diri kami sendiri, agar kami yang sehari-harinya berdiskusi hal-hal berat, membaca buku-buku hebat, menulis yang dakik-dakik, tidak merasa rendah menonton film rendahan. Namun, di sisi lain, istilah ini juga menjadi semacam cara kami men-downgrade rasa snob kami yang sering mencoba terlalu keras untuk menjadi seperti para sinefil pada umumnya; “yang membedakan film berbudaya tinggi dan film dari budaya rendah hanyalah seberapa banyak gambar daun palem di sampulnya, isinya toh sama-sama orang senggama,” kira-kira begitu cara kami melihatnya. Dan, karena itu, cakupan “film festival” kami menjadi sangat luas, beragam, dan tentu saja seringkali sangat acak, kalau bukannya ngawur. Mulai dari seri Emmanuelle dan Red Shoe Diaries yang telah menjadi klasik di rental-rental film (yang dianggap) serius ke seri Jin Pin Mei, komedi jorok dari sisa-sisa dekadensi sinema Cat III Hong Kong yang biasanya didapat di lapak-lapak CD haram; dari nama-nama Italia yang joroknya artistik seperti Bertolucci, Antonioni, atau Pasolini, atau Brass, hingga yang joroknya sungguhan ala Joe D’Amato atau Antonio Adamo; dari erotisisme Eropa yang bikin ngilu (Story of O, Salo dan film-film Pasolini lainnya, Sex and Lucia, Romance, Fat Girl dan film-film Breillat lainnya, Bais-Moi, Irreversible dan film-film Noe lainnya, film-film Von Trier, dll.) hingga erotisisme Jepang yang pilu (The Pornographer, Empire of Passion, dst.).
Persentuhan saya dengan film-film demikian, yang kini mungkin terlihat sebagai kekonyolan masa muda, seringkali saya anggap sebagai sejenis “akibat salah pergaulan”; pada satu masa, saya beraktivitas dan menghabiskan banyak sekali waktu di komunitas yang memberi tekanan tinggi untuk menjadi merasa keren oleh bacaan tertentu atau menjadi merasa hebat karena menonton film tertentu, dan perjumpaan-perjumpaan semacam ini jadi tak terhindarkan atau bahkan sepenuhnya kasual. Tapi, di sisi lain, saya yakin saya tak segampangan itu—dari kecil saya suka mencibir anak-anak yang mudah terbawa arus pergaulan, mudah dipengaruhi oleh teman-teman atau lingkungannya; saya tak pernah menyentuh alkohol atau yang lebih buruk dari itu (sesuatu yang juga terkondisikan di pergaulan saya), bahkan sama sekali tak tertarik dengan sekadar rokok, jadi apa istimewanya buku atau film dari orang lain?
Saya tahu ada sesuatu dalam diri saya sendiri yang mendorong saya ke sana, sebuah dorongan yang sama dengan saat saya, pada usia 9 atau 10, membuka laci seorang sepupu yang berisi setumpuk novel Freddy S., membacai beberapa halaman awalnya, duduk tepekur, dan tiba-tiba saja bacaan seukuran saku 100-120an halaman itu sudah tandas. Menunggui dengan teguh dan penuh tekad—sembari melawan kantuk dan kedinginan—film-film busuk penuh kekerasaan dan adegan pemerkosaan macam Golok Setan, Bergola Ijo, Pertarungan Iblis Merah, Ratu Buaya Putih, Malaikat Bayangan, Mandala dari Sungai Ular, Pembalasan Si Mata Malaikat, Tiga Cewek Jagoan, Pembalasan Ratu Laut Selatan, Santet 1 & 2, Perawan Lembah Wilis, Misteri Janda Kembang, dan entah apalagi, di awal usia belasan, tidak pernah saya lakukan karena ajakan orang lain; saya bahkan selalu bersiap diomeli ibu saya seharian, atau tak diberikan uang saku untuk sekolah, demi bisa melakukan itu. Dorongan yang sama juga yang membuat iklan bioskop Adikku Kekasihku, misalnya, atau Yang Muda Yang Bercinta, atau lebih belakangan Erotic Black Magic, menjadi jauh lebih melekat dalam ingatan dibanding ratusan iklan bioskop lain yang pernah saya temukan di koran. Dan, coba lihat, apa yang saya lakukan ketika bahkan saat menjadi merbot masjid.
Jadi, saya rasa tidak perlu penjelasan lebih mengapa nama Peng Tan menjadi menonjol di antara nama-nama lainnya. Dan kegagalan menontonnya menciptakan semacam lubang yang mesti disumpal.
Jika (kegagalan menonton) Peng Tan ada hubungannya dengan (keinginan menonton) Raped by an Angel dan Sexual Arousal, Jin Pin Mae dan A Chinese Torture Chamber Story, karena film-film itu berasal dari industri yang sama, maka saya juga bisa membayangkan ia terhubung dengan keinginan untuk menonton seri Emmanuelle atau Red Shoe Diaries atau Caligula meskipun film-film yang disebut lebih belakangan itu dibuat di belahan ujung dunia yang lain. Jika saya gagal menonton satu produk film esek-esek Hong Kong pra-Penyerahan Kembali, mudah dimengerti mengapa saya mensubtitusinya dengan beberapa film erotik Jepang berseting pasca-Perang produksi Nikkatsu, misalnya. Dan tanpa bermaksud merendahkan nama-nama hebat, para dewa di festival-festival, yang karya-karyanya bertatahkan daun palem dan bertaburkan bintang-bintang, untuk saya, ketika saya menonton film-film Noe atau Pasolini atau Breillat atau Von Trier, saya bisa melihat bayangkan Peng Tan, dan poster filmnya yang seronok, meskipun samar-samar dan jauh di belakang.
Pada akhirnya, dengan sedikit menyederhanakan, saya bisa katakan, pengalaman saya dengan “film festival”, tentu dalam pengertian seperti yang telah saya jelaskan, adalah pengalaman berburu (ingatan atas) Peng Tan.
***
Ketika saya sedang menulis ini, dan mulai menurunkan buku-buku tentang film dari rak untuk sekadar baca-baca, saya kira saya juga menemukan Peng Tan di sana.
Lima-enam tahun belakangan, tapi terutama sejak dan sepanjang pandemi, saya tampaknya lebih banyak mengumpulkan bacaan tentang film dibanding menontonnya. Sebagian alasannya karena ketidaksanggupan saya untuk mengikuti derasnya banjir dan limpah-ruah film seiring dengan perkembangan teknologi menonton film yang begitu pesat dan cepat pada dekade terakhir ini; saya merasa kewalahan untuk menampung dan menanggungnya. Buku-buku membuat film terasa lebih awet, bisa dinikmati pelan-pelan, dan bisa kapan-kapan, kita tidak terburu-buru dibuatnya. Dalam satu dan lain cara, untuk saya, menikmati film lewat buku-buku, adalah menolak dorongan untuk selalu update dengan cara lebih elegan.
Dari 3000an buku yang ada di rumah, sekitar 500annya adalah buku-buku tentang film. Tidak cukup banyak untuk seorang yang terlalu banyak omong soal film macam saya, tapi itu sepertinya cukup untuk membuat saya sibuk dan, dalam konteks ini, cukup untuk mencegah saya tidak terlalu banyak menonton film.
Buku tentang film India adalah yang paling banyak. Tentu karena ada masa ketika saya sangat intens untuk mengumpulkannya, karena saya mesti menulis. Buku-buku tentang Hollywood ada di urutan kedua, meski sejujurnya saya sudah lama tak lagi tertarik dengan mereka. Biasanya buku-buku itu terkumpul karena ia lebih mudah ditemukan. Jumlah yang paling sedikit adalah buku-buku tentang film Indonesia, meski ini adalah jenis buku film yang saya kumpulkan paling awal. (Saya sebenarnya ingin mengumpulkan buku tentang film Indonesia sebanyak mungkin, tapi apa yang dikumpulkan kalau bukunya tidak ada. Maka, untuk sedikit mengecilkan selisih, khususnya dengan koleksi buku berkait sinema India, saya biasanya mencampur buku-buku tentang kajian budaya populer Indonesia ke buku-buku film.) Belakangan, saya menambahkan beberapa buku tentang sinema Hong Kong, tapi sepertinya ia tidak akan bertambah lebih banyak dalam waktu dekat, dan sepertinya sulit untuk menjadi kelompok keempat.
Sebagai orang yang menyukai film sebagai penonton, bukan sebagai akademisi maupun praktisi, secara alami saya menghindari buku-buku teori. Meski demikian, tak terhindarkan juga, beberapa buku yang mestinya menjadi koleksi wajib perpustakaan di jurusan film ada di situ. Misalnya, kumpulan esai Fellini, esai-esai Ray, studi komprehensif tentang karya-karya Hitchcock, tulisan-tulisan tentang film oleh Ritwik Ghatak dan Guru Dutt, hingga diktat kuliah D.A. Peransi. Buku-buku kajian film produk orang kampus, bagaimana pun, adalah yang paling banyak tersedia, dan karena itu juga yang paling mudah dikumpulkan. Buku semacam ini biasanya akan paling belakang terbaca atau bisa sama sekali tidak terbaca, tergantung apakah saya membutuhkannya untuk menulis atau tidak. Buku film yang paling mudah dibaca, seringkali sebagai hiburan, adalah memoar atau biografi atau otobiografi, meskipun buku-buku sejarah film yang ditulis dalam cara populer juga sangat menyenangkan. Tapi di antara yang paling menyenangkan adalah buku-buku gossip atau buku tentang film dengan kadar gossip yang tinggi. Ya, saya menyukai film karena ceritanya, namun dalam banyak kesempatan saya kadang jauh lebih menyukai cerita tentang orang-orang film.
The Kapoors karya Madhu Jain adalah salah satu biografi paling menyenangkan yang pernah saya baca. Ia adalah kisah tentang dinasti film paling penting sekaligus paling berpengaruh di India, dan karena itu ia juga sebuah buku sejarah sinema India yang komprehensif. Namun yang jauh lebih asyik, Jain, yang tampaknya punya kedekatan yang spesial dengan Keluarga Kapoor, memenuhi bukunya yang tebal dan meliputi masa yang panjang dengan berbagai rumor dan desas-desus. Hal yang sama juga saya temukan dalam Bollywood: A History-nya Mihir Bose. Ditulis dengan keterampilan menulis yang sangat menyenangkan, khas seorang wartawan olahraga Inggris, Bose tak segan mengutip sumber-sumber paling sumir sekalipun untuk membuat buku sejarahnya penuh dengan drama, aib, dan romansa—hal-hal yang sangat mewakili Bollywood. Dalam cara jurnalistik juga, Maximum City-nya Suketu Mehta memenuhi selera ingin tahu saya. Buku biografi kota Bombay ini menceritakan Bollywood tidak dari orang-orang hebat yang ada di dalam industri, melainkan dari orang-orang malang yang ingin memasukinya.
Tapi tampaknya tak ada yang seekstrem buku Scotty Bowers, Full Service. Bowers adalah veteran Perang Dunia II yang kemudian bekerja sebagai petugas pom bensin di wilayah Hollywood Boullevard, sebelum kemudian jadi germo untuk orang-orang paling penting juga paling terkenal dalam sejarah film, dan menjadi saksi mata hal-hal paling gelap, paling ajaib, dan paling memalukan di sana. Buku ini sepenuhnya tentang aib-aib Hollywood. Tak akan mengherankan jika buku ini, cepat atau lambat, akan diadaptasi menjadi film. Dan untuk orang yang menciptakan tokoh pembual seperti Warto Kemplung, membacanya adalah petualangan yang sangat mengasyikkan.
Lalu di manakah Peng Tan di antara buku-buku itu? Peng Tan ada dan menonjol di rak itu justru karena ia tidak hadir di situ.
Peng Tan saya temukan ketika saya membaca kemegahan film-film John Woo dan Ringo Lam dan Tsui Hark, dan betapa ikoniknya Chow Yun-Fat di masa itu. Saya menemukan bahwa saya melupakan Peng Tan ketika saya menonton ulang (dan menemukan ketakjuban baru pada) seri A Better Tomorrow, The Killer, City of Fire, Bullet in The Head, dan beberapa film sejenisnya, film tembak-tembakan yang dulu ikut menemani masa remaja kami.
Dan Peng Tan tidak sendirian. Di situ ia juga ditemani para bintang “panas” Indonesia yang dulu saya tunggui film-filmnya. Saya bisa dengan jelas melihat Suzanna justru ketika namanya sama sekali tak disebut di buku yang memakai anak judul “hantu dari masa lalu”, yang dalam edisi Indonesianya bahkan memakai fotonya sebagai sampul. Suzannna disebut beberapa kali dalam sebuah studi tentang ibu-ibu yang jadi hantu dalam film horror Indonesia, barangkali karena ia pernah “Beranak dalam Kubur”. Tapi, tampaknya tak ada tempat untuk Lela Anggraini, Kiki Fatmala, Sally Marcelina, Malfin Shayna, Inneke Koesherawaty, Devy Ivone, Gitty Srinita, Megi Megawati, Windy Chindyana, Febby Lawrence, Ayu Yohana, Liza Chaniago, Debby Carol, Indah Febrizha, dan mungkin masih banyak lagi, yang meski tak melakoni peran ibu, akrab dengan film-film yang memakai judul “perempuan”, “wanita”, “perawan”, “gadis”, atau “janda”, bahkan tak jarang juga “ratu” atau setidaknya “selir”. Mereka, yang sering dianggap sebagai representasi dari masa paling bobrok dari film Indonesia, tampaknya ditakdirkan untuk dianiaya dan diperkosa di dalam film dan kemudian dilupakan di dunia nyata.
Glagah Lor, 06 Februari 2025
PENULIS

MAHFUD IKHWAN, Seorang Novelis dan Kolumnis kelahiran Lamongan yang gemar bercerita dan menyantap satay Kambing