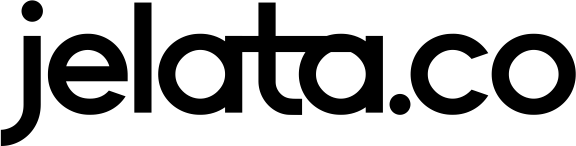Tapi kau jangan pernah menyerah / Pantang tadahkan tangan / Di hati semua sama tinggi /Atas- bawah akan berpindah”.
( Ode Pinggiran Jakarta-The Brandals)
Saya masih ingat cukup persis peristiwa itu. 1990, ba’da dzuhur. Bapak sampai di muka pintu rumah dinas bagi guru yang baru saja beberapa bulan kami tempati di wilayah pantura. Sekujur tubuhnya berpeluh membasahi kemejanya yang tipis hingga singlet dalamnya kelihatan.
Bapak baru saja pulang dari acara hajatan adiknya di Jakarta-kota yang masih tiga perempat abu-abu dalam kosa-geografis saya yang masih berusia 6 tahun. Meski nampak kelelahan, beliau berusaha tersenyum. “Tolong bawa ke belakang ya”pinta beliau ke adik sembari mengulurkan tentengan dari tangan kirinya, sebuah kardus mie instan berbalut tali rafia.
Tak lama kemudian, dari ruang belakang terdengar suara adik-adik kegirangan, saya bersicepat menuju ke sana. Kardus mie instan di atas meja makan ternyata sudah terbuka. Di dalamnya ada sebotol bubuk putih yang kemudian saya tahu disebut creamer, beberapa untai wafer berselaput coklat yang belum pernah saya temukan di warung atau toko yang agak besar di kota kami, dan..eh apakah itu yang ada di area setengah kardus?
Saya menimang-nimangnya, sebuah apel yang dua kali lebih besar dari apel yang pernah saya makan, dan oh..berbeda dengan “apel daerah”, warna merahnya ini utuh merata dengan sticker bertuliskan ibukota Amerika Serikat. Rasanya saat itu seperti melihat militer asing berseragam dengan tanda kepangkatan tersemat di dada. Gagah sekali.
Seperti yang saya tulis di atas, meskipun masih agak asing, tentu saja saya sudah mengenal Jakarta yang disinggung dalam buku pelajaran juga dari buku cerita anak-anak yang dibawakan ibu dari sekolah tempat beliau mengajar. Buku-buku tersebut mungkin untuk alasan pendidikan atau motivasi moral, selalu menggambarkan Jakarta sebagai tempat pertarungan nasib di mana kesuksesan sosial-ekonomi menjadi skor finalnya.
Berbanding terbalik dengan tujuan buku tersebut, sepetak kecil pikiran saya selalu membayangkan Jakarta seperti terminal bus di kota kami; panas berdebu ketika kemarau, banjir, becek dan bau saat musim hujan. Belum lagi para bromocorah serta kawanan pengemis berkeliaran. Saya sungguh tidak ingin mengunjunginya. Sampai apel oleh-oleh dari Jakarta itu hadir di atas meja makan kami.
Kota itu mendadak ranum dalam imajinasi saya. Jakarta terasa menjadi muara semua kebahagiaan dan kemajuan. Makanan dan minuman impor dari negeri-negeri asing, istana tempat pemimpin negara ini berdomisili, gedung-gedung seperti kandang merpati bertingkat menjulang, gadis-gadis cantik dalam TV yang mengenakan pakaian warna-warni dan apa itu dalam iklan majalah keluarga?
Anak-anak sepantaran saya yang nampak bersih, ceria dengan jajanan yang nampak mahal dan tentu saja piranti video game yang jika suatu kali berhasil saya miliki akan membuat Johan, Santo, si Kembar Azis -Aris dan seluruh lingkaran permainan saya di kampung akan memuja saya bagaikan dewa Zeus.
————-
1 Mei 2003. Kaos Rancid bootleg yang lusuh, jeans sempit robek yang dilingkari studded belt berbahan kulit imitasi di pinggang serta sepatu kumal dengan sole super tipis, saya berdiri di atas aspal yang panas. Tepat di hadapan saya melintang pagar kawat berduri dengan se-batalyon polisi.
Bendera-bendera dan kertas tuntutan tinggi teracung, seolah dengan cara begitu, orang-orang dalam gedung bertingkat yang dilindungi para polisi tersebut akan bisa membacanya. Meskipun mustahil.
Sehari sebelumnya kami berangkat dengan beberapa bus berisi mahasiswa yang akan bergabung dengan serikat buruh ibukota untuk merayakan Hari Buruh Internasional sekalian memprotes invasi Amerika Serikat ke Iraq di depan Kedubes Amerika Serikat. Heroik sekali? Mungkin setengahnya. Atau seperempatnya saja. Sisanya kami sedang bosan duduk di meja kuliah dan mencari cara bertamasya dengan murah meriah. Ha!
Di tengah orasi bergantian yang berebut suara dengan suara klakson merepet dan deru knalpot, saya memilih menepi ke sebuah kios rokok. Ini kali kedua saya ke ibukota, setelah kunjungan teramat singkat berbelas tahun lalu. Saya menatap lagi gedung-gedung tinggi, polisi, demonstran dan kawat berduri. Saat itu juga, saya menyadari telah melihat Jakarta dengan perspektif yang baru: Sarang kriminal.
Saya teringat ketika baru saja tiba di kota ini sudah nyaris berkelahi dengan sopir bus kota ugal-ugalan yang membuat bahu saya terserempet dahan pohon yang menjulur dari tepi jalan. Berikutnya, saya menyaksikan marbot sebuah masjid ber-pencak betawi ala jawara, bersiap menghantam tengkuk koleganya lantaran berbaik hati mempersilahkan kami-segerombolan “gembel”untuk menggunakan masjid sebagai tempat istirahat sementara sekaligus sholat.
Sungguhpun begitu, sebenarnya predikat “kriminal” bukan saya alamatkan kepada mereka. Seperti orang tua saya, kerabat atau tetangga di kampung atau para buruh di seberang sana yang sedang berdemontrasi, mereka hanyalah rakyat kelas kromo yang kebut-kebutan dengan nasib buruk di arena sirkuit kapital yang jelas-jelas tidak memihak. Sebutan kriminal adalah sangat layak untuk untuk mereka, yang kita bayar dengan perasan keringat sampai gumpalan daki akan tetapi tidak mempunyai hati nurani.
Mereka yang berperilaku lalim, mereka yang telah melahirkan keputusan-keputusan celaka yang menyebar bagai wabah untuk menjangkiti penyakit keputus-asaan di kalangan rakyat kecil. Mereka yang dengan makna yang sangat ambigu kita sebut sebagai pemberi perintah.
Sekumpulan pelayan yang kita bayar agar memberi perintah kepada majikannya?. Sialnya, setiap kita mengajukan keberatan, mereka malah menyediakan perangkat kekerasan. Seperti permainan yang konyol saja. Dan di sinilah wahananya. Sarangnya.
Apa benar demikian?
———-
Ada pameo “Belanda Masih Jauh” untuk mengilustrasikan sebuah jeda di antara kesibukan. Sekarang ini, betapapun saya ingin mengganti subyek kotanya dengan Jakarta dan berjingkat sepersekian inci dari permasalahan-permasalahan kota tersebut, toh sudah hampir 2 tahun saya berada di sini.
Bermukimdi sebuah kampung kota yang berbagi jalan dengan wilayah pinggiran Jakarta Selatan, jadi meskipun secara administratif masuk ke provinsi Banten akan tetapi secara sosio-kultural -kalau ikut istilah seorang teman, kampung ini “mbetawi” sekali.
Berdomisili di kota ini untuk pertama kali, saya tidak ingin mengalami kisah klise tentang orang udik yang mengalami gegar budaya di Jakarta. Sedari dari kampung saya sudah meyakinkan diri bahwa saya bukanlah tokoh Matias Akankari yang mengenakan koteka di night club dalam cerpennya Gerson Poyk, saya bukanlah pencari alamat yang tersesat karena berhadapan dengan begitu cepatnya perubahan kota Jakarta dalam cerpennya Jujur Prananto.
Apalagi saya sudah mempersiapkan diri dengan hampir menamatkan kumpulan esai Seno Gumira Ajidarma dalam Affair:Obrolan tentang Jakarta. Pendek kata, saya begitu siap menjadi manusia urban. Lagipula saya adalah kloter awal dari generasi yang mengalami lompatan evolusi tekhnologi. Jangankan Jakarta, dari Beijing sampai Islandia seperti dalam genggaman saja.
Kenyataannya tidaklah demikian.
Di sinilah saya pertama kali mengagumi udara putih tipis yang datang dari rimbun pepohonan kala sore hari yang saya kira kabut seusai hujan ternyata asap dari aktivitas membakar sampah -dalam istilah betawi disebut nabun- yang membuat saya terbatuk-batuk dan istri saya terpingkal-pingkal,di sinilah istri saya pertama kali ngomel karena saya pulang membeli nasi uduk polosan karena saya kira yang disebut membeli nasi uduk adalah nasinya doang!.
Di ruas-ruas jalan ini saya hampir tersesat, karena satu ruasnya mempunyai lebih dari 2 cabang sementara aplikasi Google Maps tidak banyak membantu. Di kota ini juga saya tertegun, betapa lambatnya kota ini mengirim kembali para pencari nafkah ke rumahnya sampai jauh malam atau malahan dini hari,seperti yang saya temui di kehidupan keluarga mertua.
Menjadikan saya kerap bertanya pada diri sendiri, apa yang diinginkan perusahaan mereka? Apa yang diinginkan kota ini? Apa mungkin imbalannya layak? Kenapa sebuah kota yang dihidupi hampir 11 juta nyawa manusia mempunyai siklus balon? Menganggap manusia sebagai balon, ditiup-tiup hingga menggelembung selagi dibutuhkan lalu dikempeskan sampai gepeng. Terus saja begitu sampai jutaan hari berikutnya, sampai ia serobek-robeknya, lalu dibuang begitu saja atau dikenang sekadarnya dengan karangan bunga.
Apakah kota ini juga akan bernasib serupa menjelang kepindahan ibukota ke Kalimantan Timur?
Saya tentu saja tidak mempunyai kapabilitas untuk menjawabnya, hanya jadi teringat wawancara sebuah media dengan Wong Kar Wai,salah satu sineas ternama Hongkong. Wong berujar bahwa beberapa filmnya seperti Ashes of Time (1994) adalah tentang tegangan antara memori dan distopia.
Artefak dan peristiwa masa lalu dihadap-hadapkan dengan bayangan ketakutan akan masa depan yang kacau balau. Wong secara lugas menyampaikan bahwa inilah yang dirasakan masyarakat Hongkong menjelang reunifikasi dengan Cina pada tahun 1997 setelah 156 tahun kota bekas koloni itu di bawah kedaulatan Inggris.
Jika memori dan distopia seperti yang dikatakan Wong adalah perasaan, di depan saya saat ini-di sebuah toko waralaba- keduanya sudah mewujud. Sebuah ondel-ondel-yang saya yakin isinya manusia dan bukan kacang hijau tumbuk (oh, maaf, yang itu onde-onde)- berjoget-joget ala kadarnya diiringi lagu Benyamin Sueb yang keluar dari speaker sember.
Boneka rangka bambu dengan topeng menyeramkan itu seturut catatan W.Scott pada tahun 1561 adalah ajimat suku betawi yang digunakan mereka sebagai penjaga kampung dari roh jahat. Mungkin karena hanya mampu melindungi kampung dari roh jahat dan bukan dari perusahaan properti atau investor yang tamak, maka kampung pun lenyap berganti kawasan perumahan elit atau hotel.
Lantas ondel-ondel terpaksa “hijrah” menjadi simbol budaya dari kota ini belaka, artinya ia dicacatkan dari sejarah dan fungsi sosialnya. Cilaka betul, simbol adalah benda mati sementara ondel-ondel berisi manusia yang butuh nasi, maka dengan sangat terpaksa ondel-ondel itu mengamen dengan masih menggendong masa lalu sebagai kebanggaan terakhir penduduk ibukota.
Tidak jauh dari saya duduk menunggu istri berbelanja, sebuah boneka juga sedang beraksi-dia berkepala besar dan mempunyai semacam antena di ubun-ubunnya. Tubuhnya yang tambun nampak dekil berhias debu jalanan dan telapak kakinya bersandal jepit. Dia seliweran di area parkir sembari mengedarkan ember untuk menadah receh seusai beberapa menit joget kecil sambil melambai-lambaikan tangan.
Dia jelas bukan jimat salah satu suku dari bangsa kami. Boneka karakter itu bernama Tinky-Winky dari seri anak-anak Teletubbies produksi BBC, Inggris. Sebuah produk dari budaya populer dekade 2000-an. Alih-alih melihatnya sebagai rivalitas dalam ranah ekonomi saja, saya menganggapnya sebagai perjumpaan masa lalu yang terpinggirkan dengan masa depan yang compang-camping. Dan kita- para penduduk kota ini-akan memilih mengangsurkan recehan kita ke ember siapa.
Saya ingin mengakhiri catatan ini dengan paragraf terakhir di atas. Tetapi, saya kembali jadi teringat apel gara-gara istri membeli apel semalam. Dua buah apel yang jauh lebih besar dari apel yang saya dapatkan dari oleh-oleh bapak semasa kecil.
Rasanya akan jadi lebih dramatis apabila menyandingkan kisah apel saya ini dengan kisah kejatuhan manusia ke dunia karena ibu umat manusia bernama Hawa nekat memakan apel surga seperti yang diceritakan dalam kitab Injil dan Qur’an.
Maksudnya, saya akan menggambarkan “kejatuhan” penduduk Jakarta setelah seseorang.. hmm..nekat memindahkan ibukota negara. Namun saya juga jadi teringat bahwa dua apel tersebut dibeli istri dari seorang bocah kecil yang menawarkan dagangannya dengan berbaju lusuh dan bertelanjang kaki.
Saya menimbang bahwa lebih penting bertanya kepada pembaca tulisan ini : Bagaimapun jadinya kota ini kelak, apakah ada jaminan bahwa adik kecil penjual apel tadi akan dimenangkan haknya?. Itu!
Penulis
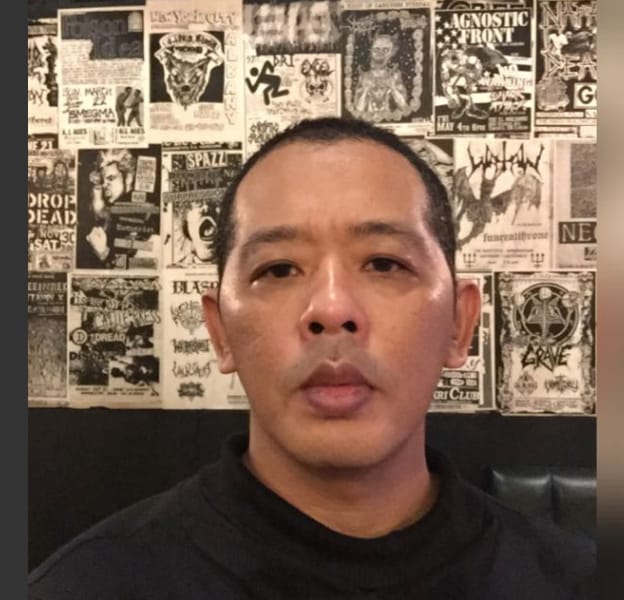
Herda Ananta Yoga Pratama
Beliau seorang penulis dan perupa tinggal di Tangerang Selatan