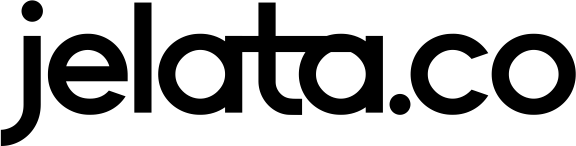BERITA duka itu saya terima tadi malam. Membuat saya terhenyak. Merasa sangat kehilangan. Dia memang tidak ada hubungan darah dengan saya, juga tak ada relasi bisnis apa-apa. Namun, saya mengikuti betul kiprahnya. Dan dia adalah perempuan yang saya sangat hormati, selain ibu saya.
Yang berpulang adalah Lilik Sulistyowati. Namun, kolega dan sahabat-sahabatnya mengenalnya sebagai Mbak Vera. Pada 24 Desember kemarin, perempuan berusia 65 tahun itu menutup mata untuk selamanya.
Izinkan saya bercerita sedikit mengenai perempuan yang begitu saya hormati tersebut. Yang teman-teman tentu tak banyak mengenal nama maupun kiprahnya. Seorang perempuan yang saya anggap sebagai unsung hero.
Perjumpaan saya dengan Mbak Vera terjadi ketika saya masih menjadi jurnalis di lapangan pada 2004. Ketika itu, Mbak Vera sudah mempunyai nama, terutama di Gang Dolly. Betul, lokalisasi yang disebut-sebut sebagai terbesar di Asia Tenggara yang kini sudah tutup itu.
Mbak Vera mempunyai LSM bernama Abdi Asih. Yang bergerak di bidang advokasi perempuan, pengentasan PSK, dan pendampingan orang dengan HIV/AIDS. Sebuah penyakit yang banyak muncul di daerah lampu merah.
Mami Vera, dulu dia banyak disebut, masuk ke Dolly bukan seperti seorang SJW yang bicara hitam-putih. Dia datang, dia mendengarkan, dia membantu, dan dia mengentaskan. Dalam bahasa sekarang, pendekatan “we listen, we don’t judge”-nya membuat dia bisa diterima di kawasan itu. Apalagi, dia juga melakukan aksi bantuan nyata.
Pendekatannya pun personal, sehingga dia bisa ketemu siapa saja di Dolly. Mulai dari muncikari, PSK, petugas kelurahan, hingga banyak pegawai RSUD dr Soetomo, yang menjadi rujukannya ketika ada masalah kesehatan.
Saya langsung merasa klik bertemu dengannya. Dia menjadi aktivis sosial karena panggilan jiwanya. Passion-nya memang di sana. Dia terlihat hidup dan bersemangat ketika bercerita tentang pengalamannya. Mengenai kisah tragis yang jarang menjadi perbincangan di luar sana. ’’Kar,’’ begitu dia biasa memanggil saya, ’’Kalau bukan saya, siapa yang mengurus mereka-mereka ini?’’

Dan memang, segmen orang-orang yang ditolong Mbak Vera ini bukan jenis orang-orang yang “menyenangkan” ketika ditolong. Misalnya, pada satu malam, ada PSK yang meminta bantuannya. Ternyata vaginanya mengalami pendarahan hebat.
Rupanya, dia baru saja menerima tamu dari seorang WN Nigeria, dan dia terlalu bersemangat. ’’Sampai jahitan delapan vaginanya. Terus saya tanya, kenapa mau diterima tamunya, dia (PSK-nya) jawab, lah penasaran pingin coba, dan ternyata memang enak,’’ kata Mbak Vera, kemudian tertawa.
Di sana, saya juga beruntung mendapatkan kisah-kisah features dan liputan investigatif. Saya pernah menulis tentang seorang PSK yang sudah teridentifikasi HIV/AIDS yang masih menjajakan diri. Kenapa masih menjajakan diri? Karena dia tak tahu jalan keluarnya. Adakah jalan kehidupan layak yang bisa diambil seorang PSK yang sudah tak terlalu muda dan mengidap HIV/AIDS untuk bertahan hidup?
Atau seorang PSK berusia 36 tahun yang hamil, lantas kemudian ditinggal suaminya dan dia harus menghidupi tiga anaknya yang lain. Jenis-jenis manusia yang terjebak dalam sebuah jenis kehidupan yang buruk, dan kemudian tak tahu bagaimana harus menatap ke depan.
Bergaul dengan Mbak Vera juga memberi saya banyak kesempatan untuk melihat sebuah dunia yang begitu absurd. Karena misi utamanya adalah mengentaskan PSK, Mbak Vera pun berupaya mencarikan alternatif kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ada yang berhasil dientaskan, dan kemudian menjadi ustadzah dan guru ngaji di kampung sekitar Gang Dolly.
Ada yang berupaya keras, kemudian mendapat skill membuat salon, dan kemudian salonnya berkembang. Tapi, yang berhasil itu mungkin tak sampai seperseratusnya. Banyak yang sudah dimodali, banyak yang sudah diberi kesempatan, tapi kemudian kembali lagi menjadi PSK.
Karena, tantangan terbesar mengentaskan PSK adalah soal easy money. Selama menjadi PSK, mereka kaget mendapat uang besar dengan gampang, lalai mengelolanya, dan ketika sudah tua dan mulai kurang laku, semuanya sudah terlambat. Suatu hal yang jelas tak bisa dientaskan dengan cara pemerintah tempo dulu: “bikin pelatihan menjahit, kasih mesin jahit, setelah itu sudah dilepas.”
Atau pernah, waktu hari AIDS sedunia, saya membuat liputan mengenai pasutri-pasutri yang salah satunya mengidap HIV/AIDS. Untuk menunjukkan bahwa dengan treatment dan perlakuan yang tepat, maka seorang pengidap HIV/AIDS bisa saja berumah tangga tanpa takut menulari pasangannya. Usai liputan, salah seorang suami yang saya liput diam-diam mendekat kepada saya, dan bilang: “mas, sebenarnya saya ini terpaksa.
Waktu mau nikah dulu, gak ngomong. Jadi, saya merasa dibohongi. Saya heran, kenapa kok sejak awal hubungan, disuruh pakai kondom terus.’’ Rupanya dia protes, baru tahu setelah setahun menikah, dan saat saya liputan, pernikahan mereka sudah mencapai lima tahun.
’’Terus gimana mas? Mosok sampeyan mau ceraikan?’’ ’’Ya gak, mas. Sudah kadung cinta, tapi ya mbok ngomong sejak dulu. Biar bisa dipikirkan,’’ katanya, masih protes. ’’Gak papa, mas. Balesannya surga, mas,’’ jawab saya, agak kurang meyakinkan.
Tapi, diam-diam saya terharu sama masnya. Begitu naif namun juga begitu baik. Dan dia masih harus menutup rapat-rapat kondisi istrinya ke keluarganya sendiri maupun teman-temannya. Biar tidak syok, katanya. Oya, ketika saya liput, tentu saja foto yang saya tampilkan di koran membuat mereka tidak bisa diidentifikasi.
Beberapa liputan ini memang sengaja saya lakukan bareng mbak Vera. Biasanya, begitu sudah selesai ditulis, maka ada orang baik yang tergerak memberikan dukungan dan bantuan. Jadi, ketika ada kasus-kasus tragis yang tak bisa kami tanggulangi, maka biasanya saya tulis.
Tujuannya, agar orang malang yang didampingi bisa dibantu oleh orang lain. Dan biasanya memang ada yang membantu. Surabaya tak kekurangan orang baik, dan kadang mereka hanya tak tahu saja ada yang menderita di sekeliling mereka.
Selama berkiprah, Mbak Vera banyak mendapat penghargaan ketika itu. Mulai dari pemerintah daerah hingga Konjen AS. Namun, semua itu tak lantas membuat dia kemudian menjadi kaya. Keadaan ketika saya kali bertemu, hingga saya terakhir bertemu pada Lebaran 2024 lalu masih sama: struggling. Pakaiannya selalu lusuh, kalaupun ada yang bagus itu kemungkinan pakaian bekas pemberian orang, dan selalu membikin aneka jajanan dan gorengan untuk mencukupi operasionalnya.
Ini yang membuat saya respect. Semua uang donasi yang diterimanya, semuanya untuk operasional kegiatan sosialnya. Karena dia begitu memikirkan yang didampinginya.
Pun ketika Gang Dolly ditutup dan banyak funding mengurangi kucuran donasinya ke LSM-LSM di Indonesia, Yayasan Abdi Asih yang dipimpinnya juga terdampak. Tiap kali harus memperpanjang sewa tempat, dia selalu mengeluh. Yang untungnya selalu saja ada jalan keluar di menit-menit terakhir.
Seiring dengan bertambahnya usia, skala kegiatan sosialnya ikut menurun. Funding makin susah didapat, dana operasional makin cekak, dan mbak Vera juga harus kerja dobel untuk sekedar mencukupi kebutuhannya. Namun, semangatnya tetap menyala. Di saat-saat terakhirnya, Mbak Vera mengasuh langsung tujuh anak-anak yang mengidap HIV/AIDS. Yang tertular dari orang tuanya.
Dengan umur berkisar antara 5 – 12 tahun. Ada yang menjadi korban KDRT sekaligus pelecehan seksual. Dengan satu mata dan sejumlah bagian hidung yang melesak akibat dipukul kayu. Ada yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Ada yang bekas keleleran, karena dia dan ibunya (yang juga sama-sama HIV/AIDS) ditolak untuk ngekos di mana-mana.
Menunjukkan satu sisi suram sosial kita. Bahwa banyak penderita HIV/AIDS dari kalangan rendah itu nasibnya lebih buruk ketimbang kematian. Tidak tahu harus bekerja apa (jangan ODHA, orang sehat saja sudah sulit cari kerja di usia di atas 35 tahun), dan begitu ketahuan sebagai ODHA, ibu kos langsung mengusir.
Tidak bisa disalahkan juga, ibu kos mana yang mau tempat kosnya ditempati ODHA. Sehingga anaknya dirawat Mbak Vera di shelter Yayasan Abdi Asih yang sekaligus kantor (yang ukurannya tak seberapa besar), sementara ibunya dikoskan di tempat lain dengan tidak mengaku ODHA.
Jenis-jenis anak yang banyak dari kita yang tak pernah kita tahu kenapa bernasib malang seperti itu. Namun, Mbak Vera merawat mereka seperti seorang ibu. Mengganti pampersnya (untuk mereka yang kadang menurun kondisinya, mereka gampang sekali berak mencret darah), tak segan memeluknya, mengajarinya ngaji, memberinya ilmu pelajaran, menguruskan obat di rumah sakit (obat ARV sangat mahal, dan satu-satunya jalan ya dengan obat gratis dari jaminan sosial pemerintah daerah).
Itu pun kadang sulit diurus jika ada apa-apa, karena mereka-mereka ini rata-rata tak ber-KTP atau tercatat dalam kependudukan.
Mbak Vera beberapa kali menghubungi saya jika ada salah satu pasien yang didampinginya tiba-tiba meninggal. ’’Kar, saya minta tolong kalau ada rezeki, bantu biaya pemakaman xxx,’’ katanya. Yang tentu saja, saya langsung mentransfernya. Biaya pemakaman plus tambahan untuk operasional, yang jumlahnya tak seberapa. Tiap Lebaran, saya selalu memberikan sebagian kelebihan rezeki saya ke Mbak Vera dan anak-anak malang itu.
Inilah yang membuat saya begitu menghormatinya. Cara Mbak Vera merawat anak-anak itu. Melihat dengan mata kepala sendiri, betapa interaksi antara anak-anak itu dengan Mbak Vera yang bukan seperti relawan dan anak yang didampingi. Namun, seperti ibu dan anak. Mbak Vera memberikan apa yang hilang dari hidup anak-anak itu: kasih sayang orang tua.
Dan ketika bertandang ke sana, saya selalu merasa malu dan tertampar. Saya tak akan pernah mempunyai kekuatan seperti Mbak Vera, yang tanpa ragu dan takut-takut menyayangi anak-anak ODHA yang malang itu. Memeluk dan melindungi mereka dari dunia yang sangat tak adil bagi mereka.
Apalagi, membaktikan hidup untuk merawat anak-anak malang ini adalah sebuah jenis pengabdian hidup yang saya sendiri mungkin tak akan pernah bisa capai. Jika merawat anak-anak yatim, itu kadang setelah besar dan mereka berhasil, maka ada semacam buah kegembiraan. Dan kadang, anak itu kemudian membalas jasa dengan membantu anak-anak lainnya yang malang.
Namun, merawat dan menyayangi anak-anak semacam ini tidak akan pernah berbalas. Mereka bisa hidup sampai dewasa saja sudah syukur. Dan seringkali anak-anak ini meninggal pada usia 13-14 tahun karena kondisinya. Saya tak membayangkan betapa hati Mbak Vera patah berkali-kali melihat anak yang dirawatnya meninggal di pelukannya (dan saya menyaksikan live berkali-kali ketika itu terjadi).
Mbak Vera tahu bahwa dia tak akan pernah mendapat balas jasa apa pun, atau tak akan pernah bisa menyaksikan anak yang dirawatnya itu sukses dan menjadi orang besar di kemudian hari. Itu yang membuat saya menaruh respek setinggi-tingginya ke Mbak Vera.
Penghormatan saya bahkan nyaris seperti saya menghormati ibu saya. Jika saya menghormat ibu saya karena jasa dan perjuangannya dalam merawat saya, maka saya menghormat kepada Mbak Vera atas jasa dan perjuangan merawat anak-anak dengan nasib sangat malang.
Mungkin ada mbak Vera-mbak Vera lain di beberapa tempat lainnya atau bahkan di Surabaya. Namun, saya merasa kehilangan. Surabaya kehilangan. Dan pastinya, anak-anak itu akan kehilangan figur yang selama ini menyayangi dan melindungi seperti ibu sendiri. Saya tak tahu bagaimana nasib mereka kelak. Apalagi, chat terakhir kami pada Oktober, Mbak Vera mengeluhkan belum ada tindak lanjut dari KPAI terkait dukungan dan bantuan untuk anak-anak ini.
Dan hanya ini yang bisa saya lakukan untuk mengenang Mbak Vera. Seorang pejuang kemanusiaan yang bergerak dalam senyap dengan hati yang sangat tulus. Semoga dilapangkan kuburnya, dan di surga nanti, saya bayangkan mbak Vera berjumpa dengan ratusan anak-anak yang pernah ditolongnya di sebuah bangsal bersih dengan banyak kasur bersprei putih dan wangi. Dan bersama-sama mereka menanti kepulangan anak-anak malang lainnya dan berbagi kebahagiaan yang tak pernah mereka jumpai selama di dunia. (*)
PENULIS

KARDONO SETYORAKHMADI
Pernah bekerja di Jawa Pos selama 17 tahun, sekarang penulis lepas dan punya kesibukan mengamati gejala perubahan sosial. Hobi merenungi kehidupan pribadi hingga menangis sesenggukan.