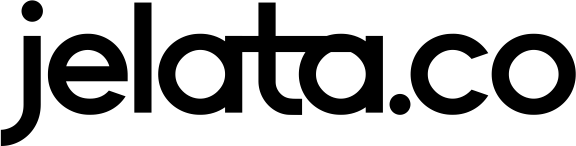Pada Maret–Juli 2017, saya dan Agung Kurniawan menyutradarai pertunjukan teater berjudul ‘Gejolak Makam Keramat’. Pertunjukan ini melibatkan ibu-ibu penyintas 65 di Jogja yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Kiprah Perempuan (KIPPER). Pertunjukan ini adalah bagian dari karya instalasi visual Agung Kurniawan yang dipresentasikan di Belgia pada rangkaian acara Europalia, Festival Budaya Indonesia yang berlangsung pada bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018.
Beberapa seniman lain ikut berkolaborasi dalam proyek ini. Di antaranya Leilani Hermiasih (musisi), Achi Pardipta (musisi), Atinna Rizkiana (perancang kostum) dan Keroncong Agawe Santoso pimpinan Erie Setiawan. Pertunjukannya sendiri digelar di Gedung PKKH UGM pada tanggal 13 Juli 2017. Dalam pertunjukan ini, kami memainkan adaptasi naskah Leng karya Bambang Widoyo SP dari Teater Gapit Solo.
Gagasan pertunjukan ini berawal dari kedekatan Agung Kurniawan dengan isu peristiwa 65. Beberapa waktu sebelumnya, Agung Kurniawan bersama beberapa musisi dari Jogja membuat konser musik yang menampilkan ibu-ibu penyintas 65 dari Jakarta yang tergabung dalam kelompok Paduan Suara DIALITA.
Dalam konser itu digelar aransemen ulang lagu-lagu bertema perjuangan hidup yang pernah dinyanyikan oleh ibu-ibu Paduan Suara DIALITA di masa lalu. Baik ketika mereka sedang berada dalam penjara maupun pada masa sebelum masuk penjara. Sebagian lagu yang ditampilkan merupakan karya yang diciptakan sendiri oleh ibu-ibu itu ketika berada di dalam penjara.
Konser ini mendapat respon yang positif dari publik sehingga mendorong Agung Kurniawan untuk melakukan eksplorasi artistik yang lebih jauh untuk membicarakan isu peristiwa 65. Keinginan itu kemudian memunculkan ide untuk mengajak ibu-ibu KIPPER membuat pertunjukan teater. Kebetulan sebelumnya, ibu-ibu KIPPER pernah punya pengalaman mementaskan pertunjukan teater di sebuah acara.
Agung Kurniawan mengajak saya terlibat setelah terjadi kesepakatan dengan ibu-ibu KIPPER. Saya menyambut ajakan itu dengan perasaan gembira sekaligus was-was. Saya gembira karena memperoleh ruang eksplorasi untuk praktik penciptaan karya saya, yang kebetulan sedang akrab dengan bentuk-bentuk penciptaan berbasis arsip sejarah dan persoalan sosial di lingkungan spesifik.
Was-was karena melibatkan ibu-ibu yang rata-rata sudah berusia lanjut, yang kondisi fisik dan psikologisnya memerlukan perhatian khusus. Apalagi waktu itu belum ada percakapan tentang gambaran bentuk pertunjukan di antara kami berdua. Yang ada hanya komitmen untuk mewujudkan ide mementaskan ibu-ibu KIPPER melalui medium teater. Hanya itu.
Ibu-ibu ini adalah korban kekerasan dari tragedi politik 65. Akibat peristiwa politik 65, mereka masuk penjara dan mengalami kekerasan fisik maupun mental yang tak terbayangkan. Bahkan, setelah keluar dari penjara, diskriminasi dan stigma yang buruk masih melekat pada diri mereka. Berpuluh-puluh tahun mereka kehilangan eksistensinya sebagai manusia.
Meskipun begitu, daya hidup mereka untuk mengatasi zaman amatlah mengagumkan. Sampai hari ini, meskipun masih mendapat tekanan dan intimidasi, mereka terus berupaya menyalakan eksistensi mereka dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berorganisasi untuk mewadahi kegiatan bersama seperti yang dilakukan ibu-ibu KIPPER dan kelompok Paduan Suara DIALITA.
Seperti halnya konser musik Paduan Suara Dialita, niat utama dari pertunjukan teater Gejolak Makam Keramat adalah menyuarakan ekspresi ibu-ibu penyintas 65 ke tengah-tengah generasi muda melalui medium seni. Hal ini dilakukan karena ibu-ibu ini adalah monumen hidup yang dibisukan dari sejarah bangsa Indonesia.
Semakin hari jumlah ibu-ibu ini semakin berkurang sementara jumlah anak muda yang tidak mengetahui sejarah mereka bertambah banyak. Dalam situasi seperti inilah kehadiran medium seni untuk menyuarakan ekspresi ibu-ibu kepada anak muda menjadi penting. Medium seni diperlukan karena memiliki kedekatan dengan anak muda dan bisa bekerja dengan cara yang kreatif.
Persoalan pertama yang harus kami hadapi ketika memulai proses adalah memilih naskah yang tepat untuk mereka. Kami membutuhkan naskah yang mampu menyampaikan persoalan sekaligus mampu mengejawantahkan daya hidup mereka di atas panggung. Setelah mengumpulkan beberapa naskah, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan naskah Leng karya Bambang Widoyo SP dari Teater Gapit Solo.
Naskah itu dipilih karena ceritanya dekat dengan persoalan yang dialami ibu-ibu KIPPER (naskah Leng ditulis tahun 1985 dan bercerita tentang perlawanan masyarakat kecil menghadapi penggusuran makam keramat di desanya yang akan dijadikan pabrik oleh pemodal). Selain juga karena menggunakan pengantar bahasa Jawa, sehingga dibayangkan akan memudahkan ibu-ibu yang mempunyai latar belakang budaya Jawa tersebut dalam memahami dan melisankan naskah.
Sempat terbesit di kepala kami untuk membuat naskah baru berdasar pengalaman ibu-ibu ketika berada dalam penjara. Akan tetapi, kami mengurungkan niat tersebut. Kami tidak ingin mereproduksi narasi kekerasan karena bisa memunculkan kembali trauma mereka. Cara itu juga hanya akan berhadapan dengan sensor publik.
Karena pada praktiknya, isu peristiwa 65 tidaklah mudah untuk disampaikan secara terang-terangan. Beberapa seniman yang berusaha untuk menggunakan isu ini sebagai karya kreatifnya, dibubarkan langsung oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang phobia dengan isu peristiwa 65.
Dalam situasi seperti itu kami memerlukan metafora sebagai jalan alternatif untuk keluar dari kebuntuan untuk mengungkapkan apa yang telah dialami ibu-ibu selama ini. Kami mengadaptasi cerita dari naskah Leng untuk keperluan itu dan mengubah judulnya menjadi ‘Gejolak Makam Keramat’.
Bentuk pertunjukan Gejolak Makam Keramat menggunakan konsep teater semakan. Konsep ini meminjam istilah semakan yang berasal dari tradisi Semakan, sebuah tradisi membaca dan mendengarkan pembacaan kitab di kalangan masyarakat Islam. Selain alasan konseptual, faktor kesulitan ibu-ibu untuk menghafalkan naskah yang panjang adalah alasan lain mengapa kami menggunakan konsep ini.
Secara teknis, konsep ini menyarankan untuk menghilangkan ruang penonton. Ruang penonton kemudian dipindahkan menjadi satu dengan ruang aktor di atas panggung. Aktor ditempatkan di kursi yang telah disusun melingkar, sementara penonton ditempatkan untuk duduk bergerombol di sekitar aktor di lantai panggung. Kedekatan jarak ini juga dirancang supaya penonton dan aktor dapat saling merasakan detail ekspresi yang muncul selama pertunjukan berlangsung.
Selama pertunjukan berlangsung penonton tidak hanya diberi ruang untuk mendengarkan pembacaan naskah saja tetapi juga dilibatkan untuk menjadi aktor. Keterlibatan mereka dimunculkan pada momen-momen tertentu yang telah ditentukan dan dipandu oleh seorang konduktor (Achi Pradipta).
Penonton didapuk untuk menjadi latar suara pertunjukan. Kadang menjadi suara pabrik, suara sirine, suara gamelan, sesekali juga dilibatkan untuk membaca naskah. Selain berfungsi menjaga suasana dan irama pertunjukan, keterlibatan penonton dihadirkan supaya pertunjukan menjadi bangunan peristiwa bersama.
Tata artistik panggung dibangun dari materi yang murah dan sederhana. Kami menggunakan lampu bohlam dan lampu neon untuk menerangi sekaligus membangun suasana panggung. Begitu pula dengan ilustrasi musik yang diproduksi dari suara mesin ketik dan alat-alat perlengkapan dapur.
Leilani Hermiasih selaku penata musik harus rela menanggalkan alat musik piano yang biasa dia gunakan sehari-hari untuk menghasilkan efek-efek suara pendukung. Di bagian kostum, Atinna Rizkiana merancang kostum dengan mengambil referensi dari model baju yang sering dipakai ibu-ibu ketika latihan dan sedikit disesuaikan dengan karakter yang dibaca.
Dia juga menambahkan detail berupa motif silet sebagai simbol dari stigma yang mereka alami. Meskipun dibangun dari materi yang murah dan sederhana, tata artistik tetap ditata sedemikian rupa supaya mampu menghadirkan kekuatan utama pertunjukan ini yang terletak pada tubuh ibu-ibu yang menyimpan sejarah perjuangan hidup yang panjang.
Total latihan dilakukan sebanyak 22 kali pertemuan setiap hari Senin dan Kamis dari pkl. 09.00 sampai pkl. 14.00 WIB. Proses latihan berlangsung di studio ICAN, sebuah studio seni rupa yang terletak di daerah Jogja bagian selatan. Ada 13 ibu-ibu yang mengikuti proses ini. Rata-rata berusia di atas 60 tahun.
Usia yang paling tua di antara mereka adalah 83 tahun. Yang mengagumkan, di setiap latihan ibu-ibu ini tidak pernah datang terlambat. Beberapa datang diantar keluarga, kebanyakan datang sendiri-sendiri. Ada yang naik becak, naik bus, naik sepeda, bahkan ada yang berjalan kaki menuju tempat latihan.
Kami melibatkan sukarelawan untuk menemani mereka selama latihan mengingat kondisi fisik ibu-ibu yang sudah menua. Beberapa ibu-ibu bahkan memerlukan penanganan khusus karena mengalami gangguan fisik akibat kekerasan yang pernah dialami ketika berada di penjara. Ada di antara mereka yang mengalami gangguan pendengaran.
Ada juga yang mengalami kesulitan berjalan. Selain bertugas menjaga kondisi fisik ibu-ibu, para sukarelawan juga bertugas membantu kelancaran proses penyutradaraan. Misalnya mengingatkan ibu-ibu jika ada yang lupa dengan gilirannya membaca, mendikte jika ada yang kesulitan membaca, menggantikan peran jika ada yang berhalangan hadir, dan sebagainya.
Proses perancangan bentuk keterlibatan penonton juga sangat terbantu oleh kehadiran mereka. Setiap saat kami bisa melakukan simulasi dan mengevaluasi materi-materi yang hendak kami gunakan untuk melibatkan penonton ke dalam pertunjukan.
Proses latihan tidak berjalan semulus yang direncanakan. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang sangat sulit ditebak suasana hati dan pikirannya. Pernah suatu ketika, seseorang dari mereka tiba-tiba menurun drastis power suaranya. Caranya membaca naskah menjadi sangat datar, tanpa ada emosi sama sekali.
Padahal di latihan sebelumnya, dia terlihat sangat ekspresif. Dia juga tidak sedang mengalami gangguan kesehatan fisik saat itu. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ibu-ibu selama latihan, naskah sering mengalami perombakan.
Begitu juga dengan susunan pemain yang juga mengalami pergantian berkali-kali. Di sepertiga akhir latihan kami terpaksa merombak total susunan pemain karena ada seseorang yang tiba-tiba harus mundur karena alasan personal.
Dalam proses ini, naskah tidak diperlakukan seperti kitab suci yang harus selalu ditaati. Naskah seperti lempung yang siap dibentuk untuk melayani kepentingan ekspresi ibu-ibu. Kami sering memotong atau mengganti teks naskah jika ibu-ibu mengalami kesulitan ketika membacanya. Biasanya karena ada kalimat yang terlalu panjang sehingga menguras napas atau karena ada kata-kata yang membelit lidah mereka.
Temuan-temuan materi dari ibu-ibu juga banyak kami gunakan untuk memperkaya dan menajamkan kekuatan naskah. Seperti lagu-lagu, kemampuan memainkan alat musik dan dialog-dialog yang tidak sengaja muncul saat latihan. Salah satu lagu yang muncul saat latihan adalah lagu yang berjudul ‘Rawa Pening’. Lagu itu berirama langgam keroncong dan liriknya diingat oleh salah satu peserta bernama bu Nik.
Bu Nik adalah bekas penyanyi istana negara. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, dia sering tampil bernyanyi di hadapan presiden Soekarno. Sayangnya nasib malang menimpa dirinya. Dia kehilangan rumah, keluarga dan tidak pernah tampil bernyanyi lagi setelah keluar dari penjara. Umurnya sekarang 83 tahun.
Untuk menampilkan kembali suara emas bu Nik di masa lalu, kami mengundang Keroncong Agawe Santoso pimpinan Erie Setiawan untuk mengaransemen ulang dan mengiringi bu Nik menyanyikan lagu Rawa Pening di pengujung pertunjukan.
Bagian produksi memegang peran yang tak kalah penting. Mereka adalah tulang punggung pertunjukan ini. Venti Wijayanti dan Pipiet Ambarmirah selaku produser dan asisten produser tidak hanya bertugas menyokong persiapan teknis pertunjukan tetapi juga menjadi caregiver bagi ibu-ibu KIPPER. Pipiet Ambarmirah adalah koordinator ibu-ibu KIPPER yang telah mendampingi mereka sejak tahun 2006.
Ia merupakan anak dari salah satu ibu-ibu tersebut. Kehadirannya juga ikut membantu memberi rasa aman dan rasa percaya ibu-ibu ketika harus bekerjasama dengan orang yang baru dikenal seperti kami. Yang mengejutkan dari kerja keproduksian adalah keberhasilan meyakinkan pemerintah dan kampus untuk ikut terlibat mendukung pertunjukan ini, mengingat selama ini pihak pemerintah dan kampus cenderung menghindar ketika diminta untuk mendukung acara-acara yang membicarakan isu peristiwa 65.
Pada hari pelaksanaan pertunjukan, produser membuka reservasi bagi 200 penonton pertama dan tenyata antusias pendaftar sangat besar, sehingga akhirnya kami menerima sampai 300-an penonton untuk hadir. Pertunjukan diawali dengan membagi penonton menjadi 4 kelompok. Plantungan, Ambarawa, Bulu dan Jefferson. Nama-nama kelompok ini diambil dari nama-nama tempat penahanan ibu-ibu penyintas 65.
Penonton kemudian diajak untuk melakukan simulasi bentuk keterlibatan yang akan digunakan selama pertunjukan berlangsung. Proses ini dilakukan di luar panggung. Agung Kurniawan, Achi Pradipta dan Leilani Hermiasih memandu dan mengolahnya menjadi peristiwa pertunjukan. Setelah simulasi selesai, aktor dan penonton bersama-sama masuk ke panggung untuk memulai proses pembacaan naskah. Peristiwa ini belangsung selama kurang lebih 2 jam dan diakhiri dengan penampilan bu Nik menyanyikan lagu Rawa Pening.
Secara umum pertunjukan berjalan dengan lancar. Ibu-ibu dan penonton tetap bertahan sampai selesai. Sebenarnya kami menyediakan dokter untuk berjaga-jaga jika ada ibu-ibu yang tumbang di tengah jalan. Di luar dugaan, mereka justru tampil sangat bersemangat. Seperti ada tenaga tambahan yang datang entah dari mana.
Energi mereka yang terpendam selama ini seperti manjing di atas panggung. Pertunjukan malam itu ditutup dengan penampilan bu Nik yang sangat memukau. Dia menjelma menjadi diva panggung. Sisa-sisa suara merdu di masa jayanya mencekat perhatian penonton. Ruangan pertunjukan dipenuhi dengan tepuk tangan dan rasa haru ketika beliau selesai melantunkan lagu Rawa Pening.
Proses penciptaan pertunjukan Gejolak Makam Keramat yang berlangsung selama kurang lebih lima bulan ini menyisakan catatan-catatan penting bagi saya. Catatan pertama saya adalah soal keterlibatan penonton dalam pertunjukan. Munculnya bentuk ini saya kira dipengaruhi oleh nalar produksi seni rupa yang terbawa oleh kehadiran Agung Kurniawan dalam proses penyutradaraan.
Sebab bentuk keterlibatannya memaksa penonton untuk aktif bergerak ketika menikmati karya, seperti cara penonton melihat karya seni di ruang pameran seni rupa. Di luar bentuknya yang masih terasa dipaksakan, ide ini berhasil memicu saya untuk melihat ulang aspek kepenontonan di wilayah pertunjukan teater.
Hal ini membuktikan bahwa, sudut pandang baru dimungkinkan muncul jika kita mau bertemu dengan tradisi dan disiplin seni yang berbeda. Keterlibatan penonton juga ikut mendorong para aktor memunculkan energi ketika mengekspresikan pembacaan naskah. Karena faktor itulah ibu-ibu KIPPER tampil prima di atas panggung.
Yang kedua saya mencatat soal kehadiran ibu-ibu KIPPER sebagai aktor pertunjukan. Jika dilihat menggunakan ukuran-ukuran estetika normatif, ibu-ibu ini adalah aktor yang memiliki ketrampilan teknis yang minim. Kekuatan ibu-ibu ini sebagai aktor terletak pada sisi kesejarahan tubuhnya yang terkait dengan isu yang sedang dibicarakan dalam pertunjukan.
Kami menghindari cara-cara konvensional untuk mengolah potensi keaktoran itu. Kami lebih memilih mengolah pengalaman batin ibu-ibu KIPPER untuk dihadirkan di atas panggung daripada mengejar standar ketrampilan teknis konvensional.
Pertunjukan ini menempatkan pengalaman batin sebagai arsip untuk mengkomunikasikan persoalan sejarah kepada penonton. Alih-alih mereduksi kenyataan sejarah, pilihan ini justru memperluas ruang imajinasi penonton dalam memahami kenyataan sejarah.
Berpuluh-puluh tahun ibu-ibu KIPPER hidup tidak dimanusiakan (ora diuwongke). Kami berharap pertunjukan Gejolak Makam Keramat dapat berfungsi memanusiakan (nguwongke) kembali keberadaan ibu-ibu KIPPER di tengah zaman yang masih belum berpihak kepada mereka.
Konsep pertunjukan Gejolak Makam Keramat merupakan konsep pertunjukan teater yang praktis dan fleksibel sehingga masih bisa diaplikasikan dan dikembangkan untuk membicarakan isu-isu yang lainnya. Bukan hanya terbatas pada isu sensitif seperti peristiwa 65. Akan tetapi, juga isu sehari-hari yang ada di sekitar kita hari ini.
Melalui pertunjukan ini saya merasa teater tampil dengan kesegarannya, tidak pasif dan tidak menjadi beku. Teater dapat dipraktikkan secara kreatif untuk memahami kenyataan sejarah sekaligus dapat menghidupkan kembali harkat dan martabat kemanusiaan yang pernah dihilangkan.
Kotagede, 27 Januari 2018
Penulis

IRFANUDIEN GOZALI
Lahir dan tumbuh di kota Jogja. Mulai berteater pada tahun 2003 di Teater Gadjah Mada UGM. Sejak tahun 2010, pria ramah yang lahir pada 20 Juli 1982 ini mulai melibatkan diri dalam proyek – proyek pertunjukan di luar kampus sebagai aktor, fasilitator maupun pencari data. Selain itu juga mulai menyutradarai pertunjukannya sendiri. Beberapa pertunjukan yang pernah disutradarai antara lain : Leng , Nggoleki Jimate Basiyo. Masihkah Ada Cinta di Kampus Biru. Bank Pasar Rakyat. Nyadran Kang Sejo Melihat Tuhan, Ziarah Ari – Ari, Gejolak Makam Keramat. Ia juga banyak terlibat dalam produksi pertunjukan bersama sejumlah komunitas, antara lain Teater Garasi, Teater Gardanalla, Forum Aktor Yogyakarta, Indonesia Dramatic Reading Festival, Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, dan Asian Dramaturgs Network. Fokus karya-karyanya banyak berangkat dari arsip sejarah di lingkungan spesifik.