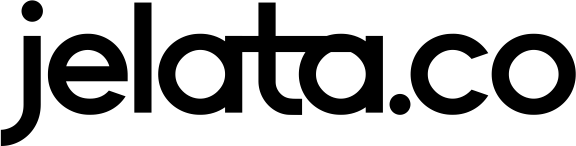Slobodon duduk di beranda, menatap langit yg tak lagi punya papan tulis. Barangkali langit dulu memang tempat belajar paling luas di sanalah manusia membaca arah, menafsir musim, dan menimbang makna hidup. Tapi kini, langit tinggal layar kosong seolah tak lagi menyimpan pertanyaan, hanya memantulkan kebisingan bumi.
Setiap hari, manusia semakin percaya diri menasihati semesta. Di layar2 kecil yg digenggam dengan jari penuh minyak gorengan, setiap orang menjadi pengkhotbah membicarakan politik tanpa membaca sejarah, membahas moral tanpa pernah menatap dirinya sendiri. Dunia kini bukan lagi arena pencarian makna, melainkan perlombaan siapa paling terdengar bijak.
Slobodon melihat fenomena itu seperti melihat sekolah yg bubar tapi gurunya tetap berdiri di depan kelas, berbicara pada kursi kosong. Dunia kini dipenuhi guru tanpa sekolah, tanpa kelas, tanpa murid. Semua berbicara, tak ada yg mendengar. Semua memberi petuah, tak ada yang menelusuri makna.
Barangkali karena itulah Slobodon melarang anaknya menjadi guru.
“Apa gunanya mengajar, Nak, kalau murid-muridnya sudah lebih sibuk menilai ketimbang memahami?” katanya suatu pagi sambil menyalakan rokok terakhirnya.
Ia tidak sedang merendahkan profesi guru, justru sebaliknya: ia sedang menangisi hilangnya makna seorang murid.
Pengetahuan hari ini, pikirnya, tak lagi tumbuh dari rasa ingin tahu, melainkan dari rasa ingin menang.
Diskusi berubah jadi adu argumen.
Dialog berubah jadi duel wacana.
Dan guru yg dulu dihormati karena kebijaksanaannya kini diukur dari jumlah pengikut di dunia maya.
Pengetahuan kehilangan kesabaran, kehilangan jeda, kehilangan keheningan yg dulu menjadi ruang bagi pemahaman tumbuh.
Slobodon membayangkan dunia tanpa murid.
Dunia yg penuh orang cerdas tapi kehilangan rasa ingin tahu.
Dunia yg penuh suara tapi miskin pendengaran.
Tanpa murid yg mau bertanya dengan polos, tanpa ragu yg jujur, tanpa kesediaan untuk tidak tahu, pengetahuan hanya akan jadi kebanggaan yg bising.
Manusia akan terus berputar di lingkaran egonya sendiri berbicara keras agar terdengar pintar, padahal tak lagi tahu apa yg sebenarnya sedang dibicarakan.
Ia menatap secangkir kopinya yg mulai dingin,
dan bergumam lirih,
“Mungkin sudah saatnya kita berhenti mengajar sejenak…
dan belajar lagi menjadi murid .. bagi hidup, bagi alam, bagi sunyi yg tak pernah memamerkan apa-apa.”
Sebab menjadi murid bukan berarti rendah, melainkan rendah hati.
Bukan tentang kepatuhan membuta, melainkan keberanian untuk tidak tahu.
Menjadi murid berarti mengakui bahwa dunia selalu lebih luas dari kepala kita, bahwa setiap orang yg kita temui, bahkan yang kita benci, mungkin sedang membawa pelajaran yang belum kita pahami.
Dunia tanpa murid adalah dunia tanpa pertumbuhan.
Ia hanya akan melahirkan manusia yg tau segalanya, tapi kehilangan kebijaksanaan.
Sebab di dunia tanpa murid, yg tersisa hanyalah kebanggaan tanpa pengetahuan yg hidup, tanpa kebijaksanaan yg berakar.
Dan mungkin, ketika manusia berhenti mau menjadi murid, di situlah sesungguhnya peradaban berhenti belajar menjadi manusia.

Ab Asmarandana. Seorang teaterawan sekaligus Dosen di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pendiri Ngaos Art. Beliau juga Mengelola Lanjong Art Festival di Tenggarong, Kalimantan Barat.