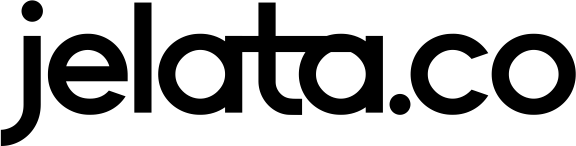Rhien, aku kembali ke desa ini bersama guguran bunga-bunga durian yang serupa lonceng dan bergelimpangan sepanjang jalan berliku menuju rumah dalam balutan warna putih keemasan. Di sepanjang jalan itu, masih bisa kuhirup sedap wangi bakaran kleang (daun cengkih) yang menguar dari cerobong asap milik rumah Pak Topik di pinggir tebing.
Lewat embus angin yang membawa aroma hujan serupa sekam kering tebakar yang menguar dari tanah basah, aku ingin tahu bagaimana kabarmu saat ini? Apakah kau sudah punya anak yang lucu-lucu? Suami ganteng dengan sedikit cambang di pipi seperti yang kau idamkan dulu. Ah, berbeda dengan daguku yang polos rata seperti meja tanpa bulu-bulu halus di sana. Aku benar-benar penasaran dan ingin bertemu denganmu walau aku tak yakin. Sebab takdir acapkali menceritakannya secara berbeda.
Rhien, masih sangat kuingat dulu, di bawah dingin gemericik air yang turun langsung dari pegunungan, menuruni gundukan bukit-bukit hijau dari atas, menyusur kelokan lembah serupa tubuh ular, menyelami dan menyelinap dalam celah-celah bebatuan, hingga aliran itu sampai di pinggir kali sebelah rumahmu. Kita, teman perempuanmu Asri dan teman lelakiku Sipran, sekali waktu saat pulang dari TK berenang di kali, di bawah rindang pohon durian, lontar, duku, dan manggis yang berjajar di tepi lereng bukit.
Senja menyaksikan kita dan berkata bahwa ketelanjangan bukan hal tabu kala itu. Kita masih kanak-kanak dan kulihat hanya kamu yang pakai celana dalam. Tiga bocah lain termasuk aku adalah bocah polos mirip lakban bening yang belum paham arti malu. Tertawa cekikikan ke sana kemari tanpa sehelai benang pun. Kadang aku membayangkan andai saja sekarang kita yang kepala tiga masih diperbolehkan melakukan hal sama? Agak kurang ajar sepertinya. Haha, sudah pasti jika ketahuan kita akan digiring ke kelurahan bersama Pak RT atas nama melanggar norma. Kita manusia, bukan binatang.
Namun, sepanjang jalan ini hingga saat tukang ojek melewati depan rumahmu, tak tampak dirimu semisal sedang menyapu halaman dengan sapu lidi atau memotong kayu-kayu kering untuk api bakar. Barangkali kau di dalam rumah. Tunggu. Aku akan ke rumahmu setelah bertemu ibuku dulu.
“Silakan masuk Nak. Duduk.”
Seorang perempuan paruh baya duduk di depanku dengan senyum manis serupa lumeran gula jawa. Namun, senyum itu seolah terpendam di kedalaman kerut wajah yang layu.
“Bagaimana kabar Rhien, Bu? Aku hilang kontak sejak di Jakarta. Ia ganti nomor.”
“Ia sudah jauh tenang dengan segala kenangan yang dibawanya.”
“Kabar terakhir sebelum aku pergi, ia dekat dengan orang seberang. Semoga kesehatan selalu menyertai keluarganya.”
Sejenak hening. Ibu Rhien tak melanjutkan kata-kata. Lalu bersuara lagi dalam getar. Belasan tahun lalu, ketika aku dan Rhien masih pakai celana bawahan abu-abu ke sekolah, ia ceritakan Pak Oki datang pagi itu ke rumah karena ia merasa, balas budi mirip sebuah utang. Maka, ketika pintu depan diketuk, ibu Rhien gegas membuka, ia lihat Pak Oki telah bersama tiga ajudannya yang ganteng dan kekar idola emak-emak di seluruh nusantara. Mereka berkemeja putih rapi dengan setelan celana hitam. Seragam. Di halaman rumahnya yang becek karena deras hujan semalam, dalam keteduhan, ia lihat mobil sedan hitam mengilat telah terparkir. Segera ia menyilakan mereka semua masuk dan duduk di atas kursi rotan sederhana ruang tamu. Sedikit kaget mereka datang tanpa telepon dahulu.
“Apa kabar Bu? Bapak ada?”
“Seperti yang Bapak lihat. Alhamdulillah, saya dan keluarga tidak kekurangan suatu apa pun. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya? Maaf, bukankah yang kemarin sudah selesai. Pak Iban akan dilantik jadi lurah jika tidak ada gugatan. Saya merasa terharu Bapak dan Mas-Mas ini mau berkunjung ke gubuk saya yang reyot ini. Lagi pula suami saya sedang menagih uang kleang ke pengepul. Apa tidak nanti saja?”
“Tidak Bu. Hanya ingin cerita tentang balas budi sebuah paku.”
“Paku?” Ibu Rhien lamban paham. Butuh waktu mengunyah perkataan Pak Oki ketika tetiba ia mengangguk ramah kepada Rhien yang muncul tiba-tiba, dan telah membawakan empat gelas kopi hitam yang wangi di nampan. Rhien membalas dengan anggukan ramah pada mereka, menyilakannya. Ia melangkah kembali masuk, membuka korden pintu ruang tamu, lalu hilang dari pandangan.
“Satu paku satu suara. Paku yang telah berjasa membuat Pak Iban terpilih jadi lurah di kampung ini.”
“Pak Iban terpilih karena memang ia ringan tangan, cepat dan tanggap membantu warga yang kerepotan. Ia selalu ada di mana warga membutuhkan. Tanpa pamrih, tanpa imbal balik yang ia harapkan. Sudah sepatutnya ia terpilih.”
“Itu ‘kan menurut Ibu. Kita sudah terbiasa kok, suara bisa dibeli dengan uang Bu. Siapa yang modalnya lebih besar, biasanya ia yang menang.”
“Bukan dilihat dari tingkah laku dan kerja nyata di masyarakat ya? Pantas saja negara ini tak maju-maju. Bukan takdir yang menentukan? Tuhan mau kau suap? Aneh.”
Pak Oki diam sejenak. Ia tahu perempuan di depannya tak paham fakta di lapangan. Lalu ia mengalihkan pembicaran.
“Ini ada ucapan terima kasih dari kami. Suami Ibu telah berjasa dalam kemenangan Pak Iban. Balas budi harus dibalas bukan? Dan ini, ada sedikit surat untuk Ibu. Dibaca nanti saja. Mohon maaf, Pak Iban belum bisa ke sini secara langsung. Lain kali mungkin akan mampir. Beliau sangat sibuk saat ini. Kami pamit. Mohon diterima. Kalau mau dikembalikan, konfirmasi ke Bapak dulu ya.”
Ibu Rhien mengangguk sambil menelan ludah, melihat amplop coklat tebal di meja. Ia kemudian melihat dari belakang punggung-punggung lelaki kekar yang keluar pintu. Tampaknya, kemenangan Pak Iban tentu saja bukan atas nama kerja keras suaminya. Pak Iban memang pantas jadi lurah ketika itu. Namun, ketika ibu Rhien membuka surat itu, ada yang bergolak di dada ibu Rhien serupa gelembung air mendidih, hingga pada deret kata …
… kebun kleang milikku sudah aku sewakan untuk kalian. Uang pengganti kerja keras kalian dan timses sudah aku berikan. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa saya beli Bu. Ketenangan, ketentraman, rasa nyaman berkumpul bersama keluarga. Enam tahun aku selalu ingin menghilangkan kesepian itu. Aku tak tahu kenapa Tuhan tega mengambil istri dan dua anakku secara bersamaan ketika longsor saat itu. Dan untuk itu, mohon maaf sekali, jika Ibu berkenan, aku akan datang untuk Rhien. Sekali lagi, jika ibu mengizinkan. Salam.
***
“Setelah lulus kau akan ke mana Rhien?”
“Pengen langsung cari kerja.”
“Loh, bapakmu punya empat pabrik suling cengkih. Kau pasti bisa kuliah. Jadi dokter, jadi guru, jadi PNS. Bukankah kau dulu yang ingin mematahkan stigma jika orang gunung tak bisa sekolah tinggi?”
“Kamu sendiri?”
“Aku mau langsung cari kerja. Teman dekatku yang ngajak. Jakarta.”
“Setelah ini, setelah kita berpisah untuk tujuan masing-masing, kuharap kau selalu mengabari keadaanmu ya.”
“Tentu saja. Namun, aku punya pertanyaan untukmu. Kemarin malam kulihat di rumahmu ramai sekali. Aku tak tahu acara apa. Bisa sedikit cerita?”
“Jika kau suka warna biru, apa bisa dipaksa menyukai warna abu-abu?”
“Berjalannya waktu bisa saja. Pikiran manusia sering berubah-ubah. Namun, aku lebih tak paham maksudmu.”
“Biar takdir yang menceritakannya nanti.”
***
Setelah masa jabatan enam tahun Pak Iban selesai, untuk aturan baru lurah yang terpilih bisa menjabat selama delapan tahun. Hingga selesai pencoblosan, Pak Iban kalah tipis saat mencalonkan diri lagi. Saat itu ibu Rhien sedikit percaya, siapa banyak uang, dia bisa menentukan kemenangan. Dengar-dengar, rival Pak Iban kali ini seorang milyarder dari kota yang pulang kampung dan nyalon lurah. Setelah kekalahan itu, Pak Iban menarik semua bantuan untuk bapak Rhien. Membatalkan janji. Dan kebun kleang miliknya ditarik kembali. Beruntung, bapak Rhien masih punya pekarangan sendiri di lereng bukit, walau kecil, untuk biaya hidup sehari-hari.
Namun, hal aneh selanjutnya adalah pada Rhien, yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi pemurung. Seharian ia mengurung di kamar. Padahal, semua yang ia cita-citakan sering ia ceritakan ke ibunya. Tubuhnya layu serupa daun pisang kering. Ia seolah tak punya daya menghadapi kemelut di keluarganya. Ketika ia tahu duduk perkaranya, jumlah suara yang didapat Pak Iban dan rivalnya sama. Hanya saja, keterwakilan wilayah di empat dukuh menjadi penentu kemenangan. Pak Iban hanya mewakili kemenangan di tiga wilayah dukuh. Aturan itu yang menjadikannya rival Pak Iban menang.
Di mata masyarakat Pak Iban memang lelaki sempurna. Lelaki yang belum genap empat puluh tahun dengan tubuh tinggi dada bidang, rambut selalu klimis dengan dagu putih licin bersih serupa lantai selesai dipel, tetapi desas-desus selalu tak bisa dikendalikan. Warga seolah janggal dan sok tahu jika anak dan istrinya dikorbankan demi kekayaan. Sebagian menyangkal, itu asli bencana. Sebagian besar lagi membenarkan, seolah itu azab yang harus diterima Pak Iban. Sebuah batu besar menggelinding tepat di atas rumahnya. Meremukkan semua yang ada di dalam ketika Pak Iban pergi. Sedikit longsoran tanah menimpa rumah tetangga. Namun, tak ada korban. Hanya tiga orang keluarga Pak Iban saja yang terkena musibah itu.
Ibu Rhien meneruskan kembali cerita itu ketika aku melihat, kali ini pipinya telah basah. Aku terlalu fokus pada cemilan di meja dan lupa ada sebuah hati di sana yang barangkali serupa bawang cacah yang teriris tipis-tipis. Keluarga Rhien menolak lamaran. Rhien masih ingin sekolah kala itu. Dan setelah penolakan itu. Rhien mendadak aneh. Tak mau makan. Mengurung diri. Lalu mengubur semua cita-citanya yang belum terlaksana bersama raganya ke dalam tanah. Bersama-sama.
***
Rhien, menyesalkah aku kembali ke kampung ini? Kakiku terasa berat menapaki jalan menanjak menuju arah pulang. Namun, aku tak ingin menangis. Sudah kukumpulkan semua keping kenangan yang tercecer ke dalam dada dengan segenap jiwa raga. Seandainya kau masih sendiri_dan masih ada_ingin aku mengajakmu ke meja pak penghulu lalu membawa dirimu ke rumahku yang baru saja kubeli di Jakarta.
Hari ini, masih saja kuingat selepas pelukan itu. Benar bukan? Di Kedungrante, dalam pelukan gerimis yang merangkul tubuh kita, takdir acapkali menceritakannya secara berbeda.
Biodata Penulis
Dody Widianto lahir di Surabaya. Silakan kunjungi akun IG: @pa_lurah untuk kenal lebih dekat.