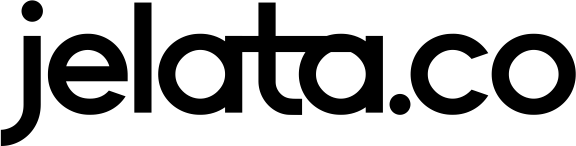Solo Mime Parade diselenggarakan kedua kalinya oleh Solo Mime Society tempo hari, 13 Juni 2014 di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Menarik bahwa peristiwa langka ini diawali dengan Diskusi pantomim sore harinya dengan tiga pembicara. Mereka dikenal sebagai sutradara, aktor dan esais (Hanindawan, YE Marstyanto, dan Bandung Mawardi). Moderator oleh RSW Lawu. Pada pada malam harinya, parade pertunjukan pantomim disuguhkan kepada khalayak dengan menampilkan enam garapan dari enam kelompok: Teater Thoekoel, Teater Lugu, Himatis ISI Surakarta, Alya & Tara, Kang Ututh dari GSP (Gubug Seni Pantomim), dan dari Solo Mime Society.
Pantomim, sebagai sebuah bentuk pertunjukan, boleh dikatakan cukup populer, meskipun di lain pihak merupakan pertunjukan yang jarang dapat disaksikan secara langsung kecuali di televisi sebagai “gimmick” iklan atau penyerta dalam “show” tari modern. Dan, paling sering kita hanya ketemu Septian Dwi Cahyo yang adalah pemain pantomim satu-satunya yang berhasil meraih popularitasnya dan mempopulerkan seni pantomim melalui media televisi. Dugaan: mungkin sejak penampilannya berpantomim dalam serial TVRI, “Rumah Masa Depan”, yang dibintanginya sekitar masa 1980-an dulu. Dan, belakangan ia juga mengunggah video-video penampilan dan tutorialnya di YouTube). Gara-gara populer tetapi jarang, maka antusiasme penonton dalam acara ini cukup menggembirakan.
Lebih dari itu, penulis merasa bahwa dalam arus informasi-komunikasi dimana berjejalan kata-kata dan retorika hari-hari ini, pantomim menjanjikan sesuatu yang berbeda. Siapa tahu, laku, gerak dan mimik, tanpa kata dapat memberikan semacam alternatif pencerahan, ketika penonton secara merdeka mengolah informasi yang dominan visual menjadi sesuatu yang imajinatif, asosiatif, introspektif, dan konklusif. Keberagaman tema garapan dalam keenam pertunjukan kali ini adalah menu yang kaya nutrisi. Pantomim bukan hanya rangkaian peragaan berjalan di tempat, bersandar di tembok, memetik bunga, berpelukan, memegang tali, atau melompati kali.

Alya dan Tyara membuka rangkaian pertunjukan dengan “Sendiri”. Penampilan dua siswi SD ini cukup memukau penonton dengan kemampuan masing-masing untuk menunjukkan bakat dan hasil latihan yang cukup memadai: mengantarkan sebuah narasi yang, sayangnya, menurut penulis terlalu muram untuk dibawakan oleh dua anak manis ini. Gerak dan mimik mereka cukup artikulatif sehingga hampir tak ada masalah bagi penonton untuk mengikuti alur cerita yang membingkainya.
Apalagi dengan karakterisasi tokoh yang cenderung realistis, seorang ibu, wanita karir, dengan kostum tipikal wanita pekerja kantor, dan seorang anak, meskipun masih dengan atribut khas pantomim, kaus tangan dan make-up topeng pantomim. Unsur-unsur itu membuat penceritaan menjadi gamblang: seorang ibu single parent dengan seorang anak yang kesepian karena ibunya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kesibukannya, ibu ini bahkan tidak terkesan dengan kejutan ulang tahun dari anaknya, hingga akhirnya ia menjadi korban kecelakaan lalu lintas ketika berangkat bekerja.
Pertunjukan “Sendiri” ini cukup menarik terlepas dari beberapa hal di sisi gagasan dan penggarapan yang masih memerlukan perhatian. Klise pada pilihan tema dan cerita, misalnya, masih harus menanggung logika ruang imajiner dan pengadeganan yang masih agak kedodoran. Andai saja, misalnya, blocking pintu tidak bergeser-geser, atau tidak ada kemunculan tokoh mimer pelawak yang terkesan dipaksakan yang malah merusak bangunan dramatik dari narasi yang dibawakan oleh dua anak berbakat ini.
Teater Thoekoel menyajikan tema besar tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Entah, mengapa pertunjukan yang membawa nilai nasionalisme ini justru diberi judul dengan bahasa Inggris: “Red White”, yang secara gramatikal penggabungan dua kata sifat ini membentuk frase yang tidak bermakna. Padahal, ejaan kata “thoekoel” yang dibentangkan pada semacam spanduk yang membuka pertunjukan ini cukup memberi nuansa latar zaman perjuangan.
Pertunjukan “Red White” menjadi menarik karena usaha yang keras dari kawan-kawan Teater Thoekoel untuk membebankan sebuah narasi besar berlatar sejarah pada bentuk pertunjukan pantomim. Beban inilah yang barangkali memaksa penggunaan properti muncul dalam pertunjukan pantomim ini. Hal ini sah-sah saja selama pemain tidak kehilangan ruang eksplorasi geraknya sehingga kita tidak terlalu banyak kehilangan idiom-idiom gerak pantomim yang khas. Atau, mungkinkah kekhasan inilah yang sengaja ingin dibongkar?
Himatis ISI Surakarta memberi judul yang tak biasa untuk repertoarnya, “:) :(“. Pertunjukannya pun tak biasa. Seorang tokoh mime tampil ke panggung dengan membawa sebuah patung yang diperankan oleh seorang aktor. Adegan-adegan mengalir seputar bagaimana si tokoh mengeksplorasi bentuk patung dengan peralatan pahat (atau tempa)-nya. Beberapa bagian adegan menjadi lelucon slapstick yang cukup segar. Misalnya, ketika patung ditempa di satu bagian menyebabkan perubahan bentuk tiba-tiba sehingga bagian lain dari tubuh patung mengenai si tokoh dan direaksi dengan mimik yang lucu.
Penonton pun terhibur. Lelucon yang sama berulang. Hingga ketika si tokoh hendak menempa bagian vital dari patung, si patung pun tak lagi pasrah. Kali ini dia menolak atau melawan. Ia mengejar si tokoh hingga ke belakang panggung, dan penonton mengakhiri pertunjukan dengan tepuk tangan. Tetapi, ternyata si patung muncul lagi dengan kostum si tokoh dan memberi kesan bahwa si tokoh pematung itu telah dikalahkan oleh patung pemberontaknya. Sebagai tontonan dengan gagasan yang absurd dan metaforik, sajian ini cukup menghibur.
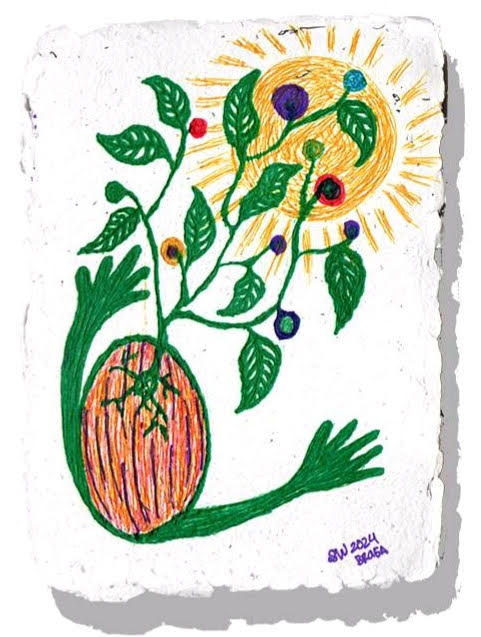
Teater Lugu mengisi paruh kedua rangkaian pertunjukan dengan narasi romantis bergaya popular ala Korea. Paling tidak ini tampak pada ilustrasi dialog yang tak jelas bahasa apa, tetapi intonasinya biasa kita dengar dalam drama-drama Korea. Dengan penceritaan realis dan alur linear, pertunjukan ini tampaknya dimaksudkan untuk mudah dipahami dan menghibur. Dan, itu berhasil! Tanpa membaca sinopsis pun penonton akan dengan mudah memahami unsur-unsur intrinsik yang menyusun narasi pertunjukan ini.
Kostum, deskripsi setting yang muncul dari gerak aktor dan aktrisnya, musik, dan vokabuler gerak yang akrab, memudahkan penonton untuk mencerna pertunjukan ini mentah-mentah. Semua hal yang hadir dalam lihatan dan dengaran membuat pertunjukan ini terlalu gamblang untuk memungkinkan tafsir yang beragam dari penonton. Semua pasti akan sepakat tentang apa yang berlangsung di atas panggung dan itulah yang tampaknya ingin coba disuguhkan. Pertunjukan ini sangat menghibur bagi yang memang ingin mencari hiburan.
Kang Ututh menggunakan idiom-idiom gerak pantomim untuk menggambarkan laku perbuatan tradisional atau rural. Dia gambarkan bagaimana seorang tokoh dengan piranti yang digambarkan sebagai golok atau parang, menebang pohon/gedebog pisang yang kemudian digunakan sebagai media untuk menancapkan wayang dalam pertunjukan wayang. Sebuah laku sederhana yang kita jumpai sehari-hari.
Yang menarik adalah ini diceritakan dalam bentuk pertunjukan pantomim. Hal ini menjadi pengingat bahwa pantomim, ketika diniati untuk dilakoni, memang harus kita tarik untuk menjadi kesenian yang tidak berjarak, terlepas dari sejarahnya. Gagasan pertunjukan pantomim dapat saja bersumber dari keseharian kita, dari latar belakang kultural kita, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa pantomim berasal dari akar tradisi pertunjukan Barat.
Solo Mime Society menegaskan sekali lagi bahwa keseharian adalah sumber inspirasi yang tak habis-habis untuk digarap menjadi pertunjukan pantomim. Sebut saja laku mencuci, bermain, menata meja makan, makan, berkelahi, bahkan tidak hanya laku perbuatan manusia. Gerak tumbuhan pun dapat menjadi gerak teatrikal pantomim yang menarik. Tema pun dapat pula berkembang dari penceritaan realis menjadi surealis.
Menyaksikan rangkaian pertunjukan dalam Solo Mime Parade kali ini, memberi gambaran pada kita bahwa pantomim mempunyai ruang jelajah gagasan yang tak terbatas. Selain itu, dari segi teknis, pantomim juga sangat mungkin berkembang melalui eksplorasi terus menerus oleh para pelakunya. Akan mungkin bermunculan banyak gaya, aliran, mazhab atau apapun namanya, masih dalam bingkai seni pantomim dan itu sah saja. Sehingga, tak perlu ada grup atau kelompok yang mengklaim “lebih pantomim” dari yang lain asalkan masing-masing terus berikhtiar untuk mengejar kesempurnaan teknik-teknik yang dipercayainya.
Di luar persoalan-persoalan teknis dan isi pertunjukan, peristiwa perayaan satu malam ini menunjukkan bahwa seni pantomim dapat berdiri sendiri sebagai seni pertunjukan yang utuh dan solid. Ia bukan hanya metode latihan keaktoran. Ia bukan hanya pertunjukan sisipan dalam bingkai acara resepsi, promosi atau eksibisi. Ia adalah bentuk seni pertunjukan yang harus terus diperjuangkan.
Solo Mime Parade ibarat piring saji seni pantomim. Maka agar piring ini secara berkala terus terisi, dapurnya harus terus “ngebul”. Proses harus terus berlanjut karena khalayak menunggu Solo Mime Parade berikutnya. Siapa tahu kita lebih beruntung dapat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan dari kelompok-kelompok pendukung Solo Mime Society secara mandiri. Selamat!
Penulis

Wirawan, lahir di Surakarta hampir 45 tahun lalu, mengenal dan lalu menyukai seni sejak nemu buku Puisi Dunia Djilid 1 Balai Pustaka tergeletak di kamar Pakliknya waktu SD.
Dia baru berani masuk teater di tahun kedua masa kuliah. Clingus dan grogian membuatnya milih belajar jadi sutradara yang ndak perlu tampil.
“Monumen”-nya Indra Tranggono, “Dalam Bayangan Tuhan”-nya Arifin C Noor, “The Party”-nya Salvomir Mrozek, “Petang di Taman”-nya Iwan Simatupang, lakonnya “K[em]edol”, dll. pernah digarapnya bersama Kelompok Peron Surakarta.
“Riders to the Sea”-nya John M Synge, “The Importance of Being Earnest”-nya Oscar Wilde, “The Sea Gull”-nya Anton Chekov, dll. pernah digarapnya bersama Solo English Arts Theatre.
“The Zoo Story”-nya Edward Albee dan lakonnya “[Su]jarah” sempat digarapnya bersama Sindikat Sandiwara.
Jadi aktor dan sutradara pocokan pun pernah dijalani.
Tapi itu dulu.
Sekarang dia lebih banyak jadi penonton teater tingkat karisidenan, tinggal di Karanganyar, dan mencari nafkah dengan menjadi Guru di SMA Negeri di Surakarta, sambil diam-diam kepingin nggarap Waiting for Godot saklek-saklekan.