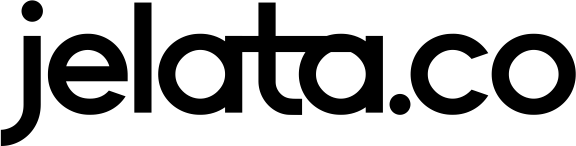Adzan maghrib berkumandang. Sebuah penanda yang dinantikan. Semua orang yang berpuasa seolah terprogram untuk menunggu detik-detik itu. Piring sudah tersusun, gelas sudah berembun, doa-doa dipanjatkan dengan setengah hati, karna separuh lainnya sibuk dengan aroma makanan yang memanggil.
Namun, setelah suapan pertama, setelah tegukan pelepas dahaga, maghrib tak lagi jadi pusat perhatian. Ia hadir dengan gegap gempita, tapi setelahnya, ia hanya bayangan yang perlahan memudar.
Jika aku jadi maghrib, apakah aku akan merasa bangga atau justru sedih? Aku yang dinanti dengan penuh harap, hanya untuk segera ditinggalkan. Aku datang sebagai cahaya, tapi setelah menyinari, aku dilupakan.
Maghrib, dalam dirinya, adalah refleksi dari kehidupan manusia. Kita selalu menunggu sesuatu, keberhasilan, cinta, kesempatan. Tapi setelah itu tiba, kita sering tak memberi ruang untuk benar-benar menghargainya. Kita berpindah ke harapan berikutnya, seperti pengendara yang buru-buru meninggalkan lampu merah setelah hijau menyala.
Padahal, barangkali maghrib bukan sekadar tanda boleh makan. Ia adalah perhentian. Sebuah pengingat bahwa ada keindahan dalam jeda, bahwa setiap momen yang datang layak direnungi sebelum kita melanjutkan perjalanan.
Maka, andai aku jadi magrib, aku ingin bertanya
Setelah menungguku begitu lama, apa kau benar-benar hadir bersamaku, atau hanya sekadar lewat?
PENULIS

AB Asmaradana, seorang teaterawan Indonesia tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya. Pendiri dan mengelola ruang seni Ngaos Art di Tasikmalaya, Jawabarat dan Lanjog Art Festival (LAF) di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.