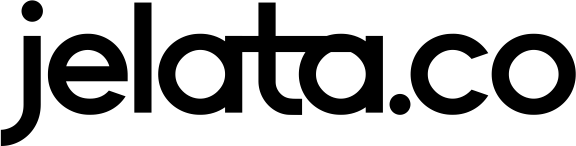Peluru-peluru Dablo, Senja anti Mainstream dan Menggiring Bulan ke Dalam Rumah
Dablo berlari ke atas sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, mengacung-acungkan senapan berlaras panjang tepat di depan warung tambal ban, sambil terus menembak. Ia lalu bergegas turun menyadari berada di atas kap mobil justru menempatkan dirinya sebagai target empuk peluru, ia pun turun dan bersembunyi di balik mobil. Kepalanya muncul lagi, matanya nyalang memandang sekitar, memastikan tidak ada musuh mengintai. Rupanya ia sedikit merasa lega telah berhasil melepaskan diri dari kejaran. Si empunya warung tambal ban, seorang lelaki seusia ayah saya, tampak santai melihat Dablo tergopoh-gopoh berlari menjauhi mobil, menyeberang jalan, menuju panggung yang sebenarnya.
Dablo memulai pertunjukan berdurasi dua puluh lima menitnya tanpa penonton menyadarinya. Ia mengendap-endap di sela penonton seperti seorang gerilyawan, berdiri di balik pohon seolah tubuhnya terlindung dengan baik. Ia pun memainkan lakon kecil berjudul “Seperti Biasanya” dan di sepanjang acara penonton terlihat terhibur sekali.
Sebagai seorang pemain pantomim gerak tubuhnya bisa dikatakan sempurna, menguasai teknik bermain pantomim klasik, menunjukkan jam terbangnya yang sudah tinggi. Tidak hanya area duduk penonton, halaman Warmo, dan lapangan parkir, pemain pantomim asal Bandung Dede Permana atau yang mempopulerkan dirinya dengan nama Dablo ini menggunakan tiap titik yang memungkinkan untuk pertunjukan, bahkan ia berlari menyeberang jalan dan naik ke kap mobil, setelah itu ia berlari lagi menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan. Saya dan beberapa orang penonton mengikutinya, bukan karena mengkhawatirkan keselamatannya; saya hanya ingin menyaksikan mimik seriusnya dengan lebih dekat ketika ia melakukan adegan yang bisa dibilang penuh humor tersebut. Berpindah ke area samping warung Dablo melanjutkan. Segala kegaduhannya ternyata hanya mimpi. Ia lalu terbangun, dan melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti umumnya pertunjukan pantomim klasik Dablo menunjukkan satu demi satu adegan keseharian dengan detail; bangun tidur, berwudlu, sholat, bercocok tanam, memanen hasil, dan menjualnya ke tengkulak.
Meski pertunjukan ini dilangsungkan pada 15 November 2018, saya menuliskannya pada bulan Januari 2019. Awal tahun yang lumayan berat. Seperti biasa, kepala saya penuh tenggat waktu pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kesenian. Biasanya, saya akan membuka media sosial dengan harapan mendapatkan hiburan; sekadar meme, gambar kucing, atau video panda, tapi saya harus bersabar setidaknya sampai tempat kerja terlebih dahulu baru saya membuka ponsel. Saya pun berusaha mencari hal lain yang layak dipikirkan selain tenggat waktu pekerjaan. Waktu itu saya teringat perkataan satu dua orang penonton kaya referensi pada pertunjukan Dablo malam itu. Saya lupa perkataannya persisnya–sebenarnya saya merekamnya tapi mungkin saya menghapusnya lagi karena memori ponsel saya terlalu penuh. Pada intinya ia mengatakan kalau dua pertunjukan malam itu, termasuk pertunjukan Dablo, dinilai belum bisa meruang dengan baik; masih melakukan eksplorasi yang begitu-begitu saja, kurang nekat dan tidak spektakuler. Padahal, katanya, Tunggak Semi, tajuk pekan pantomim yang dihelat Bengkel Mime Theater ini, mengoarkan tema “melirik ruang-ruang kecil yang simpatik”.
Meski saya terkagum pada lontaran kritik karena seingat saya bahasanya begitu rapi tersebut, saya tidak serta merta setuju. Saya mungkin terkesan lebih miskin referensi karena saya cukup puas dengan apa yang saya tonton waktu itu, dan saya tidak bisa membandingkannya dengan pertunjukkan lain yang dinilai olehnya telah meruang dengan lebih baik. Sejujurnya saya lama kelamaan cukup kepikiran dengan kritik tersebut -sebenarnya saya memang suka sedih menghadapi kritik karena saya sendiri paham bagaimana susah payahnya membuat pertunjukan-. Yang mengganggu pikiran saya bukan di ruang seperti apa yang seharusnya dipilih oleh seorang pemain, tapi lebih pada bagaimana pemain menerjemahkan kata “meruang” itu sendiri. Apakah meruang hanya selalu berkenaan dengan latar; tempat dan benda-benda fisik saja; bangku, pohon, jalan, sungai, balok kayu, lapangan, meja kursi, mobil lewat, sawah? Apa bedanya menggunakan balok kayu buatan di atas panggung dengan ranting pohon di pinggir jalan? Apa bedanya berenang bolak-balik di sungai dengan pura-pura berenang di hanya satu titik? Tidakkah pantomim justru tidak mengindahkan tempat karena ia lah yang menciptakan tempat itu? Waktu mencari tempat parkir motor saya buru-buru menarik kesimpulan: selama ruang hanya soal sesuatu yang sifatnya fisik, maka di mana pun pertunjukan diadakan tidak akan ada bedanya. Saya lalu jadi lebih bertanya-tanya lagi, jika meruang tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang fisik, lalu hal-hal nonfisik apa yang seharusnya ada di sana?
Setelah memindahkan motor-motor lain supaya motor saya mendapat tempat saya duduk di jok dan membuka ponsel karena tidak berhenti berbunyi. Tapi alih-alih membaca pesan-pesan di grup kerjaan saya malah nyasar—dengan sengaja—ke sebuah ruang yang pintunya bergambar burung biru kecil. Saya membuka aplikasi tersebut dan kaget betapa orang-orang penuh energi memenuhi linimasa. Berbeda dengan dunia sunyi yang diagungkan oleh seni pantomim, meski tidak ada bunyi semua orang bersuara secara verbal. Sepertinya kegelisahan mereka sudah pada puncaknya, kata-kata mencari celah, seperti air mengucur dari tempayan bocor saja. Semua orang mencari perhatian, semua orang ingin dipahami dan didengarkan. Semua orang mencari panggung. Kemudian saya berpikir, twitter bisa disebut sebagai sebuah ruang dan karakter penonton atau netizen -atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai warganet- bisa dipelajari bahkan dikelompokkan sesuai kebutuhan. Seperti rumus komunikasi klasik “ada yang menyampaikan dan ada yang menerima pesan”, aplikasi twitter dan media sosial lainnya sebenarnya adalah contoh ruang alternatif jika kita meletakkan pemahaman bahwa ruang adalah tempat berkomunikasi, dan ruang dapat berupa panggung atau tempat pengganti panggung: kedai kopi, trotoar, sawah, jembatan, bahkan atas pohon sekali pun jika memungkinkan. Persoalannya adalah: untuk bisa disebut ruang, si pembawa pesan, dalam hal ini pemain, harus memasukkan penonton ke dalam pertunjukkannya, bukan secara literal, tapi memahami siapa mereka, dan apa kebutuhannya untuk mau mendengarkan pesannya.
Saya kira, ketika membicarakan ruang kita seringkali melupakan bahwa penonton adalah bagian darinya. Dalam ruang terdapat interaksi penonton dengan pemain, dan interaksi di sini bukan melulu diujudkan dengan dialog -baik dengan atau tanpa kata-. Interaksi di sini adalah pemahaman pemain pada apa yang dibutuhkan (sebelum akhirnya paham pada apa yang diinginkan) oleh penonton. Menurut pengamatan saya penonton terbagi menjadi dua, mereka yang menjadi host audience yaitu penonton yang didatangi oleh pertunjukan, selebihnya adalah guest audience, yaitu penonton yang mendatangi pertunjukan, yang biasanya sudah mempunyai bekal referensi. Di Warmo malam itu ada kedua jenis penonton tersebut di atas. Dan saya, meski adalah guest audience, sudah lebih dulu mencoba memahami kebutuhan dan menempatkan diri sebagai host audience karena tempat seperti Warmo adalah tempat yang juga sering saya kunjungi. Saya sendiri membayangkan saya tengah duduk di sebuah warung kopi bertukar kabar dengan teman atau mengetik laporan, lalu menikmati satu nomor pendek pantomim. Dan tentu saja, sebagai penikmat rutinitas saya tidak ingin pertunjukan tersebut terlalu spektakuler dan sulit dimengerti karena tujuan saya berada di warung kopi tersebut adalah mendapatkan kenyamanan. Dan jika memang ingin mengganggu kenyamanan saya dan menawari saya sesuatu, sebagai urban muda saya minta tolong -dengan egois- sajikanlah sesuatu yang apik, menggugah, namun relatable af!
Kembali pada pertunjukan pantomim di malam itu.
Salah seorang penonton sempat saya ajak bercakap seusai pertunjukan, dan katanya, dia hanya pernah menonton unggahan video dan foto di facebook sebelum akhirnya menyaksikan aksi pantomim dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang bahkan tidak berencana untuk menonton pertunjukan apa pun, karena ruang yang dipakai malam itu relatif tidak lazim untuk sebuah pertunjukan pantomim. Selain karena pengunjungnya yang biasanya anak-anak yang lebih dekat dengan dunia literasi, juga karena warung mojok atau Warmo letaknya relatif jauh di utara -kata anak selatan-; area yang lumayan jarang disentuh jenis kesenian pantomim, seni gerak bisu yang nyaris tidak pernah dikenal lagi oleh masyarakat luas. Tidak kurang dari lima puluh orang orang menjadi penonton malam itu dan lebih dari separuhnya saya yakin belum pernah menonton pertunjukan pantomim sebelumnya, terlebih, pertunjukan pantomim dengan panggung yang demikian luas, seluas kehendak pemainnya.
Melihat raut muka penonton waktu itu saya cukup merasa puas. Buat saya, pertunjukan malam itu sudah menyentuh penonton dengan baik. Dablo menembakkan senapannya ke berbagai arah dan tentu saja sebagian dari peluru-peluru itu ada yang mengenai sasaran.
Dari sebuah ruang yang dipenuhi remaja masa kini, saya berpindah dan mendamparkan diri di sebuah studio wayang di jalan Taman Siswa Yogyakarta. Pertunjukan dihelat pada tanggal 18 November dan dimulai pada pukul 20.00.
Studio Wayang Ukur milik (alm) Ki Sukasman itu sebenarnya adalah tempat tinggal dan workshop/bengkel kerja miliknya yang kemudian didedikasikan oleh beliau menjadi sebuah museum. Rumah bergaya tradisional Jawa yang berada di tengah kampung dengan halaman yang ukurannya separuh dari lapangan voli itu berbentuk huruf L dengan dua pintu utama menghadap halaman. Sejak sore, anak-anak usia sekolah dasar sudah bermain di tempat tersebut, dan saya kira, memang di situlah tempat mereka biasa bermain sehari-harinya. Ide dari Tunggak Semi memakai tempat ini sebagai salah satu ruang alternatif pertunjukan adalah sebuah angin segar yang lain. Penonton yang hadir di ruang ini tentu saja berbeda dengan penonton di ruang-ruang lain, selain latar belakang juga lebih beragam kelompok usianya
Berbicara soal judul, sama halnya dengan Dede Dablo, Solo Mime Society dan Popo juga bersahaja sekali dalam membuat tajuk untuk pertujukannya.
Popo dengan Padang mBulan, Senja dipilih oleh Solo Mime Society sebagai judul. Lucunya, karena saya terlanjur membayangkan senja bermakna populer yang begitu-begitu saja, saya lumayan kaget ketika ternyata senja yang dimaksud oleh kelompok pantomim asal Solo ini adalah senja yang berbeda; senja yang merujuk pada usia, bukan sebuah sore berlatar langit oranye dan matahari terbenam separuh, meski senja-nya usia ini diturunkan juga maknanya dari senja populer andalan anak indie dan nyastra.
Kalau terlalu banyak memakai kata senja dalam menulis atau membuat status di media sosial, kita akan diolok sebagai anak indie atau nyastra, seolah keduanya buruk dan sama sekali tidak membanggakan. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Menjadi musisi atau setidaknya penikmat musik indie tentu saja membanggakan, apalagi menjadi penikmat atau penulis sastra. Yang diolok warganet sebenarnya adalah anak-anak yang sok mempunyai selera musik yang bagus sehingga hanya mendengarkan musik-musik non-populer yang biasanya diusung musikus indie dan sok nyastra hingga terlampau sering menuliskan kegalaun dalam puisi pendek dengan pilihan diksi yang itu-itu saja. Sialnya, senja yang pernah begitu indah dimaknai oleh Seno Gumira Ajidarma itu akhir-akhir ini menjadi diksi pilihan sejuta umat, saking disukainya. Sebagai snob sok keren saya menyayangkannya. Karena yang tadinya non-populer menjadi populer, dan sesuatu yang populer dianggap berkurang keindahannya. Kenapa bisa begitu? Mungkin akan saya bahas lain waktu.
Tapi seperti yang saya singgung di paragraf sebelumnya, Solo Mime Society menarik kata senja menjauh dari hiruk pikuk itu. Senja miliknya adalah senja yang tidak kalah indahnya dengan senja milik SGA dalam cerita pendeknya. Beranjak dari senja, mari menuju pada suasana malam itu, suasana yang diam-diam saya rindukan karena mengingatkan saya pada masa kecil; berkumpul dengan teman-teman di bawah sinar bulan di halaman rumah, bermain ular naga panjangnya atau jamuran. .
Saya duduk di salah satu tikar yang digelar, bergabung dengan masyarakat sekitar. Musik dengan gitar akustik diperdengarkan, suara penyanyi perempuan merdu menghangatkan. Seorang kakek berjalan tertatih seperti tengah mencari-cari seseorang. Ia menyimpan potret seseorang dalam sakunya lalu ia bertanya pada beberapa orang yang ditemuinya -penonton- apakah seseorang itu pernah dijumpainya. Kesepian dan keputusasaan tergambar di rautnya. Ia kemudian bertemu dengan teman seusianya yang tuna nutra, juga satu temannya lagi yang sama kesepiannya dengan dirinya. Lalu acara bully-membully ala teman dekat pun terjadi di sepanjang pertunjukan.
Tiga orang berusia senja yang mempunyai karakter dan latar belakang beragam dan satu orang suster genit yang diperankan oleh seorang lelaki perawat mereka menjadi satu komposisi klasik jika ingin meramu sebuah drama komedi. Mereka berkomunikasi dan bercanda dengan cara yang khas, seperti yang kita kenal dengan istilah guyon batur alias guyon masyarakat kelas bawah. Meksi terkesan kampungan, di saat-saat tertentu humor-humor seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan, tanpa berwacana macam-macam, yang penting hati senang dan terhibur. Tapi meski dibalut humor, cerita tentang tiga lelaki berusia senja di sebuah panti wreda diusung oleh Solo Mime Society dengan lumayan menyentuh. Terlepas dari tema meruang yang mereka terjemahkan dengan lugas, jalan cerita Senja sangat gamblang hampir tanpa simbol-simbol. Mereka memakai teras depan dan halaman Wayang Ukur sebagai latar, dan bermain-main dengan benda-benda di sekitarnya: sapu, pohon belimbing wuluh, tanaman hias, jendela, bahkan sandal penonton yang terserak seperti di halaman masjid waktu Jumatan. Suasana yang terbangun di ruang ini begitu akrab. Setidaknya ada lima puluh orang penonton yang terdiri dari penonton tamu atau guest audience dan masyarakat sekitar atau host audience yang menikmati empatpuluh menit suguhan itu dengan tawa dan sukacita.
Sampai cerita berakhir saya lupa bahwa yang saya tonton adalah sebuah pertunjukan pantomim. Barangkali karena kode-kode yang sering dibawa pantomim minim sekali saya jumpai dalam Senja. Riasan wajahnya putih tapi tidak terlampau tebal, tidak ada kaus bergaris atau suspender, terlebih topi. Mereka pun kadang meggunakan barang-barang berujud seperti sapu misalnya. Beberapa adegan dengan pantomim klasik yang umum seperti menimba tetap disuguhkan, dan sepanjang pertunjukan tetap tanpa bicara. Pertunjukannya cukup panjang, ceritanya pun runut, alur dan naskahnya tampaknya ditulis dengan baik.
Berbeda dengan Solo Mime Society, Yustinus Popo yang biasa dipanggil Popo bermain lebih dulu dengan lebih puitik. Ia menggabungkan yang realis dengan surealis. Pertunjukan sepanjang kira-kira dua puluh lima menit itu dimulai dari dalam rumah hingga penonton yang sudah nyaman dengan duduk lesehan dan berharap disuguhi sesuatu dari teras depannya, dengan ragu berdiri dan mendekat ke sisi yang lain setelah menyadari mereka telah kehilangan beberapa menit. Mereka berdesakan untuk mengintip dari balik jendela berteralis kayu, ingin tahu apa yang sedang berlangsung di dalam.
Terlihat Popo sedang duduk dan memainkan wayang-wayangnya, sambil mengenang-ngenang sesuatu. Tanpa mengetahui dengan sadar bahwa apa yang sedang disaksikan adalah sebuah pertunjukan pantomim, saya kira penonton tak akan dapat menemukan bedanya dengan sebuah pertunjukan teater. Kostum, rias, dan gerakan Popo sangat realis dan tidak tertangkap jelas gerak patah atau mimik wajah khas pantomim. Baru setelah ia berjalan keluar menuju halaman untuk menarik dan memindahkan bulan ke dalam rumah, gerakan pantomim terlihat dengan jelas.
Saya melihat penonton baik dari maupun yang bukan dari masyarakat sekitar antusias terhadap apa yang ditawarkan oleh kedua penampil ini. Pada pertunjukan Popo misalnya, penonton ikut merasakan beratnya perjuangan Popo yang tampak dari gerak tubuhnya, menggiring bulan ke dalam rumah kemudian membantunya dengan sukarela. Keasyikan Popo menarik bulan dari langit pun membuat beberapa anak penasaran atas “apa yang tengah terjadi” di atas sana.
Baik Dede Dablo, Popo, maupun Solo Mime Society bagi saya telah melugaskan gagasan ruang dengan baik melalui caranya masing-masing dengan bumbu-bumbu humor. Sampai saat ini saya sebenarnya masih mempertanyakan apakah humor harus selalu menjadi bumbu utama pertunjukan pantomim, tapi meski demikian suguhan dengan bumbu apa pun, selama ia menyampaikan pesan dan pesan itu diterima dengan baik oleh penontonnya, maka ruang telah terbentuk, dan setengah dari misinya telah tercapai. Warmo dan Studio Wayang Ukur telah menjelma menjadi sebuah ruang yang penuh kehangatan, setidaknya untuk saya, penonton tamu miskin referensi yang merasa diterima oleh tuan rumahnya.
Penulis

Tiaswening Maharsi, penulis fiksi, pemain pantomim, dan pekerja swasta, tinggal di Yogyakarta.