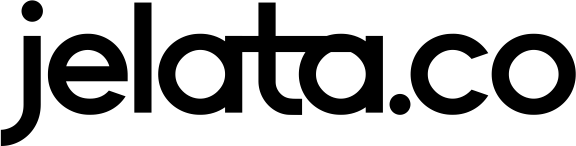Memori itu masih terngiang hingga kini. Ketika aku masih kecil, bapak sering mengajakku ke kota dengan sepeda jengki plantangan. Aku duduk di depan, sementara bapak mengayuh pelan. Sepanjang jalan, ia menunjuk bangunan demi bangunan yang kami lewati, seolah sedang membacakan peta ingatan. Kami berkeliling Malioboro, menyusuri ruas-ruas jalan bersejarah, tertawa kecil melihat kuda-kuda menarik andong.
Sebelum pulang, bapak tak pernah lupa mengajakku mampir ke warung soto langganannya di Ngadiwinatan, kampung di sebelah barat Malioboro. Dan setiap kali kami mau pulang, melewati palang pintu kereta api, tiap kereta melintas ia akan berkata, “ja jajan, aja jajan,” sambil menirukan suara kereta yang meraung lewat. Kalimat sederhana itu ternyata menyimpan pesan panjang: jangan boros, jangan konsumtif. Baru ketika dewasa aku sungguh memahaminya.
Bapak pula yang mengajarkanku agar tidak mudah berutang, agar mengelola uang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ingatan lain: aku sering diajak bapak melakukan pelayanan ke rumah-rumah. Tak banyak detail yang bisa kuingat, namun kehadirannya selalu terasa—tenang, setia, dan penuh tanggung jawab.
Bapak adalah pribadi yang pendiam dan pekerja keras. Dari desa kecil di lereng Gunung Merbabu ia merantau sejak muda demi menggapai cita-citanya. Bapak pernah ditugaskan ke pelosok hutan—wilayah yang terpencil, jauh dari denyut peradaban. Dalam salah satu lawatannya, ia singgah di sebuah desa kecil milik suku pedalaman. Suasananya masih ramai, seolah baru saja selesai sebuah upacara adat. Asap tembakau lokal mengepul pelan di udara, dilinting rapi dengan salung, menyatu dengan aroma tanah basah dan kayu tua.
Di tengah lingkaran para tetua adat, kepala suku menyambut bapak dengan segelas kopi. Tatapannya tajam namun penuh selidik, lalu ia bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangan bapak ke wilayah mereka. Bapak menerima gelas itu dengan tenang. Namun sebelum menyesapnya, ia menundukkan kepala, memejamkan mata, dan memanjatkan doa atas kopi yang dihidangkan. Belum lama doa itu usai, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Gelas kopi di tangannya tiba-tiba retak, lalu pecah terbelah menjadi dua. Waktu seakan berhenti. Kepala suku dan para tetua adat terperanjat; sorot mata mereka berubah, antara heran, takut, dan hormat. Dengan suara tertahan, mereka bertanya: doa apa yang baru saja bapak panjatkan?

Tak banyak yang dijelaskan. Namun sejak saat itu, suasana berubah. Kecurigaan perlahan luruh, digantikan penerimaan. Bapak akhirnya diterima dengan baik oleh komunitas suku pedalaman tersebut. Hubungan yang terjalin bukan sekadar urusan tugas, melainkan ikatan saling percaya—antara keyakinan, adat, dan kemanusiaan.Hingga tiba waktunya bapak kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan tugasnya, hubungan baik itu tetap terjaga, menjadi kisah yang kelak dikenang sebagai perjumpaan sunyi antara iman dan kearifan lokal, di jantung hutan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia.
Setelah berada di kota budaya Yogyakarta, jelas dalam ingatanku saat pertama kali beliau membeli sepeda motor bebek Kawasaki Binter Joy. Keluarga sederhana kami menyambutnya dengan sukacita—motor pertama yang kami miliki. Motor itu menemani kami cukup lama, hingga aku duduk di bangku sekolah menengah pertama.
Dengan motor itu pula aku pernah terperosok masuk comberan saat belajar berkendara, karena terlalu bersemangat menarik gas.
Setelah ekonomi keluarga membaik, sepeda motor bapak pun berganti dengan motor keluaran tahun yang lebih muda. Bahkan, beliau selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemputku ke sekolah. Ketika aku beranjak dewasa, meski aku kerap memiliki jalan pemikiran yang berbeda, kasih sayang itu tak pernah berkurang sedikit pun. Sebagai anaknya, aku berupaya agar tidak merepotkan bapak—terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhanku saat menapaki dunia seni.
Sejak tahun 2017, bapak jatuh sakit akibat stroke. Ia terjatuh di kamar mandi, lalu berteriak memanggil namaku. Aku berlari menolongnya, jantungku berdegup tak karuan, lalu membawanya ke rumah sakit dengan menumpang mobil Pak Yan. Dalam perjalanan itu, aku mencoba tampak tenang, padahal di dalam dada ada ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
Setelah seminggu dirawat, bapak diperbolehkan pulang dengan obat jalan dan kewajiban kontrol rutin. Di rumah, bicaranya tidak sedikit pun pelo; artikulasinya justru sangat jelas. Kejernihan suaranya membuatku gamang—antara bersyukur dan takut—seolah penyakit itu belum benar-benar pergi, hanya bersembunyi, menunggu waktu.
Suatu sore ia berkata lirih, “Le, nek aku mati piye?” pertanyaan itu menghantam batinku. Ada dorongan untuk memeluknya, ada pula keinginan untuk menutup telinga dan berpura-pura tak mendengar. Namun yang keluar justru jawaban datar, setengah bercanda, “Mati ya disumet, Pak.” Aku menertawakan kata-kataku sendiri, sementara hatiku bergetar.
Canda itu adalah perisa palsu bagi rasa takutku sendiri. Aku ingin terlihat kuat di hadapannya, sebab aku tahu, jika aku runtuh, bapak akan semakin terpuruk. Padahal, di dalam diam, aku sedang belajar menerima satu kenyataan yang pahit: bahwa suatu hari nanti, aku harus siap kehilangan, meski belum siap untuk mengakuinya.
Aku memahami betapa terpuruknya perasaan beliau ketika menerima ujian itu. Bapak merasa tak lagi mampu berbuat banyak. Namun demikian, ia tak pernah lelah berjuang menggembalakan gereja yang dibangunnya dengan susah payah sejak tahun 1990.
Pada 8 Desember 2025, bertepatan dengan ulang tahun adikku, aku mengirimkan bunga, dupa, dan doa ke makamnya. Siang itu terasa hening dan teduh, seolah semesta ikut menyampaikan doa-doa yang kupanjatkan. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu mendekat ke makam adikku. Momen itu terekam oleh kamera yang kusiapkan sebagai kenangan—sebagai bukti sayangku untuknya. Kupu-kupu itu terbang perlahan, mengepakkan sayapnya, mengitari makam adikku, seakan membawa kabar dari dimensi lain.
Sejak hari itu, kondisi Bapak perlahan kian menurun, seakan tubuhnya mengikuti irama waktu yang telah ditentukan Tuhan. Sepulang menonton pembukaan pameran seni rupa, sesampainya di rumah suasana telah ramai oleh saudara yang berkumpul. Doa-doa mengalun lirih, memenuhi ruang dengan harapan dan kepasrahan. Dalam suasana yang khusyuk itu, Bapak meminta maaf kepada Ibu, kepadaku, dan adikku—sebuah pengakuan tulus, seolah ia tengah merapikan hatinya sebelum pulang.
Kami pun bergantian memohon maaf kepada Bapak, dengan air mata yang tak lagi mampu ditahan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai anak: belum sepenuhnya membahagiakan, belum sanggup memenuhi semua harapan. Namun di saat-saat itu, aku merasa Bapak telah memaafkan jauh sebelum kata-kata terucap.
Empat malam berturut-turut Bapak meminta ditemani. Ia ingin didoakan, dimohonkan ampunan atas dosa-dosanya. Malam-malam itu terasa seperti doa panjang yang tak terucap—sunyi, namun penuh makna. Dalam kelemahan tubuhnya, tampak kekuatan iman yang berserah sepenuhnya. Bapak mengajarkan kami arti menerima: bahwa hidup bukan tentang seberapa lama bertahan, melainkan seberapa ikhlas melepas.
Jumat Pon, 12 Desember 2025, dalam kondisi yang semakin lemah, Bapak meminta tubuhnya dibangunkan hingga posisi duduk. Tak lama kemudian, ia kembali berbaring. Denting jam terdengar lirih, seolah menandai batas antara dunia dan keabadian. Pada saat itulah Bapak mengembuskan napas terakhirnya—tenang, tanpa keluhan, seperti seseorang yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang.
Secara jasmani, kami semua tenggelam dalam duka dan kehilangan. Namun secara rohani, kami percaya tugas Bapak telah selesai. Ia telah menyelesaikan bagiannya di dunia yang fana ini, dan kini beristirahat dalam damai.
Natal tahun ini kali pertama tanpa Bapak. Di tengah cahaya lilin dan kidung malam kudus, aku belajar memaknai kehilangan. Bukan hanya tentang kelahiran Kristus, tetapi juga tentang pengharapan—kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal.
Penulis

MEUZ PRAST, Seorang Perupa muda yang aktif melukis dan berkegiatan seni rupa. Founder Kembang Jati Art House Yogyakarta.
Suka menulis puisi dan cerpen, juga aktif di komunitas Sastra Bulan Purnama. Mengajar Seni Lukis Di Ponpes Bumi Cendikia Yogyakarta, Sering menjadi Master of Ceremony (MC) diberbagai hajatan seni.