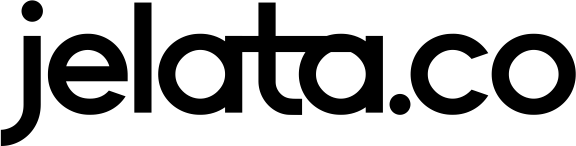Minangkabau sudah tidak aku temui dalam temuan-temuan peneliti barat yang dulu singgah dan menetap di kampungku. Aku hanya mendengar dari orang-orang tua kampung yang dulu menyebut, “dulu ada orang bule tinggal di sini dua tahun. Katanya peneliti. Tapi tidak tahu apa yang dia teliti”. Kampungku sekarang sudah berubah, tinggal di rumah sendiri yang hanya diisi ayah, ibu, dan beberapa orang anak. Anak laki-laki sudah tidak tidur di surau. Tidur di rumah ibunya dan syukurnya sudah dapat berbaring di kamar sendiri. Perempuan sudah pandai bersolek dan hilir-mudik bersama pacarnya. Tanpa harus takut dimarahi mamak karena “membuat” malu. Tak ada lagi macam hayati, yang dipaksa kawin mamaknya karena alasan harta. Tak kutemui macam Siti Nurbaya yang diperistri laki-laki yang bau tanah. Tak kulihat lagi satu rumah gadang diisi puluhan orang. Tak tampak lagi ninik mamak yang punya kuasa penuh namun keok di rumah istrinya. Tak tersisa perempuan yang tabah di poligami. Tapi, hanya satu yang tersisa, perempuan mandiri sejak dalam pikiran. Itulah Amak, dan dua orang adikku, Syaifah dan Halimah.
Tidak lagi kutemukan apa yang dikhutbahkan cristin dobbin dalam bukunya, orasi elizabet dalam tulisannya, dan sejumlah penulis lain yang tak berdarah minang. Begitu juga dengan putra daerah, seperti muhammad rajab, yang membahas sitem matrillineal, hilang ditelan bumi. Mungkin sudah hangus terbakar kerak bumi, pikirku. Mungkin juga disembunyikan urang bunian ke dada gunung marapi. Atau dibawa merantau oleh urang kubu yang -konon katanya- memiliki hubungan kerabat dengan orang minangkabau. Tak jelas. Benar-benar tak jelas.
Di rumah yang sudah semi permanen, cat kuning yang mulai pudar, dan retak di dinding depan karena gempa 2009, aku tinggal. Bersama Abak, Amak, dan dua orang adekku yang sudah beranjak remaja. Mereka perempuan yang sama seperti Amak, mandiri. Mau mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan tanpa perlu ada perintah. Mereka tak segan mengambil pakan ternak ketika abak sakit. Memikulnya bergantian sampai kendang sapi. Menempuh jarak lebih kurang 1.5 KM. “hidup yang ditumpangi, harus berani berkorban. Kalau Abak sudah tak ada, masih ada kemandirian yang menjadi bekal”. Ungkap Halimah, adekku paling kecil.
Pernah suatu hari Abak sakit dan harus dirawat di rumah sakit daerah. Rumah sakit itu lumayan jauh dari rumah. jangankan mobil, motor saja tidak ada untuk mengantar Abak. Untung ada Datuak Gindo Tamamek yang baik mau mengantar Abak. Saat itu jua, Syaifah sedang sakit juga. Mau tidak mau, Amak harus menjaga Abak di rumah sakit. Sementara Halimah harus menjaga Syaifah di rumah. Pekerjaanku sebagai pegawai di kedai orang, mengharuskan untuk tidak mengucapkan libur, sekalipun berbagai alasan yang logis sudah kuutarakan. Walhasil, Halimah lah yang harus menjaga Syaifah dan mengambil pakan ternak agar sapi tidak melenguh sore hari karena kelaparan.
“tak apa dik?”
“dengan Ikhlas awak lakukan, Da.”
“bagaimana nanti kalau sakit?”
“semoga saja keadaan lekas membaik.”
Tidak ada penyesalan terpantul dari kata-katanya. Raut wajahnya teduh, seperti Rohana Kudus yang tabah memperjuangkan hak nya dan hak Perempuan Minangkabau lainnya. walaupun badannya kecil, tak sampai 160 cm, tetapi ketegarannya melebihi usianya. Kedewasaannya memang terpancar dari sosok Abak, yang tak pernah mengeluh menghidupi keluarga kecilnya. Dalam rentang umurku yang akan menginjak 24 tahun, belum pernah sepercik kekecewaan keluar dari mulut Abak. Kepasrahaan Abak menjalani hidup membawa aliran kebahagiaan yang deras. Singgah di hati istri, dan anak-anaknya tercinta. “Tidak perlu kalian menjadi PNS. Yang penting jadi “orang” saja bagi Abak sudah cukup.” Ungkapnya suatu kali.
Malam hari aku bergantian dengan Amak menjaga Abak. Biar amak bisa istirahat dan menemani Halimah di rumah. Tapi bukannya istirahat, Amak malah memasak masakan kesukaan Abak, samba lado itiak. “biar Abak lekas membaik. Bisa pulang dan merawat anaknya yang tengah sakit juga.” Ungkap amak kepada Syaifah. Namun, masakan itu tak jadi dimakan Abak, karena Abak telah dipanggil Tuhan ketika suara ngaji masih berkumandang, pertanda waktu subuh sedikit lagi datang.
Di hari itu, tak sedikitpun air mata Amak jatuh. Tidak berteriak-teriak, atau histeris mendengar kematian suaminya. Mungkin ia tidak ingin terlihat lemah, ataupun tidak ingin menambah kesedihan terhadap dua putrinya yang meringkuk sambil menahan tangis dan kesedihan. Mungkin juga tak ingin melihat aku sedih. Banyak kemungkinan. Tapi kemudian aku tahu, Amak tak ingin menangisi kepergian Abak yang indah. “orang yang meninggal hari jumat, akan terlepas dari azab kubur”. Begitu cerita Amak yang disampaikan Etek Bainah kepadaku.
Amak tak pernah menyuruh anaknya karena takut merepotkan. Orang tua mana yang rela jalan kaki 5 KM karena tak tega membangunkan anaknya yang tengah terlelap. Mungkin Amak saja yang demikian. Karena uang untuk naik ojek tak cukup. Sekedar pembeli ikan asin dan seperempat cabe untuk mengisi lambung keluargaku ke depan. Gajiku bulan ini hanya untuk membayar kredit, pembeli kursi tamu menyambut lebaran nanti, sebagaimana yang dari dulu Amak cita-citakan. “Ingin benar Amak ada kursi di rumah kita, Nak. Kalau ada tamu yang datang, tidak bersela lagi di atas lantai yang dingin.” Katanya satu hari ketika menyabit padi di sawah Etek.
Tidak dimana-mana, keluarga yang miskin akan menjadi kaum marginal ketika acara perkumpulan keluarga besar. Tampak dari luar saja dihormati, namun ada ghibah yang menjajal cerita kepedihan hidup keluarga yang miskin di bilik-bilik kecil perbincangan. Bahkan orang yang dianggap memiliki akal budi sekalipun pernah masuk ke bilik kecil itu. Amak, aku, dan dua adekku selalu menjadi topik hangat bagi keluarga besar. Mereka menelanjangi kami, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki seperti ditelanjangi. Jika Amak duduk dekat mereka, mereka akan menggeser pantatnya, menjauh dari Amak. Namun keteguhan hati Perempuan yang aku pinjam rahimnya itu begitu tabah. Tak ada kemarahan. Tak ada bantahan. Bahkan tak ada perbicangan bahwa ia dihina sedemikian kejam setelah kembali dari kumpul keluarga besar.
“Kau suruh Amakmu bersuami lagi. Mungkin kehidupan kalian ada yang menjamin.” Saran Mamak kepadaku. Mamak, adek laki-laki Amak itu satu-satunya keluarga yang prihatin kepada keluarga kami. Namun sarannya itu sangat menusuk hati. Dia mengira bahwa setelah kematian Abak, hidup kami makin sengsara. Salah. Dia salah besar. Kami hidup seperti biasa. Ada aliran kebahagian yang masih dialirkan Abak dari surga. Keyakinan itu yang membuat kami senantiasa menjalani hidup, walaupun sebenarnya hal ini tidak kami inginkan. Pernyataan itu sungguh menyayat hati. Kalaupun dia keluarga kami, mengapa kata-kata pedih itu dia ucapkan dengan gamblang? Kalau dia benar seorang mamak, mengapa dengan begitu lantang dan telanjang kata-kata itu terucap? Kalau dia benar-benar tulus dan prihatin dengan kondisi kami, mengapa tidak dari dulu ia menolongku untuk melamar bekerja di KUA? Untung saja ucapan itu terlontar kepadaku saja. Kalau aku mengetahui dari Amak atau dari kedua adikku, akan ku buat dia menyusul Abak!
“Kalau mau menikah lagi, Mamak saja lah. Tidak usah terlalu baik, jika kata-kata Mamak membuatku naik darah!” balasku kemudian.
Sejak saat itu, tidak ada seorangpun yang benar-benar prihatin terhadap kami. Apakah aku menyesal? Tentu saja tidak. Lebih baik hidup begini. Menjalin ikatan dunsanak dengan orang yang benar-benar tulus, walaupun tidak sesuku. Tidak serumah gadang, namun sama-sama punya perasaan yang saling memerdekakan. Tidak sepayung, namun sama-sama menguatkan untuk berjalan di ribuan titik hujan. Salah satunya, tetangg belakang rumahku, Uwo Sari.
Uwo Sari Perempuan yang benar-benar prihatin dengan kondisi kami. Tidak berani memberi nasehat, karena takut ucapannya akan menyinggung dan meluluhlantakkan ikatan saudara semanusia yang telah terjalin berkelindan. Hanya sering datang ke rumah dan selalu membawa singkong yang ia panen dari belakang rumahnya. “Untuk disantap malam-malam. Selain sehat, juga hemat. Hehehe.” Selalu begitu. Menghadirkan gelak disetiap pembicaraannya adalah khas Perempuan tua itu. Aku yakin ini adalah siasat agar kami tidak merasa dihinakan ketika diberi. Aku banyak belajar dari Uwo Sari. Salah satunya adalah tertawa ringan sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicara.
“Uda, pulanglah sebentar!”
“Kenapa?”
“Mamak mengamuk di belakang rumah?”
“kenapa orang itu?”
“Dia memaki-maki Amak dan Uwo Sari”
Mendengar dua guru hidupku dijadikan bak binatang, aku langsung pulang. Tanpa pamit atau permisi kepada boss, warung langsung ku tutup. Biarlah. Kalau dipecat, nanti cari pekerjaan lain.
“Berani Waang memaki Amak Den, Anjiang!” Tanpa salam dan permisi, kepalan tanganku langsung tepat melesat ke pelipis bajingan itu. Tidak peduli lagi aku dengan hukum negara, hukum adat, atau hukum agama. Itu urusan belakangan saja. Jika nanti aku ditanya polisi kenapa aku memukul bajingan itu, akan kujawab saja dengan pertanyaan; “Tindakan apa yang akan bapak lakukan jika ibu Bapak dihina didepan umum?” dan jika aku ditanya oleh mamak-mamak ku yang lain, “kenapa kau meninju mamakmu sendiri?” akan kujawab juga dengan elegan dan berwibawa -melebihi wibawa ninik mamak itu- tanpa kesombongan; “jika mamak sudah dihinakan dengan pertanyaan belagu, kemudian amak saudara-saudara yang mulia ini dihina di depan banyak pasang mata, kira-kira pepatah nasehat atau golok yang akan saudara-saudara keluarkan?” dan jika aku ditanya nanti oleh Tuhan, kenapa aku melakukan kepada orang yang lebih tua, maka akan kujawab dengan penuh harap dan ampun “Mereka yang terbunuh karena menjaga harta saja dihukumi syahid oleh wakilMu -ya Rabb- di dunia, maka mungkinkah aku hanya pasrah dan diam jika harta paling berhargaku dihina sedemikian kejam?”
Dan benar saja, aku dihakimi di depan mahkamah rumah gadang gajah maaram itu. aku ditelanjangi dengan kata-kata yang tak tersudu di ayam, tak termakan di itik. Jika kata-kata itu diberikan kepada anjing buruan, tak sampai waktu semalam untuk mengantarkannya ke akhirat. Namun pantang menyerah dan sikap melawan sudah menjadi makananku sejak kecil, dari suapan Abak yang lembut tapi tegas, setiap kepalan kata dibombardir untuk menghajarku, sebesar paha gaja serangan balik untuk mereka. Sekuat yang mereka bisa, dua kali lipat aku campakkan lagi ke muka-muka mereka. Tapi kunci-an ada pada mereka. Aku diusir dan tidak dianggap lagi bagian dari mereka.
“Jangan membantah saja kau, Jalang!” Dubalang Tua itu menghardikku. Kekejamannya memang sudah terkenal dikalangan preman-preman Minangkabau, namun aku sudah tidak punya rasa takut. Sudah lama sifat jantan ini mau keluar. Dan aku yakin, tubuhnya yang tak lagi muda akan sangat mudah kuliukkan. Ajaran silek dari Guru Tuo Surau Subarang sangat ingin aku praktekkan lagi. Menjadikannya seperti samsak jerami, samsak yang biasa aku gunakan untuk latihan. Namun masih kutahan. “Balas kata dengan kata. Balas tangan dengan tangan” bisikku dalam hati.
Begitu juga dengan Mak Menan, yang harusnya menjadi penengah. Sebagai orang yang paling tua, aku berharap ia menjernihkan segala yang keruh, meringankan segala yang berat, tempat bertanya bagi yang bingung, tempat bercerita bagi musafir. Namun nyatanya tidak. Badan yang ringkuk dan suara yang tak lagi jernih, malah ikut jua memperkeruh. “Sudah tak ada lagi ikatan kita. Carilah dek Waang mamak lain yang bisa mengerti dengan keras kepalamu!” katanya sambil melempar kopiah yang warnanya sudah kekuningan ke arahku.
“Aku membela yang benar. Berdiri di jalan Tuhan. Menumpas segala hal yang tak elok. Abak mengajarkanku begitu. Pun jua tuan-tuan sekalian. Dulu tuan-tuan sangat marah kepadaku jika aku berjalan di arah yang kalian anggap salah. Sekarang, Amak ku dihina oleh bajingan itu….”
Asbak yang terbuang dari bambu itu melayang ke arahku. Untung saja kutungkas dengan cepat, hingga asbak berakhir di kepala Sati Rajo, Mamak yang sangat membenci keluargaku. Ia hanya diam. Tak berani untuk berkata. Sifatnya yang munafik itu tak berani ia tampakkan. Kalaupun berani, akan kutambahi tumpahan asbak ke kepalanya.
“Kalau tuan-tuan mengaku beradat, maka jangan memotong pembicaraan seorang yang tuan anggap hina ini.”
“Amakku dihina. Uwo Sari yang tak tahu apa-apa pun ikut terseret oleh mulut bajingan itu. Anak macam apa aku, jika hanya diam? Bagaimana dengan perasaan tuan-tuan jika orang yang tuan anggap guru dan orang yang paling sayang kepada tuan-tuang diperlakukan dengan keji? Apakah tuan-tuan hanya diam? Apakah tuan-tuan hanya menasehati dengan pepeatah-peitith yang sudah lapuk ditimpa hujan arus zaman itu? Atau kah tuan akan mengambil golok dan memancang leher orang yang menghina itu, lalu membuangnya di kubangan kerbau?”
Semua terdiam. Mungkin mereka mengamini. Mungkin juga mereka menyiapkan amunisi kata-kata dan menenunnya lalu memutarbalikkan fakta. Mungkin juga menyiapkan langkah untuk menghajarku bersama-sama. Aku tidak tahu. Yang jelas, mereka tidak berani lagi menatapku. Sorot mata mereka kemana-mana; ke tonggak tuo, ke jendela, ke gorden bilik yang belum tertutup, ke lampu yang mulai dikerubungi laron, ke tumpahan asbak yang masih berserakan puntung rokok di depan Sati Rajo.
“Keluar lah kau sekarang. Sebelum datang pukulan kami ke pangkal telingamu” ucap Monti Balang. Pernyataan pengecut. Tak pantas bagi seorang pemangku adat untuk menghajar manusia tak bersalah secara kolektif. Lebih baik buang saja gelar itu, atau surukkan ke lipatan selimut yang sudah koyak di bagian tepinya itu.
Aku keluar. Tak mengucap salam. Menatap satu-satu. Laki-laki, perempuan, di atas rumah itu sama saja bagiku sekarang. Tidak lain kumpulan pengecut. Sedangkan Mamak, adek ibuku, sudah terlanjur ketakutan melihatku, apalagi sejak tangkisan asbak tadi.
“Ada benarnya omongan anak tadi, Mak.”
“Tidak ada kebenaran yang lahir dari pembangkang!”
“Mohon izin mak. Ambo setuju dengan pendapat Monti barusan. Akan menyulitkan kita kedepannya.”
“Kesulitan seperti apa yang tergambar dalam pikiran, kau?”
“Mamak bayangkan saja. Adat yang terhampar seantero luhak nan tigo, di bawah agamo nan saandiko, berdinding dua gunung, berlembah nan tiada tara, siapa yang berhak untuk mengeluarkan seseorang dari sukunya?”
“Ambo yang bertanggung jawab”
“Pertanggungjawaban atas nama siapa? Kita sekarang tidak punya pangulu. Akan dicerca habis-habisan kita oleh ninik mamak yang lain. Jangan sampai oleh si jalang satu itu, kita dibantai habis, dibredeli dengan peluru pituah yang tajam, Mak”
“Tampaknya pengecut juga kamu rupanya”
“Bukan begitu, Mak. Apakah mamak sanggup melawan itu dengan “alua jo patuik”?
“Sabar dulu Jon, biarkan Mak Menan berpikir dulu. Kan dia orang hebat. Kita lihat, sejauh mana pikirannya berjalan.”
“Siapa lagi yang akan bertanya? Biar sekali jawab!”
“Jangan merasa pintar sendiri, Mak. Kita semua sama di sini. Jangan ‘babana surang’”
“Haram jalang kalian semua. Kenapa tidak dari tadi kalian begini? Kenapa setelah kepulangan anak jalang itu kalian seperti ini? Lupakah kalian siapa aku? MENAN! Yang menjadi pihak penengah urusan kalian selama ini! Sekarang ini balasan kalian?”
“Jangan berpanjang lebar, Mak. Jawab saja pertanyaan Saya tadi!”
“Kalau kalian tidak sanggup untuk menjawab ninik mamak itu, “indak kayu, janjang den kapiang, mah!”
“Dengan cara apa?”
“Tahan sebentar, Monti. Biarkan orang tua ini berpikir barang sejenak!”
“Kalau ditunggu jua, subuh juga selesainya ini!”
“Jangan sampai kita pula yang saling menapuk dada di sini!”
“OI, Mak Menan. Jawablah!”
“Dengan kepala dingin kita selesaikan, Tuan Monti!”
“Mengapa Mamak kau diam saja lagi, Dubalang?”
“Orang tua biasanya menerawang apa yang akan terjadi. Sekali aia besar, sekali tepian berubah, Nti.”
“Selama Gunung Marapi masih tegak menjulang tinggi, menghadap kepada luhak nan tiga, lareh nan dua, masih mencukam di bumi minangkabau, selama itu Menan, heiiii kalian denganr. MENAN!!!! Tidak akan kalah!”
“Caranya??”
“Selama Danau Singkarak, Danau Maninjau, masih berair, selama itu jua Menan tidak akan surut!”
“Dengan cara apa???”
“Selama Pagaruyung masih ber-raja, agama masih ber-malin, adat masih ber-datuk, selama itu jua Menan selalu menapak di jalan kemenangan!”
“sudahi saja pertemuan malam ini. Tidak ada yang dapat mufakat bertemu, tidak ada kata sepatah didapat. Menan menurut Menan, Ambo menurut Ambo, kalian menurut kalian saja. Ber-benar sendiri saja kita masing-masing!”
Begitu yang kudengar dari samping rumah gadang itu. Mereka tak tahu, bahwa Mak Menan sudah kutiupkan Sirompak. Dia hanya bisa meracau tanpa makna, berkicau tanpa penyelesaian. Hanya membisu untuk menjawab lurus-lurus saja, tuli mendengar segerobak pertanyaan dari orang-orang yang ragu. “Kabu allah kabu muhammad, kabu bagindo rasulullah….Assalamualaikum”, Aku beranjak senyap-senyap, ke belakang rumah gadang, membuang ludah ke sudut kiri rumah gadang itu, lalu berlari ke arah pulang.
Besoknya aku mendapat kabar Mak Menan kritis, setelah ditonjok belasan kali oleh Monti dan Jon Ladiang.
PENULIS
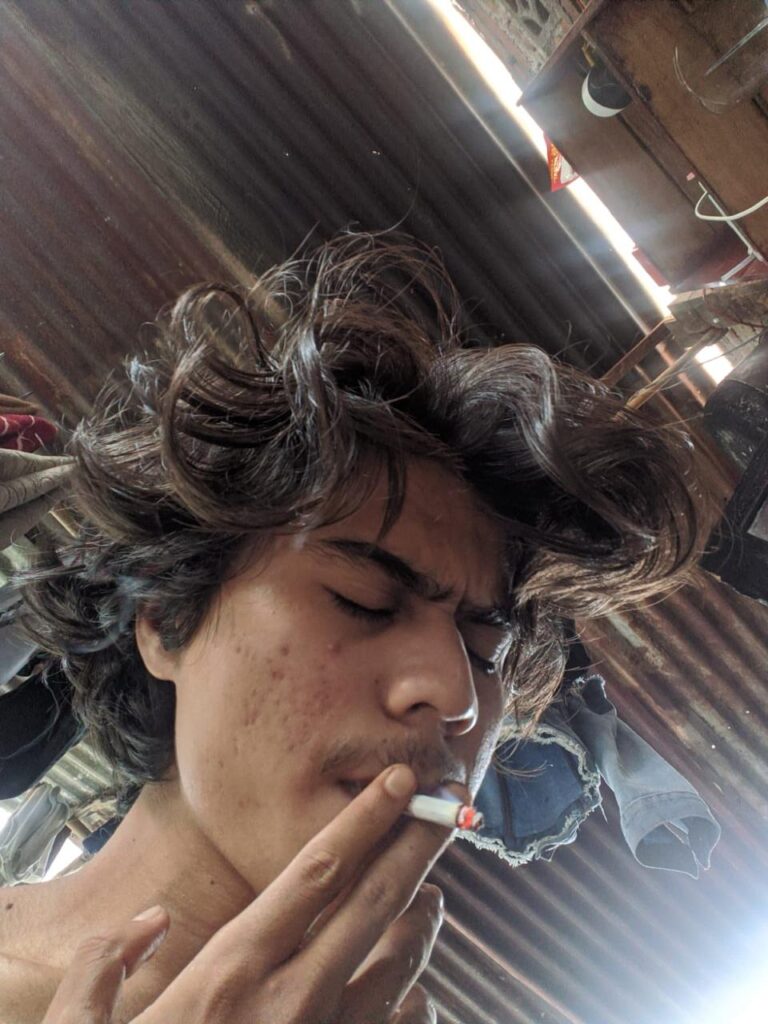
GERI SEPTIAN, adalah seorang nyeniman tak berktentuan. hidup ngelaju dari utara ke selatan jogja. menari-nari di sela-sela hujan..